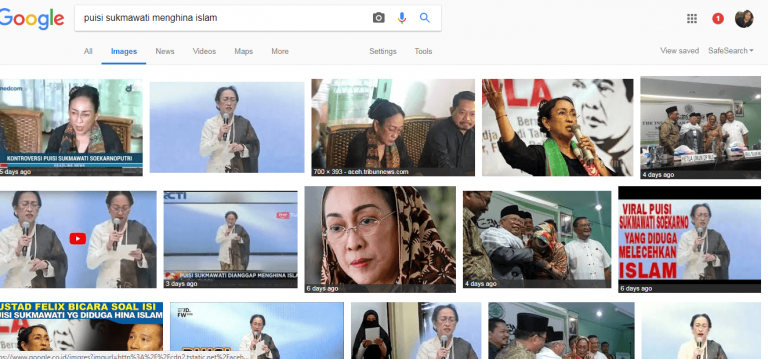
Sudah banyak yang bicara perihal Puisi Sukmawati tapi lupa satu hal penting: pertarungan ideologi yang melatarbelakangi kisruh ini. Sukmawati Soekarno Putri, dengan mengenakan kebaya ciptaannya, membacakan karya puisi ciptaannya juga dengan judul “Ibu Indonesia”. Dari empat paragraf puisi yang dibacakan tersebut, isi puisi tersebut memiliki keterkaitan dengan acara pagelaran busana tersebut. Tidak sekadar menautkan acara tersebut, Sukmawati kemudian memberikan konteks Islamisme yang menguat di ruang publik dan nasionalisme Indonesia yang direpresentasikan melalui sosok Ibu Indonesia.
Hal ini tercermin dari perbandingannya mengenai Syariat Islam dan Sari Konde Ibu Indonesia, Kidung Ibu Indonesia dan Alunan Azan. Sebagai sebuah ekspresi sekaligus kritik atas kekinian yang terjadi di Indonesia, tidak ada yang salah dalam puisi tersebut. Apalagi tema puisi tersebut memiliki kecocokan dengan acara pagelaran busana tersebut. Namun, puisi tersebut dianggap menjadi persoalan karena tiga hal. (Baca: Teks lengkap puisi Sukmawati yang dianggap hina islam)
Pertama, tahun-tahun politik (2018-2019). Pembicaraan mengenai Islam dan simbol-simbol yang terkait dengannya akan menjadi makanan empuk untuk para predator politik di tengah upaya membangun tiga stigma yang terus-menerus didengungkan sejak tahun 2014; Anti-Islam, Komunis dan Aseng. Pilkada DKI Jakarta tahun lalu menjadi cermin bagaimana pelintiran kebencian ini dimainkan dengan cukup efektif. Karena itu, cara-cara ini juga akan terus dimainkan hingga Pilpres 2019, di mana preseden ini mulai muncul, yaitu hoax kekerasan terhadap tokoh agama.
Kedua, menguatnya Islamisme ruang publik. Tumbangnya rejim Orde Baru tidak hanya menciptakan kekosongan kekuasaan, secara bersamaan, kondisi itu mengartikulasikan kelompok-kelompok Islam yang saat rejim Orde Baru berkuasa direpresi dan mengalami ketertindasan. Kegamangan dan kecemasan sejumlah kelompok kelas menengah di Indonesia terhadap modernitas, makin menguatkan Islamisme ruang publik.
Ketiga, menguatnya pengguna internet sekaligus sosial media di tengah tradisi literasi yang miskin. Alih-alih menjadi semakin lebih terbuka dan bijak seiring dengan berlimpahnya informasi, telepon genggam pintar dengan jaringan internet justru makin menguatkan pelbagai kebebalan atas kemalasan membaca. Sejumlah hoax yang menjadi viral dan kemudian membangkitkan emosi sentimen keagamaan, nasionalisme ataupun etnisitas merupakan cermin ini. Meskipun harus diakui rejim algoritma dalam internet, baik itu digunakan oleh Google dan media sosial makin memperkuat separitas di mana orang cenderung akan mendapatkan dan disuguhkan informasi atas pilihan-pilihan dan kecenderungan politiknya. Di tengah tiga faktor ini, puisi yang disampaikan oleh Sukmawati seperti memberikan umpan kepada para predator politik yang lapar dan di tengah fanatisme massa agama.
Meskipun demikian, harus diakui, penghadapan antara nasionalisme dan agama yang termuat dalam puisi Sukmawati itu memiliki lintasan sejarah yang panjang di Indonesia. Di sini, agensi-agensi perubahan yang memberikan kontribusi penting kehadiran Indonesia memiliki landasan ideologinya sendiri. Landasan ideologi dalam memberikan kontribusi pembentukan Indonesia ini juga yang menjadi perdebatan akademisi mengenai kontribusi signifikan para pendiri bangsa dan sejumlah pejuangnya yang seringkali dihapuskan dalam tradisi sejarah di Indonesia.
Bagi Ben Anderson (2003) terbentuknya imajinasi bangsa Indonesia itu dimediasi oleh kapitalisme media cetak, di mana orang-orang di negara jajahan merasa tersambung antara satu dengan yang lainnya, khususnya melalui bahasa dan praktik-praktik kebudayaan serta penindasan yang mereka alami. Dalam konteks Hindia-Belanda, imajinasi kebangsaan dengan melihat kebobrokan praktik-praktik kotor Kolonial Belanda ini justru muncul melalui selebaran, cerpen, dan novel yang ditulis oleh kelompok keturunan Tionghoa. Karya sastra semacam inilah yang dikategorikan sebagai batjaan liar (Farid dan Razib, 2008). Tidak berhenti di sini, kelompok-kelompok sekuler ini yang kemudian mendirikan sekolah, dunia pergerakan, dan pelatihan untuk kalangan kelas menengah atas.
Melalui kajian sejarah dan tulisan-tulisan cendikiawan Muslim yang belajar di Mesir dan Arab Saudi, Michael Laffan (2003) mengkritik temuan Ben. Ia mengungkapkan bahwa mereka inilah yang terus memperjuangkan Indonesia dan Asia Tenggara sebagai bagian dari imajinasi ummat. Kajian religius nasionalisme ini kemudian diteruskan oleh para sarjana Indonesianis sesudahnya, yaitu Kevin Fogg (2012) dan Chiara Formichi (2012). Menurut mereka berdua, imajinasi negara Islam dengan tumbuhnya nasionalisme religius Islam sudah ada sejak Kartosuwiryo khususnya sejak tahun 1950-an. Bahkan pada level akar rumput, banyak dari pejuang-pejuang Muslim pada fase revolusi 1945 menganggap bahwa apa yang mereka lakukan adalah bagian dari bentuk jihad dalam Islam. Meskipun ketika Indonesia merdeka, mereka mengalami kegagalan dalam mengusulkan Indonesia sebagai negara Islam.
Di sisi lain, ideologi komunis dalam pembentukan keindonesiaan tidak bisa dikesampingan. Selain partai tertua, PKI merupakan partai yang memiliki massa yang banyak. Tidak hanya menyebutkan nama Indonesia pertama kali dalam sebuah partai sebelum Indonesia terbentuk, partai ini juga terlibat dalam pergerakan nasional yang melakukan perlawanan terhadap imperialisme Belanda ketika itu. Selain PKI, partai Murba (Musyawarah Rakyat Banyak) dengan ideologi komunis, meskipun tidak dideklarasikan secara terbuka, menghimpun orang-orang kiri Indonesia yang memberikan kontribusi dalam Revolusi Indonesia saat itu.
Atas jasa-jasanya, orang komunis dan kiri ini mendapatkan penghargaan sebagai pahlawan nasional. Di antaranya yaitu, Alimin bin Prawirodirjo dan Tan Malaka. Namun, peristiwa 1965-1966 yang ditandai dengan pembunuhan massal atas mereka yang PKI dan di-PKI-kan serta stigma yang terkait dengannya saat rejim Orde Baru berkuasa, menghapus jejak itu semua.
Di tengah ketiadaan komunis, ideologi nasionalis dan agamis ini pasca rejim Orde Baru mengalami pertarungan kembali yang hasilnya terlihat dalam politik elektoral dan sentimen-sentimen yang muncul di ruang publik. Di tengah dua pertarungan besar ini, demokrasi yang sudah berjalan 20 tahun di Indonesia kemudian menjadi tumbal. Padahal, sistem demokrasi inilah yang memungkinkan kelompok-kelompok kecil yang tak bersuara terepresenasikan. Karena itu, geliat dua pertarungan ini justru mengabaikan kelompok-kelompok minoritas, baik secara keyakinan, ideologi, sosial, maupun ekonomi.
Dengan demikian, jika puisi Sukmawati ini terus digoreng seperti kasus Ahok, yang menang bukanlah dua ideologi besar ini, melainkan predator politik yang beririsan dengan oligarki. Jika sudah begini, tidak penting lagi bagi kita untuk berteriak keadilan, kemiskinan, dan hak-hak warga negara yang dirampas kemudian memperjuangkannya atas nama demokrasi. Ini karena, wajah persekusi dan kekerasan akan setia mengintai.



