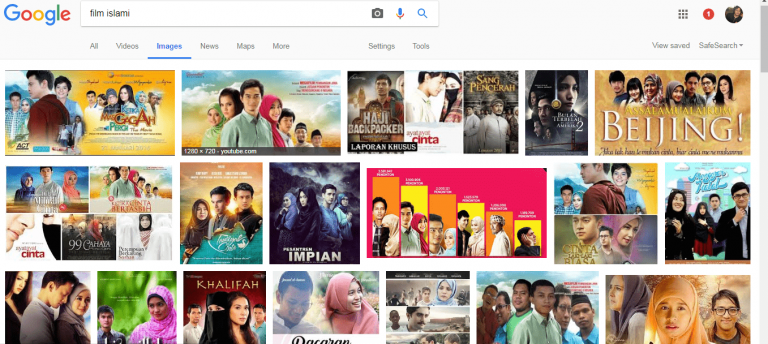
Apakah film islami di negeri ini kian konservatif? Pertanyaan itu muncul sebagai dasar pemikiran tentang banyaknya film islami yang belakangan merajai bioskop tanah air. Terang saja, film seperti Ayat-ayat Cinta 2 dan Surga yang Tak Dirindukan 1 & 2 misalnya, mampu menyedot jutaan penonton. Tapi, benarkah film islami ini ditujukan untuk dakwah atau sekadar profit saja? Apalagi, film-film ini hanya menjadikan islam sebagai latar dan simbol belaka?
Jawaban atas hal itu saya temukan dalam diskusi terbatas yang digelar Alif.id di Cangkir 9, Kalibata City, jelang akhir pekan lalu. Kira-kira Kamis malam (29/3), lepas Isya, café khas Aceh ini dipenuhi belasan kaum muda progresif yang memenuhi undangan Alif.ID dalam diskusi “Dua Dunia; Film dan Islam”.
Sebagai awam akan film, malam itu memberi banyak informasi dan perpektif baru bagi saya, tentang bagaimana melihat sebuah film, terutama seputar film religius islam di tanah air. Kehadiran Sutradara Nurman Hakim dan Susi Ivvaty, Founder Alif.ID sebagai duet narasumber membuat diskusi santai ini padat akan pengentahuan dan informasi berharga.
Salah satu yang paling menarik perhatian saya adalah perebutan narasi islam dalam perfilman di Indonesia. Rupanya, perebutan klaim ‘siapa yang paling islami’ tidak melulu hanya terjadi di pentas politik atau media sosial saja lho kisanak, namun juga terjadi di dunia perfilman.
Lantas pertanyaannya siapa yang paling berhak bilang bahwa sebuah film lebih islami dari pada yang lain?
Sebelum menjawab pertanyaan itu, ada dimensi menarik yang terkandung dalam dimensi sebuah film sebagaimana dijelaskan oleh Nurman Hakim; pertama film sebagai cerminan sebuah kebudayaan, atau minimal refleksi dari cara berpikir sebuah masyarakat yang menggandrunginya. Kira-kira begini, saat film tertentu disukai oleh satu kalangan dengan jumlah penontoh mencapai satu juta, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa kira-kira cara berpikir film tersebut cocok dengan cara berpikir mayoritas kelompok penontonnya.
Kedua, di saat yang bersamaan, sebuah film merupakan cerminan dari isi kepala seorang penulis naskah atau sutradara yang mendalanginya.
“Ia (film) tak lain merupakan buah pikiran dari sutradara di belakangnya lengkap dengan konteks sosial, psikologis yang sedang dirasakannya dan latar belakang politik yang dialaminya,” papar Nurman.
Sutradara film Tiga Doa Tiga Cinta, Khalifah dan Bid’ah Cinta itu juga menegaskan, sebuah film memperlihatkan kecenderungan kepada sisi mana si pembuat film itu berpihak, apakah kepada gerakan progresif atau sebaliknya konservatif. Singkatnya, apa yang dilihat penonton di layar kaca, tak lain adalah isi pemikiran surtradara yang menukangi film tersebut.
Jadi, jika kita ingin mengetahui pemikiran dan keberpihakan seorang sutradara, lihatlah filmnya.
Sayangnya, jenis film yang disukai saat ini adalah film yang cenderung konservatif, glorifying, dan kerap hanya menunjukkan sisi islam yang sempurna tanpa celah untuk kritik. Kejadian semacam itu bukan tiba-tiba disukai tanpa alas an. “Justru kondisi ini sesungguhnya merepresentasikan pemahaman masyarakat indonesia terhadap wajah islam”, lanjut Nurman.
Tentu tak berlebihan jika masyarakat Indonesia dinilai semakin konservatif. Tesis nurman itu medapat pembenaran dari dunia nyata melalui, misalnya, tingginya rangkaian aksi demonstrasi 411, 212 dan seterunya, tingginya angka persekusi atas mayoritas terhadap yang ‘sedikit’. Dalam catatan Wahid Foundation juga berkata demikian; potensi intoleransi terhadap kelompok yang tidak disukai di Indonesia meningkat di tahun 2017 (57 %) dibanding tahun 2016 (51%).
Barangkali ekspresi ketidaksukaan terhadap kelompok lain dan glorifikasi berlebihan terhadapa kelompok sendiri yang juga menyebabkan film islami di Indonesia begitu kaku dalam memaknai nilai-nilai islam. Ketidak sukaan ini juga kerap berakibat pada ketidak-objektifan dalam menentukan nilai sebuah data. Sebagimana yang diungkapkan Susi Ivvaty, bahwa terdapat sejumlah film islami yang ‘kebablasan’ dalam mengglorifikasi islam tanpa data yang kuat.
“Beberapa film islami, bahkan, lahir dari riset yang minim. Film semacam ini sejatinya menyesatkan,” tambahnya.
Jenis film semacam ini juga yang kemudian menampilkan sosok manusia islam yang ‘maha-sempurna’, yang digambarkan sebagai seorang pria berwajah tampan, memiliki kecakapan di atas banyak orang, kaya, alim, dan membuat semua perempuan bilang “nikahi aku Fahri”. Kalimat “nikahi aku Fahri” sendiri sempat menjadi viral di media sosial sebagai respon atas ‘kesempurnaan’ seorang Fahri dalam film “Ayat-ayat Cinta 2” yang banyak menuai kritik karena dianggap terlalu imaginatif.
Dalam kontek ini kita menjumpai produser film yang sepertinya kurang atau tidak mau mementingkan edukasi di atas profit.
“Para pelaku industri perfilman tidak ada urusan dengan (nilai dan edukasi) itu. Ndak peduli apakah film yang dibikin berdampak positif atau negatif. Itu bukan urusan mereka. Yang ada (dalam pikiran mereka) hanyalah bagaimana mereka bisa dapat untung dari produksinya,” tambahnya.
Dari serangkaian hasil diskusi perfilman islam malam itu, diam-diam masyarakat perfilman Indonesia tidak mengalami kemajuan dalam budaya perfilman, bahkan bisa dikatakan mengalami kemunduran jauh ke belakang. Kemunduran yang sama juga dapat kita temukan pada cara berpikir kita di kehidupan nyata.
Lantas bagaimana cara kita memajukan budaya islam progresif dalam wajah perfilman kita? Itulah tantangan besar untuk kita bersama.



