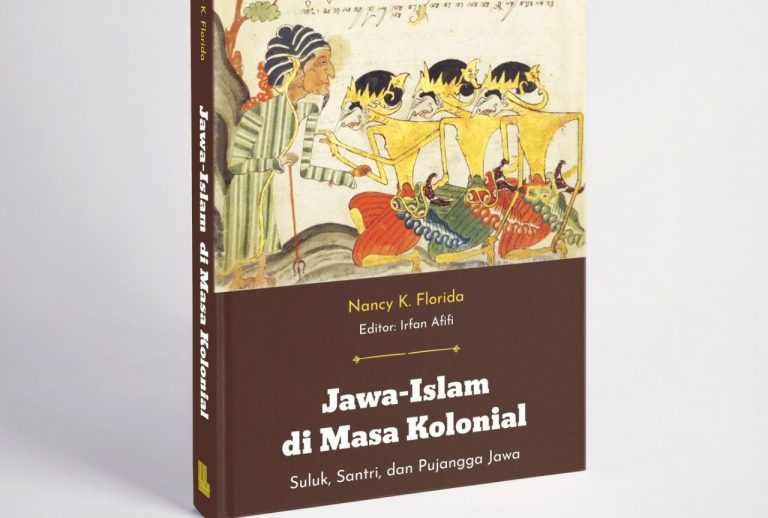
Resensi buku Islam Jawa di Masa Kolonial ini melacak apa yang telah kolonialisme lakukan terhadap Islam di Jawa. Kolonialisme sukses memisahkan Islam dari tradisi keraton.
Bagaimana kita membaca Islam ketika kontruksi kolonial begitu mencengkram dalam wacana pengetahuan kita? Di mana setiap saat kita seperti disodorkan dengan berbagai narasi pengetahun yang samar-samar bahkan dikaburkan terkait tradisi keislaman masyarakat kita. Hal inilah yang kiranya menjadi pangkal dari persoalan pengetahuan keislaman kita sehingga terjadi polarisasi yang begitu kentara antara Islam dan tradisi masyarakat, yang denyutnya masih bisa kita rasakan sampai hari ini.
Dalam hal ini, kolonialisme dengan grand design moderismenya mempunyai kepentingan politis agar polarisasi memang terjadi di tubuh keislaman kita. Karena bagaimanapun dalam tubuh Muslim Jawa, bahkan daerah-daerah lainnya, kesatuan antara budaya dan agama menjadi nafas dari laku hidup masyarakat kita. Kepentingan kolonialisme dengan para orientalismenya bermain untuk secara tegas memisahkan antara Islam dan tradisi priyayi yang identitik dengan keraton.
Maka terjadi proses pembelahan identitas kultural yang disebut Zizek sebagai “subyek-subyek yang retak” di tubuh identitas keislaman kita.
Diakui atau tidak, kekuatan Islam memang menjadi basis utama perlawanan terhadap kolonialisme. Kita bisa berkaca pada peristiwa sejarah perang Jawa yang dipimpin oleh Pangeran Diponegoro tahun 1825-1830 yang hampir menghancurkan ekonomi Belanda. Trauma mendalam atas perlawanan kultural yang disokong bersama oleh kaum priyayi dan kiai ini, sontak mengakibatkan politik etis dan pecah belah Belanda dilancarkan. Dari momentum tersebut juga kemudian, Belanda dengan sekuat tenaga berusaha memisahkan dua entitas kultural antara elit Islam dan kaum priyayi keraton.
Semenjak itu pula proses konstruksi wacana keislaman yang awalnya bersumber dari tradisi intelektual keraton melalui para pujangga Jawa seperti Yusadipura higga ke Ranggawarsita terputus dengan gagasan keislaman yang diwakili oleh kaum pesantren. Munculnya lembaga kajian Javanalogi di Surakarta menjadi titik pijak bagaimana konstruksi pengetahuan yang cenderung destruktif akhirnya muncul dan melembaga di instansi-intansi sekolah kita.
Oleh karenanya, problem pengetahuan yang sudah jauh mengakar dalam alam pikir masyarakat kita semenjak kolonialisme tersebut, menjadikan pemahaman kita terhadap Islam Jawa sangat parsial dan terfragmentasi sedemikian rupa.
Belum lagi arus baru pemahaman moderisme yang selalu menghantam wacana tradisi keagamaan yang dianggap sebagai mitos, klenik, dan tidak saintifik terus merangsek ke dalam alam pikir kita. Disisi lain pemahaman keagamaan Islam baru yang datang dari Timur Tengah semakin menguat dan mengeras dengan tuduhan kafir, khurafat, bid’ah yang secara serampangan memojokkan tradisi keagamaan di Nusantara yang selama ini diwarisi oleh para ulama dan wali di nusantara.
Islam Diamati di Jawa Masa Kolonial: Upaya Pemisahan Islam dan Tradisi Keraton
Dari apa yang saya gambarkan di atas, buku baru dari salah satu Indonesianis dan peneliti naskah-naskah kuno Jawa dari Michigan University, Nancy K. Florida yang di editori oleh Irfan Afifi yaitu Jawa Islam di Masa Kolonial, Suluk, Santri, dan Pujangga Jawa menjadi relevan untuk dibicarakan.
Nancy yang hampir mewakafkan separuh dari hidupnya selama 30 tahun untuk meneliti naskah kuna berupa serat, suluk, dan babat di Keraton Surakarta. Menjadikan otoritasnya terhadap khasanah naskah-naskah yang tersimpan di Keraton Surakarta yang sebenarnya menyimpan warisan keislaman tidak terbantahkan lagi. Dalam buku ini, Nancy menunjukan dengan jelas dan tegas bahwa sebenarnya hampir 85 persen dari 3000 naskah yang dibacanya merupakan warisan keilmuan keislaman yang bercorak ajaran tasawuf.
Padahal sebelumnya para orientalis di masa kolonial seperti Cohen Sturat, De Graaf, Pigeaud, melalui diskursus filologinya para sarjana kolonial tersebut berusaha membingkai kesustraan Jawa menjauhi kebudayaan kita sesuai dengan kepentingan politik mereka. Narasi Islam yang menjadi jantung kebudayaan kita berusaha dikaburkan maknanya, bahkan dihilangkan dari dimensi faktualnya. Dengan motif tersebut filologi kolonial kemudian mengajari kita bahwa kesusteraan Jawa mencapai puncak kehalusan dan keindahan pada masa lalu pra-Islam yang sangat jauh, dengan warisan budaya tulis sastra Kawi kuno zaman Hindu-Budha.
Mereka menganggap bahwa kesusastraan Jawa yang menghasilkan Kakawin tumbuh subur dan akhirnya gemilang sebelum Islam ada di Jawa. Parahnya, kemudian mereka beranggapan kehadiran Islam di akhir abad-15 telah menghantam proses tumbuh kembangnya kesusastraan Jawa di masa sebelumnya.
Filologi kolonial menunjukan secara tersirat, bahwa apa yang mengikuti “penaklukan Islam” adalah periode panjang yang terselubung kegelapan, yaitu budaya kesusastraan Islam yang muncul di wilayah pesisir (daerah sepanjang pantai utara Jawa). Mereka mengatakan bahwa pengarang pesisir periode tengah tersebut menghasilkan karya turunan yang “tidak asli”, yang kadang-kadang rusak atau tak lengkap, dengan topik Islam “yang asing” (Nancy:2020).
Kelahiran Kembali Kesusatraan Jawa
Masih dalam kerangka sejarah filologis kolonial, pada akhir abad ke-18 kesusasteraan Jawa akhirnya mengalami semacam “kelahiran kembali” (renaisans) di Keraton Surakarta, sebuah kelahiran kembali yang memeberi efek pemulihan kembali sebagai “kebesaran kebudayaan sastra Jawa Kuno” yang hilang. Renaisans ini secara umum dianggap mencapai kesempurnaanya setalah berhasil menerjemahkan kakawin Jawa kuno ke dalam bahasa Jawa modern dalam bentuk tembang dan macapat.
Seperti disampaikan oleh filolog terkemuka saat itu Theodore Pigeaud yang menandai ranaisans klasik ini dengan pernyataan: “beralihnya minat para sarjana Jawa dari karya Islam ke sastra kakawin Jawa Kuno, serta perkembangan lebih lanjut kesusasteraan di Keraton Surakarta pada abad ke-18 dan ke-19, serupa dengan kelahiran kembali kesusasteraan Jawa klasik.” Menurutnya, karena para pujangga akhirnya berbelok dari Islam asing ke asal Jawa Hindu-Budha-nya puisi Jawa telah lahir kembali. (Jawa Islam di Masa Kolonial, hlm. 17).
Nancy menyatakan bahwa dalam periode ini renaisans kesusastraan Jawa telah hadir walaupun dengan waktu yang cukup singkat (bahkan mungkin dapat dikatakan mati waktu masih di dalam kandungan). Karena menurutnya, menjelang akhir abad ke-19, filologi kolonial telah menetapkan kesimpulan bahwa berbagai hasil karya terkemuka renaisans Surakarta ternyata merupakan terjemahan atau “gubahan yang buruk”.
Tidak hanya itu, mereka juga telah mengelompokkan banyak karya sastra lebih baru yang dihasilkan di lingkungan keraton ini sebagai karya yang merosot secara isi dan semakin susah dipahami.
Bagaiamanapun itu, filolog kolonial telah menggariskan bahwa yang mereka maksud dengan renaisans dalam pandangan mereka, lahir di dalam tembok tinggi Keraton Surakarta, kebal akan waktu dan perubahan terutama akan jauh dari interuksi pesan politik Islam. Karena itu juga menjelang akhir abad ke-19, filologi kolonial telah menetapkan kesimpulan bahwa berbagai hasil karya terkemuka ranaisans Surakarta ternyata merupakan terjemahan atau gubahan yang “buruk”, semakin merosot secara isi dan semakin susah dipahami. Dari hal itu juga kemudian kebudayaan Jawa dibentuk sedemikian rupa dan di gariskan terus menerus dan diamini hingga kini.
Pemaparan di atas menunjukan bahwa para filolog kolonial telah berhasil membangun narasi besar terkait kesusastraan Jawa seperti yang mereka inginkan. Dengan maksud dan tujuan untuk memutus rantai pengetahuan Nusantara. Yang sebenarnya tersimpan dalam kesusastraan Jawa merupakan ajaran para wali yang termanifestasikan dalam keilmuan di keraton Surakarta maupun Yogyakarta berupa naskah-naskah berupa babat, suluk, dan berbagai ekspresi tradisi lainya.
Hal ini bisa ditunjukan bahwa para pujangga keraton mulai dari Yusadipura yang dianggap sebagai bapak renaisans Surakarta merupakan seorang santri atau “pembelajar Islam”. Pada usia 8 tahun Yusadipura sudah menjadi “santri lelana” ia dikirim ke desa pedalaman Bagelan-Kedhu untuk belajar bahasa Arab dan huruf Jawa di pesantren Kyai Honggamaya, seorang teman dari kakek dari ibu. Begitupun R. Ng. Ronggawarsito juga merupakan salah satu santri dari Kiyai Hasan Besari dari daerah pedalaman Ponorogo. Dari fakta sebagai pembelajar Islam itulah maka yang dapat dilihat dari karya mereka meupakan ajaran-ajaran tasawuf Islam yang tidak terlepas dari ajaran keilmuan yang sudah ada terlebih dahulu dari ajaran leluhur kita di Nusantara.



