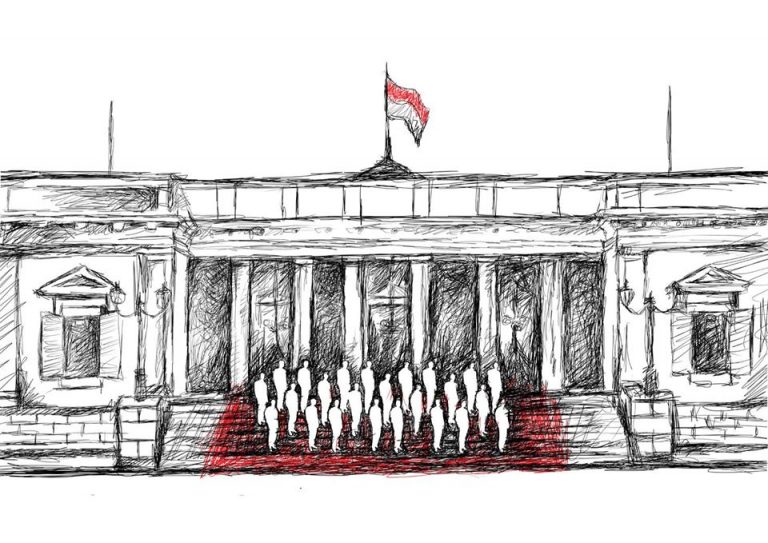
Pendaftaran calon presiden yang ditetapkan oleh KPU memang masih lama, yaitu tanggal 19 Oktober-25 November 2023, tapi saat ini, sudah ada beberapa calon yang sering menjadi bahan berita media nasional maupun lokal.
Namun ada satu hal yang dianggap sangat ‘machiavelanis’ yaitu menggunakan politik identitas untuk meraup suara ataupun memperkuat basis sendiri. Menurut Firman Noor dalam Politik Identitas : Problematika dan Paradigma Solusi, (2019), politik identitas secara sederhana bisa dimaknai sebagai strategi politik yang memfokuskan pada pembedaan dan pemanfaatan ikatan primordial sebagai kategori utamanya. Politik identitas dapat memunculkan toleransi dan kebebasan, namun di lain pihak, politik identitas juga akan memunculkan pola-pola intoleransi, kekerasan verbal-fisik dan juga pertentangan etnik dalam kehidupan.
Sementara itu menurut Zaidan Nawawi dalam Kontestasi Politik Identitas, (2022), fakta sosiologis dan politis Indonesia yang beragam banyak dijadikan jualan politik oleh elit tertentu demi meraih kepentingan yang sifatnya jangka pendek. Fakta ini sebenarnya berjalan netral, namun menjadi ‘jijik’ jika keragaman itu ditunggangi oleh kepentingan politik.
Politik Identitas ‘Tanda’ Jahiliyahisme dan Kemusyrikan
Lalu bagaimana sebenarnya politik identitas itu jika ditinjau dari sudut pandang Al-Qur’an? Karena politik identitas bisa berjalan dalam dua arah: menguatkan basis massa juga membelah bangsa. Membelah bangsa sepertinya yang lebih mendominasi situasi politik saat ini menjelang pilkada 2024. Allah swt mengingatkan dalam Qs Ali Imran ayat 103 :
وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا ۖوَاذْكُرُوْا نِعْمَتَ اللّٰهِ عَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ اَعْدَاۤءً فَاَلَّفَ بَيْنَ قُلُوْبِكُمْ فَاَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهٖٓ اِخْوَانًاۚ وَكُنْتُمْ عَلٰى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَاَنْقَذَكُمْ مِّنْهَا ۗ كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُوْنَ
Artinya : “Dan berpegang teguhlahlah kamu semuanya pada tali (agama) Allâh, dan janganlah kamu bercerai berai, dan ingatlah nikmat Allâh kepadamu ketika kamu dahulu (masa jahiliyah) bermusuhan, lalu Allâh mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara, sedangkan (ketika itu) kamu berada di tepi jurang neraka, lalu Allâh menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah, Allâh menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk.”
Menurut AG Prof Quraish Shihab dalam Tafsir al-Mishbah, bahwa pada masa jahiliyah masyarakat pada waktu itu saling bermusuhan. Lalu Allah swt menjadikan Islam sebagai pemersatu. Hati kaum muslim saling terpaut karena cinta yang didasari oleh Islam. Berdasarkan tafsiran ini kita bisa memahami bahwa keterbelahan, keterpecahan umat adalah jahiliyahisme. Mungkinkah kita saat ini akan kembali menjadi jahiliyah modern karena politik identitas yang memecah belah tersebut?
Kemudian di lain ayat Allah SWT menyebut bahwa orang yang berpolitik identitas adalah bagian dari sikap menyekutukan Allah :
وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيَعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ
“Dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka menjadi beberapa golongan. Tiap-tiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka”. (Ar-Rum: 31-32)
Kenapa politik identitas yang memecah belah adalah bagian menyekutukan Allah? Itu dikarenakan adanya ‘pemujaan’ elit politik. Jika dulu ada pemujaaan dewa-dewi maka saat ini dewa-dewi itu adalah elit politik tertentu yang dipuja dan ‘dikultuskan’.
Perlukah Fatwa Larangan Berpolitik Identitas?
Jika mengamati dua ayat di atas tentang saling memecah belah sebagai bagian Jahiliyahisme dan kemusyrikan maka mungkin sebaiknya para tokoh ormas, MUI maupun para ulama bisa melakukan ijtihad untuk merumuskan apakah fatwa larangan itu penting untuk mengantisipasi kembalinya politik identitas seperti yang terjadi di Pilkada DKI 2017 dan Pilpres 2019.
Dalam salah satu jurnal yang ditulis oleh Ansar Suherman, dkk, Identity Politic Contestation in the Public Sphere: A Steep Road of Democracy in Indonesia (2020), disebutkan,
Pertama, politik identitas dianggap sebagai senjata ampuh oleh elit politik untuk menjatuhkan popularitas dan elektabilitas saingan politiknya atau upaya untuk mendapatkan dukungan politik dari publik. Isu suku dan agama merupakan dua hal yang selalu masuk dalam agenda politik identitas elit di Indonesia, apalagi suasana primordialisme dan sektarianisme masyarakat Indonesia masih cukup kuat sehingga sangat mudah untuk memenangkan simpati publik, menyulut kemarahan dan sentimen massa dengan menyebarkan isu-isu etnis dan agama.
Selain itu banyak ustadz atau tokoh agama pendukung calon tertentu yang menafsirkan beberapa ayat dalam Al-Qur’an sesuai dengan ‘nafsu’ politik sendiri tanpa merujuk pendapat para ahli tafsir.
Landasan Fatwa Larangan Politik Identitas
Sebuah fatwa lahir salah satunya karena adanya masalah yang tengah ramai diperbincangkan oleh masyarakat. Sejak Pilkada Jakarta 2017 hingga sekarang politik identitas masih menjadi mesin utama kalangan politisi untuk menguatkan dukungan. Dan yang viral saat ini adanya tabloid yang ‘memamerkan’ salah satu kepala daerah yang dibagikan di beberapa masjid dan itu ditengarai oleh netizen sebagai politik identitas, bahkan hashtag #BapakPolitikIdentitas beberapa kali mencuat di tweeter.
Dalam sebuah jurnal yang berjudul Memahami Indonesia Melalui Persfektif Nasional, Politik Identitas, Serta Solidaritas yang ditulis oleh Mifdal Zusron Alfaqi (2016), ada 3 bentuk politik identitas yang sekarang terjadi:
Pertama, legitimasi, politik identitas diperkenalkan oleh institusi yang mendominasi masyarakat. Misal partai politik, ormas atau lembaga Islam.
Kedua, resistensi, usaha membentuk atau memperkenalkan identitas oleh aktor sosial karena merasa diri ‘tertekan’.
Ketiga, proyek, aktor-aktor sosial membentuk identitas baru. Misal kita lihat munculnya perkumpulan-perkumpulan yang mengatasnamakan islam, GNPF dan PA212.
Para pelaku Politik Identitas juga biasanya sekalipun terbukti menyebar hoaks, namun tetap dibantah bahwa hoaks tersebut dari ‘orang sebelah’, parpol A atau B, ormas A atau B.
Karena saling berpecah belah, saling bermusuhan dan membangga-banggakan kelompok sendiri adalah Jahiliyahisme maka sebaiknya seorang muslim berlindung kepada Allah swt dari hal tercela tersebut. Tapi jangan juga buta politik. Rasulullah SAW mencontohkan pada masa berada di Madinah, beliau bisa menyatukan berbagai suku dan agama. Tentunya tidak terlepas dari kepiawaian Rasulullah dalam berpolitik, salah satunya dengan mengedepankan akhlakul karimah dalam merangkul dan ‘membungkam’ musuh.
Kebijakan Politik ala Rasulullah SAW
H.A Jadzuli dalam Fiqh Siyasah; Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah (2013). Ada beberapa metode politik yang digunakan yaitu ukhuwah islamiyyah (persaudaraan sesama muslim antara Muhajirin dan Anshor) dan ukhuwah insaniyah (persaudaraan sesama manusia/warga Madinah yang terdiri dari berbagai suku Yahudi dan Nashrani ).
Selain itu Rasulullah juga membuat role model kebijakan politik, pertama, membangun infrastruktur seperti masjid yang menjadi pusat kegiatan ummat. Mengingat saat itu belum ada gedung pemerintahan, maka di masjidlah segala kebijakan dirumuskan dan dikeluarkan.
Kedua, membangun SDM yaitu persaudaraan antar komunitas dari berbagai latar belakang suku, etnis, agama dan ras.
Ketiga, membuat nota kesepakatan atau MoU dengan beberapa pemimpin suku.
Keempat, memperkuat militer karena pada saat itu Madinah masih rentang serangan pihak musuh.
Role Model kebijakan politik yang dibangun oleh Rasulullah SAW di Madinah 1400 tahun yang lalu tentu bisa menjadi spirit untuk untuk majunya iklim politik di Indonesia ke arah yang lebih baik, meskipun kita tidak perlu ‘seperti’ Madinah pada abad ke 6 M. Karena kebijakan politik Nabi tentunya disesuaikan dengan keadaan Madinah saat itu.
Meskipun demikian ada beberapa kesamaan dengan Indonesia, yaitu keragaman masyarakat. Bahkan, keragaman masyarakat Indonesia lebih kompleks, begitu juga konsep wilayahnya yang terpisah-pisah. Berbeda dengan Madinah yang hanya terdiri dari satu wilayah saja.
Menjadi pemimpin Indonesia haruslah cinta keragaman seperti Nabi. Nabi selalu mengedepankan akhlak, serta persatuan antar komunitas untuk menyelesaikan masalah dan membangun masyarakat. (AN)



