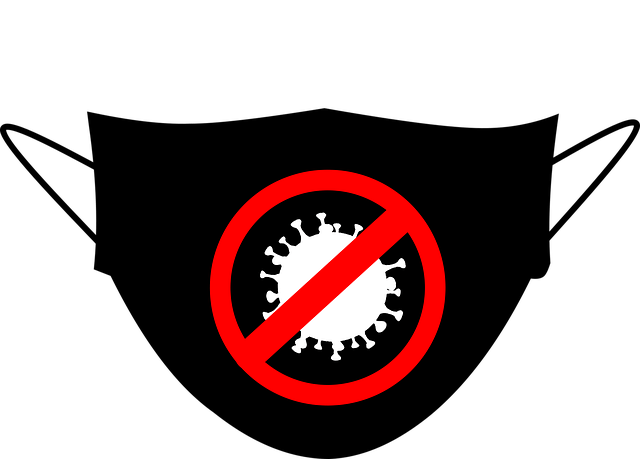
Situasi seperti pandemi membutuhkan cara pandang yang jeli dalam melihat mana masalah alam (natural problem) dan mana masalah sosial (social problem). Dua-duanya punya konsekuensinya masing-masing bila seseorang keliru menggunakan cara pandang.
Dunia sosial (social science world) mengenal istilah negosiasi. Realita dalam dunia sosial tidak ditentukan oleh realita per se, tapi ditentukan oleh beragam faktor, misalnya, kesepakatan, interpretasi dan kepercayaan, baik pada skala individu ataupun kolektif. Hal ini yang memungkinkan seseorang boleh membayangkan, atau bahkan memaksakan kehendak idealnya pada suatu kondisi sosial tertentu.
Dunia sosial membolehkan seseorang untuk berbeda dengan interpretasi ataupun kepercayaan yang telah disepakati oleh suatu komunitas. Situasi sosial hanya bisa berubah oleh dua hal: seorang yang otoritatif/berkuasa, atau mayoritas yang bersepakat. Dua hal tersebut kadang saling klik, namun tidak jarang juga saling bertentangan.
Berbeda dengan dunia sosial, dunia alam (natual science world), tidak mengenal istilah kata negosiasi. Misalnya, kalau realitanya adalah X, maka seseorang tidak akan bisa mengubah realita itu meski seribu kali berkelit atau menyangkalnya. X hanya dapat berubah kalau seseorang menggunakan kacamata dan pendekatan yang sesuai dengan hukum alam yang berlaku di dalamnya.
Hal ini menjelaskan―misalnya―mengapa optimisme militeristik Luhut Binsar Panjaitan bahwa “kita [tentara] kalau sudah dikasih tugas, hanya dua [prinsipnya]: amankan dan laksanakan,” saat ditanya oleh Najwa Shihab soal bagaimana menyelaraskan pilkada dan pandemi yang grafiknya semakin vertikal, tidak berdampak apa-apa bagi pelandaian kurva pandemi. Dengan kata lain, optimisme naif.
Natural science hanya mengenal dunia yang hitam putih: kalau tidak mati, ya hidup. Dan natural science tidak tunduk pada apapun, tidak terkecuali politik dan kenestapaan sosial (meski politik dan sosial sering kali ngeyel terhadap natural science). Natural science hanya tunduk pada hukumnya. Siapa yang tidak tunduk pada hukum alam, ia akan terlibat dalam dead or alive game, tak peduli satu ataupun sejuta nyawa.
Hal ini juga yang menjelaskan mengapa stiker pencegahan virus korona yang ditempel di semua transportasi publik tidak berpengaruh apa-apa pada pelandaian kurva, jika jumlah pengguna transportasi umum semakin hari semakin naik, dan sebagian moda transportasi justru memberikan harga promo. Dengan kata lain, Jargon ‘new normal’ atau slogan “boleh [ke bioskop], asal sesuai protokol kesehatan” adalah ekspresi intelektual paralisis yang berusaha menjinakkan realita banal dengan cara pandang yang tidak selaras dengan hukum realita banal tersebut.
Saat masalah alam berbuntut pada ketidak-nyamanan sosial, pada titik inilah seseorang/komunitas rawan terpeleset menggunakan cara pandang yang keliru. Post-truth, kondisi ketika ada satu realita per se tertentu yang orang punya beragam kepercayaan tentangnya. Ketidak-mampuan seseorang dalam menundukkan hukum alam sering kali mendorongnya untuk memaksakan cara pandang sosial untuk menyelesaikan natural problem, meski seseorang itu tau bahwa cepat atau lambat dead or alive game akan membinasakannya.
Di Indonesia, kondisi itu dapat diukur dengan membuktikan hipotesis bahwa: “penggunaan retorika optimistik dan slogan ber-eufimisme semakin meningkat seiring dengan semakin vertikalnya grafik pandemi.” Pembuktian ini dapat dilakukan―misalnya―dengan mengkombinasikan scrapping kata-kunci yang mengandung muatan harapan, optimisme dan kepercayaan di internet, dan screening riwayat-riwayat pernyataan pengambil kebijakan yang memuat substansi serupa. Hasil yang didapat kemudian dibandingkan dengan pola perilaku tertentu yang ada di lapangan atau yang terekam oleh data statistik (misalnya peningkatan/penurunan mobilitas penduduk, dll).
Membuktikan hipotesis ini tidak hanya dapat mengindikasi kental atau tidaknya budaya menutupi/merias realita pahit dengan kata-kata indah agar lebih nyaman dan lebih bisa diterima, tapi juga sekaligus dapat mengungkap: seberapa mengakar kegagapan dalam menggunakan cara pandang logika ilmu alam dan logika ilmu sosial dalam menyelesaikan masalah yang ada, terjadi di Indonesia.
Kalau kekeliruan cara pandang terjadi di lapisan pengambil kebijakan, maka misleading adalah konsekuensinya. Kalau terjadi di lapisan masyarakat, maka disorder adalah luarannya. Dua-duanya sama-sama berujung pada akhir yang tidak membahagiakan.
Pengaruh politik sering kali menyebabkan science denial di kalangan pengambil kebijakan. Sedangkan di lapisan masyarakat, perasaan lelah/frustasi terhadap situasi yang ada sering kali mendorong pencarian realita alternatif yang dianggap lebih mengobati perasaan lelah/frustasi yang dialami, seperti teori konspirasi, hoaks, dan willful ignorance. Di tengah pandemi yang memekakan perasaan, kita tidak tau telah seberapa jauh scientific disrespect ini meluas dan telah menyentuh lapisan mana saja.
Bagaimana kita dapat bertahan di masa depan, jika masih belum disiplin dalam menentukan dan menggunakan cara pandang terhadap masalah yang ada? Menebar kata-kata indah yang tak menyentuh realita adalah bentuk membohongi diri sendiri. Mungkinkah kita dapat bertahan hidup di masa depan kalau institusi-institusi sosial yang ada (sekolah, politisi, dll) masih tetap lebih tertarik pada penanaman ideologi partisan dibanding penanaman sikap ilmiah? Meski ketidak-hadiran sikap ilmiah dalam institusi politik, keagamaan, pendidikan dan kemasyarakatan telah terbukti membawa kerusakan yang tidak murah.
Saat Hungaria mengalami keresahan ilmu pengetahuan dan pelembagaannya, tokoh sastra era 1780-an, Gyӧrgy Bessenyei menggulirkan prinsip bahwa, tujuan utama pembudidayaan sains adalah upaya untuk menggapai kesejahteraan bagi semua orang. Dan prinsip inilah yang menjadi cikal gemilangnya Hungarian Academy of Sciences. Bessenyei tidak lain sedang mengamalkan hadist Nabi, siapa yang ingin bahagia di dunia dan akhirat maka harus dengan ilmu. Kenestapaan hanya muncul dari dua hal, pertama, hidup tanpa ilmu. Kedua, tidak belajar dari masa lalu.



