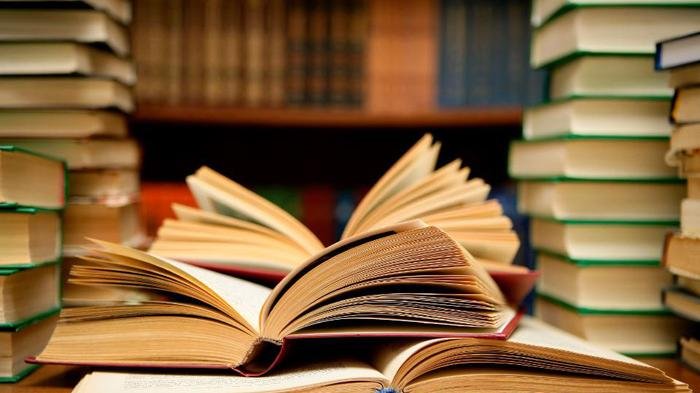
Ketika menyebut nama Najamuddin al-Thufi, orang langsung teringat mengenai konsep maslahahnya yang liberal lagi kontroversial. Liberal jika diukur dari zamannya –bahkan oleh sebagian pakar– juga sampai saat ini. Letak keliberalan konsep maslahah pemikir asal Sarsara ini adalah ketika ia meletakkan maslahah di atas teks wahyu. Konsep taqdim al-maslahah ‘ala al-nash wa al-ijma’, memprioritaskan maslahah atas teks (Al-Quran dan Sunnah) juga ijmak adalah puncak pemikaran al-Thufi.
Ulama bermazhab Hanbali ini juga berpendapat bahwa maslahah adalah inti pokok, sumber pertama, dan tujuan utama dari syariah. Baginya, tujuan dan sesuatu yang sifatnya inti mesti lebih diprioritaskan daripada sesuatu yang sifatnya sarana. Teks adalah sarana, maslahah adalah tujuan. Teks adalah wadah, maslahah adalah isi.
Alasan penulis kitab Syarh al-Arbai’in al-Nabawiyah ini menjadikan maslahah di atas posisi puncak mempunyai beberapa alasan. Di antaranya adalah, maslahah merupakan amr haqiqi fi nafsishi, sumber paling riil dan paling jelas di dalam dirinya; al-wadlih bayanuha, sudah terbukti; la yukhtala fih, tidak perlu diperdebatkan; sementara teks wahyu itu saling bertentangan di satu sisi, anna al-nushuh mukhtalifah muta’aridah; dan adanya kontradiksi antara sesama hadis Nabi juga antara hadis dengan Al-Quran di sisi yang lain, ta’arud al-riwayah wa al-nushush.
Selain itu, adanya kontradiksi-kotradiksi dalam teks hadis menimbulkan ketidaksepakatan pendapat di antara para ulama. Begitu juga adanya kelompok sektarian yang menjadikan hadis sebagai legitimasi kelompoknya, sembari mendiskriditkan kelompok lain.
Banyaknya peperangan, pertikaian, dan saling benci di kalangan mazhab hukum, juga jadi alasan al-Thufi menjadikan maslahah di atas segalanya, termasuk teks wahyu.
Gagasan ini sontak saja menjadi kontroversi. Bagi pihak yang sepakat –seperti Shubhi Mahmasani, Abu Yusuf al-Hanafi, Mustafa al-Ghulayain, Ibarahim Husen, dan Munawir Sjadzali –menyebut konsep maslahah al-Thufi perlu direaktualisasi dan dijadikan rujukan dalam menghadapi problematika kehidupan manusia. Dengan menjadikan maslahah sebagai acuan tanpa dikekang oleh teks, maka hukum Islam akan selalu progresif dan kontekstual.
Bagi pihak yang menolak, pemikiran kekonseptor kelahiran 675 H ini dianggap kebablasan, salah, keluar dari syariah, bahkan dianggap sesat. Tak ayal pemikir bernama lengkap Sulaiman bin ‘Abd al-Qawi Ibn al-Karim Ibn Sa’id al-Thufi mendapat tuduhan macam-macam. Mulai dari tuduhan syiah, liberal, mengada-ada, muktajilah, sesat sampai kepada tuduhan murjiah.
Kritik Ideologis dan Epistemologis Terhadap al-Thufi
Menurut Haurani, di abad pertengahan, ada dua peta pemikiran tentang baik dan buruk, yakni objektif-rasional dan subjektif-teistik. Yang pertama mengatakan bahwa baik dan buruk, maslahah atau madharat bisa dikatahui secara objektif oleh akal tanpa perlu bantuan teks. Bagi yang terakhir, baik dan buruk, maslahah atau madharat tidak bisa diketahui sebelum ditentukan oleh Tuhan dan dikonfirmasi oleh teks wahyu.
Senada dengan itu, Muhammad Khalid Mas’ud, menyebut ada dua krakteristik dari konsep maslahah klasik. Pertama, determinisme teologis, bahwa maslahah tidaknya sesuatu ditentukan oleh Tuhan melalui teks wahyu. Kedua, determinisme metodologis, yakni malahah selalu di bawah bayang-bayang maslahah mursalah dan qiyas.
Jika kedua tolak ukur ini dijadikan untuk menilai al-Thufi, maka secara sepintas ia masuk ke dalam aliran objektif dan keluar dari determinisme teologis dan metodologis. Hal ini terlihat ketika al-Thufi membangun teorinya secara rinci: pertama, akal secara mandiri bisa mengetahui dan mendapatkan al-mashalah dan al-mafasid, istiqlal al-uqul biidrak al-masalih wa al-mafasid. Kedua, maslahah adalah dalil syar’i yang mandiri, tanpa terkungkung teks, al-maslahah dalil syar’iy ‘an al-nushuh. Ketiga, maslahah adalah dalil syar’i mandiri terhadap aspek muamalat dan adat, al-maslahah dalil syar’iy lil mu’amalah wa al-adah.
Benarkah penilaian ini? Ternyata Muhammad Roy Purwanto dalam disertasinya yang dibukukan dengan judul Dekonstruksi Teori Hukum Islam (Kaukaba, 2014) menilai al-Thufi tidak konsisten. Kemudian secara mendalam Purwanto mengkritik secara ideologis dan epistemologis konsep maslahah al-Thufi.
Pertama, kritik ideologis, pada awal konsep maslahah al-Thufi sangat rasional, akan tetapi dalam rincian dan pendasaran konsepnya, al-Thufi terpasung oleh hegemoni teks, seperti terlihat dalam contoh-contoh yang ia berikan. Ini sebenarnya bukan kesalahan yang disengaja oleh al-Thufi, melainkan karena kondisis dan situasi di era itu, di mana penggunaan dan kekuasaan teks sangat menonjol dan menghegemoni. Akibatnya al-Thufi kena imbasnya.
Kedua, kritik epistemologis, menurut Purwanto, al-Thufi tidak konsisten dalam menggunakan akal sebagai basis epistemnya dalam membangun konseo maslahahnya. Maslahah menurut al-Thufi adalah dalil paling kuat, tapi dalam realita dan prakteknya justru masih terjebak ke dalam pusaran teks. Begitu juga al-Thufi tidak memsistematisasi konsep, teori dan definsi yang jelas tentang maslahah. Akibatnya tidak aplikatif, dan konsep maslahahnya belum siap pakai.
Apapun itu, al-Thufi sudah memancing debat berkepanjangan dan menumbuhsuburkan diskusi tentang maslahah. Al-Thufi adalah nama yang tidak boleh absen ketika berbicara tentang maslahah.
Wallahu A’lam.



