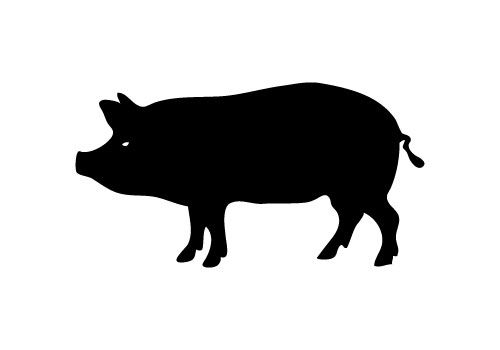
Persoalan rendang yang mengandung bahan non-halal baru-baru ini sedang ramai diperbincangkan, khususnya di dunia maya. Pemilik restoran yang menawarkan menu tersebut bahkan sudah diminta keterangan oleh pihak berwajib, dan mengklarifikasi apa yang telah dilakukannya. Namun, sepertinya persoalan tidak selesai begitu saja.
Di media sosial, saya justru mendapati postingan yang agak ngegas dari seorang politisi, Fadli Zon. Dia menyebut bahwa memasukkan daging babi ke menu masakan padang bisa melukai orang Minang. Dengan percaya diri, Fadli Zon juga menyematkan prinsip orang Minang ‘adat bersendi syarak, syarak bersendi Kitabullah’ untuk melegitimasi makanan khas orang minang tersebut dikenal halal.
Bagaimana kita sebaiknya menyikapi hal ini? Sebelum dijawab, kita rasanya perlu tegas dalam mengulik persoalan ini dengan kepala dingin dan niat untuk belajar, bukan menyerang membabi buta.
Sebab, titik krusial dalam permasalahan rendang babi adalah identitas. Bisa dicek bagaimana perdebatan terkait “Rendang” yang selalu diasosiasikan sebagai jati diri sebuah wilayah yang mayoritasnya Muslim. Agama yang bertumpuk dengan identitas suku, selain Padang atau Minang, Banjar adalah contoh terdekatnya. “Suku ya agama, agama ya suku” tulis Hairus Salim saat menggambarkan masyarakat Banjar.
Masalahnya, kita cukup sering terjebak pada fanatisme yang menjurus pada kekerasan. Terlebih di era internet hari ini, perundungan siber mudah sekali dijumpai di linimasa kita. Jangan-jangan kita juga sering melakukannya. Untuk itu, kita harus lebih hati-hati dan tenang mengulas hal ini. Tanggapan politisi di atas sangat tidak bijak, maka jangan ditiru.
Terus, apakah rendang adalah identitas orang Minang? Bisa jadi. Sebagaimana keributan ini bermuara, identitas seharusnya tidak melekat pada benda, termasuk rendang. Namun, dia adalah simbol daripadanya. Jadi, apakah memasukkan daging babi pada masakan rendang itu bermasalah? Di titik ini kita harus mengambil jalan berputar terlebih dahulu sebelum memahami permasalahan ini, yakni melihat bagaimana permasalahan makanan ini menjadi simbol?
Selain identitas yang bersisian antara suku dan agama, saat Islam berjumpa dengan masyarakat Minang juga ada proses halalisasi. Alasan inilah menurut Fadly Rahman, pakar sejarah makanan, yang saya kutip dari wawancaranya di bbc.com, nilai-nilai tradisi yang dimiliki dan dipegang masyarakat Minangkabau sebaiknya dihargai sebagai kearifan lokal.
Artinya, identitas agama masyarakat Minang tentu menjadi bagian dari kearifan lokal yang harus dihargai. Rendang sudah diakui sebagai teknik dan proses mengolah makanan untuk diawetkan. Jadi, daging rendang adalah hasil pengolahan daging dari proses dan teknik olahan tersebut. Islam mulai memberi pengaruh besar dalam proses tersebut dengan panduan kehalalan yang harus diikuti masyarakat Minang sebagai Muslim.
Irisan inilah yang menjadikan rendang babi menjadi “bermasalah”. Ajaran Islam yang mengharamkan babi, jelas tidak memberi “ruang” untuk masuk dalam olahan tersebut. Sehingga, selama yang mengolah rendang adalah masyarakat Minang jelas saja babi tidak akan masuk daftar mereka.
Namun, kembali kita ingatkan, bahwa permasalahan ini adalah soal identitas yang saling bertumpuk dan bersilangan. Ada dua hal yang perlu kita renungi persoalan identitas terkait rendang ini. Pertama, ikatan suku dan makanan. Ketika babi masuk sebagai daging yang diolah rendang jelas sekali mengunjang kesadaran kita, yang selama ini sudah tersetting bahwa rendang terasosiasi dengan identitas keislaman masyarakat Minang.
Kedua, ilusi identitas tunggal. Menukil dari penjelasan Amartya Sen, ekonom dan filsuf kelahiran India, dalam buku Kekerasan dan Identitas bahwa identitas kita sebagai manusia tidak mungkin tunggal, apalagi dipaksa tunggal. Mungkin apa yang dijelaskan oleh Sen tidak berhubungan dengan makanan, dan lebih terfokus pada kehidupan manusia modern.
Namun, dari ulasan Sen, kita sebenarnya telah belajar, di dunia modern yang batas-batas primordial mulai mengabur, karena kemajuan teknologi transportasi dan internet, orang semakin sulit diidentifikasi atas satu identitas saja. Apakah rendang yang sudah melekat pada masyarakat Minang bisa seperti itu? Jelas saja.
Mari kita coba ulas bersama. Disebut di atas, rendang adalah salah satu kearifan lokal masyarakat Minang. “Lokal” yang disebut oleh Fadly Rahman di atas merupakan bersisian dengan apa yang kita sebut “Asli” dan “Tiruan”. Rendang yang asli dan bagian dari kearifan lokal tidak saja terkait teknik dan proses, namun juga terkait rempah yang ada dan berbagai hal lainnya yang terkait kehidupan masyarakat Minang.
Jadi, masyarakat Minang adalah Muslim, maka keaslian yang dikaitkan dengan mereka juga terkait dengan identitas mereka tersebut, termasuk agama. Babi tidak akan pernah masuk daftar bahan yang diolah karena identitas mereka melarangnya. Identitas adalah salah satu hal yang membentuk perilaku.
Sebelum lebih jauh, saya ingin cerita soal salah satu makanan favorit di Banjar, yakni Ketupat Kandangan. Memang berbeda dengan rendang yang telah memiliki “pakem” dalam prosesnya, Ketupat Kandangan tidak ada dalam daftar hak cipta makanan. Cara pengolahan ikan yang diasapi, kuah, atau tingkat kematangan ketupat jelas sangat beragam.
Suatu hari, saya pernah diajak ayah saya untuk menyantap Ketupat Kandangan di salah satu tempat favoritnya. Menariknya, di warung makan tersebut yang mengolah dan berjualan adalah suami-istri asal luar Kalimantan, bahkan dijual di luar tempat asalnya, yakni Kandangan. “Apakah ketupat ini masih asli Kandangan?” canda saya sembari bertanya pada ayah saya. “Jelas saja” begitu jawab singkatnya.
Belakangan, ayah saya menjeleaskan jawabannya. Menurutnya, orang luar Kalimantan itu telah belajar dengan orang yang tepat, entah dia berasal dari Kandangan atau tidak, untuk membuat menu tersebut.
Keaslian sebuah menu atau teknik mengolah makanan adalah persoalan kompleks, sebagaimana kehidupan kita sebagai bangsa yang sangat beragam ini. Ada cerita lagi untuk menggambarkan bagaimana sengkarut persoalan ini di tengah kehidupan kita hari ini.
Pernahkah anda merindukan satu menu makanan, namun pada akhirnya mie instan jadi solusinya? Saya pernah mengalaminya. Saat ingin sekali memakan soto banjar, Indomie dengan cita rasa Soto Banjar akhirnya jadi solusi mengatasi kerinduan tersebut.
Mengapa bisa demikian? Saat masih kuliah dulu, saya pernah terlibat perbincangan soal Indomie. Saat itu seorang teman diskusi saya bertanya, bagaimana perusahaan Mi Instan bisa “membajak” cita rasa dari seluruh Indonesia tanpa ada yang protes. Hanya dengan beberapa gram bumbu, satu mangkok mie instan dapat menggantikan satu piring soto. Bisa dibayangkan bagaimana absurd dinamika ini.
Baca Juga, Mengapa Babi Diharamkan dalam Islam, Ini Alasannya
Dua cerita di atas, bagi sebagian orang, tidak setara dengan memasukan babi dalam olahan rendang. Namun, dua cerita di atas memberikan kita sudut pandang baru soal “asli” atau “kearifan lokal” terkait makanan. Kompleksitas dalam identitas makanan kita semakin masuk ke wilayah abu-abu, dan mungkin saja kita juga masih mempertanyakan “apakah makanan ini tetap punya identitas asli, jika masuk entitas baru dalam bumbu, rempah, hingga cara mengolahnya?”
Pepatah Arab berbunyi, “Kencingi sumur Zam-zam, maka kamu akan terkenal”. Mungkin banyak orang menuduh penjual rendang yang memuat babi sebagai unsur di dalamnya adalah mencari ketenaran. Sebaiknya, kita yang harus melakukan refleksi atas tuduhan tersebut, jangan-jangan kita yang malah melakukan apa yang di sebut “menunggangi gelombang”
Fatahallahu alaina futuh al-arifin



