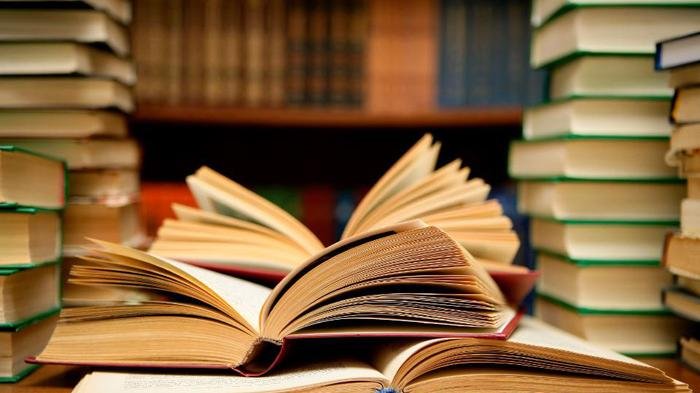
Setelah serangkaian teror yang melanda negeri beberapa waktu silam, pihak kepolisian bergerak cepat dengan melakukan penangkapan para terduga teroris. Salah satu hal yang layak dicermati dalam penangkapan teroris adalah ditemukannya sejumlah “buku jihad”. Misalnya, ketika polisi melakukan penangkapan terduga teroris di Mojokerto pada 17 Mei 2018, mereka menyita 28 buku terkait “jihad”.
Penemuan buku dalam penggrebekan terduga teroris sebetulnya bukan hal baru yang mengejutkan. Sebelumnya, dalam sejumlah penangkapan terduga teroris, polisi juga menemukan “buku jihad” di kamar kos atau rumah kontrakan. Hanya saja, masih terdengar suara-suara sumbang terkait hal itu: menyatakan bahwa buku-buku itu sengaja ditaruh oleh polisi. Suara serupa itu lazimnya berasal dari mereka yang meyakini aksi teror sebagai bentuk pengalihan isu, konspirasi dan upaya menyudutkan Islam.
Memang kita boleh saja bertanya: seberapa relevan buku menjadi alat doktrin di masa sekarang? Apakah para terduga teroris itu masih memiliki romantisme membaca buku sebagaimana dilakukan oleh orang-orang di masa silam? Pun demikian, penemuan buku jihad di rumah atau kamar kos terduga teroris sejatinya masuk akal belaka. Sama masuk akalnya menemukan buku-buku karya Cak Nur di kamar kos aktivis HMI dan buku-buku Gus Dur di rumah kontrakan anak-anak PMII.
Membincang buku dan jihad, saya teringat salah satu hasil penelitian Pascasarjana UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Pusat Pengkajian Islam dan Masyarakat UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Penelitian bertajuk Literatur Keislaman Generasi Milenial itu mengungkap banyak hal menarik. Penelitian yang dilakukan di 16 kota di Indonesia itu hendak mengetahui bacaan apa saja yang diserap dan diakses oleh generasi milenial Indonesia hari ini.
Penelitian itu menemukan lima corak literatur keislaman yang diakses generasi milenial: jihadi, tahriri, salafi, tarbawi, dan islamisme populer. Rangkuman penelitian itu disajikan dengan ringkas dan menarik dalam sebuah video pendek. Salah satu informasi menarik penelitian itu adalah bahwa literatur jihadi memang kerap dijadikan rujukan oleh pelaku teror. Literatur itu berciri: menggambarkan dunia dalam keadaan perang, sehingga umat Islam perlu berjihad, di mana saja. Buku-buku bercorak jihadi beredar di kelompok terbatas.
Menariknya, buku bercorak jihadi ini diproduksi di Solo, kota kelahiran Jokowi. Adalah penerbit Jazera dan Era Intermedia yang menjadi ujung tombak. Kedua penerbit itu menerbitkan buku Tarbiyah Jihadiyah dan Jihad Jalan Kami. Buku bercorak jihadi relatif tidak laku di pasar. Persebaran utamanya hanya di Solo, Bogor, Yogya dan beberapa kota lain. Solo tampaknya patut diberi garis bawah, mengingat ia adalah kota dengan penerbit buku islamisme dan jihadisme tersubur
Sementara itu, buku bercorak tarbawi berkembang seiring arus gerakan tarbiyah di kampus-kampus di Indonesia tahun 90-an. Buku-buku itu mempromosikan gagasan Ikhwanul Muslimin dengan tokoh-tokoh seperti Hassan Al Banna, Sayyid Qutb, dan Said Hawwa. Menurut penelitian, buku para ideolog itu hanya dibaca para aktivis tarbiyah senior, sedangkan level pemula/junior membaca karya penulis seperti Solihin Abu Izzudin dan Salim A Fillah.
Penelitian Pascasarjana UIN Yogyakarta dan PPIM UIN Jakarta itu juga menyimpulkan bawah meski perkembangan teknologi sudah sedemikian maju dan masif, tapi buku cetak masih menjadi sumber pemahaman Islam generasi milenial.
Selain itu, ternyata, literatur keislaman yang tersedia di pasaran bukan berasal dari kelompok Islam arus utama seperti NU dan Muhammadiyah.
Mencermati peta literatur keislaman generasi milenial tentu penting dan menarik. Dari sana kita bisa membayangkan wajah generasi milenial muslim Indonesia di masa mendatang. Meskipun bacaan bukan satu-satunya faktor pembentuk.
Kiranya kelompok Islam damai dan Islam ramah juga perlu lebih kreatif dan massif menghasilkan buku cetak dengan sasaran anak muda. Sebagaimana rekomendasi penelitian tersebut di atas. Dan tidak hanya berfokus pada dunia maya.



