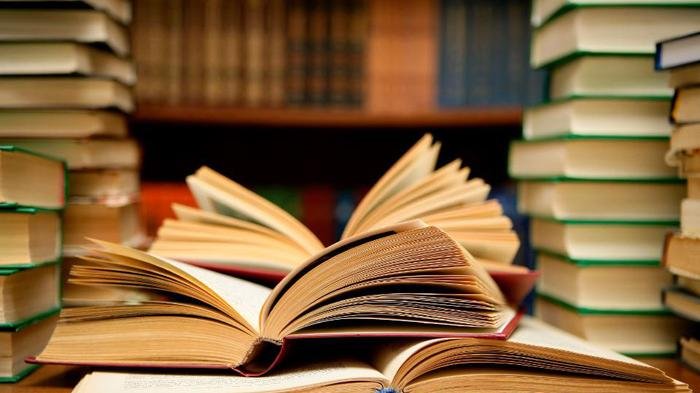
Buku adalah jendela dunia. Melalui buku kita bisa belajar banyak hal. Karenanya, membaca itu sangat penting, supaya kualitas pengetahuan kita semakin meningkat. Kalau pengetahuan meningkat, menyikapi berbagai macam persoalan akan terasa mudah. Peradaban Islam pada masa dulu sangatlah maju. Produk pengetahuannya sangat banyak dan beragam. Kemajuan peradaban Islam ini tentu tidak terlepas dari semangat membaca para ilmuwan dan ulama masa itu.
Syekh Abdul Fattah Ghuddah menulis sebuah buku yang menjelaskan banyak hal tentang produktifitas dan semangat keilmuan ulama dulu. Buku itu berjudul Qimah al-Zaman ‘Indal Ulama. Dalam buku tersebut, Syekh Abu Ghuddah, menyebut beberapa ulama yang kesehariannya tidak pernah lepas dari buku. Di antara ulama itu sebagai berikut:
Imam al-Jahidz (163-255 H), ulama pakar kajian bahasa, biologi, zoologi, dan teologi. Kebiasaanya adalah pantang menutup buku sebelum mengkhatamkannya. Bahkan rela membayar uang sewa toko buku. Harapannya, supaya diperkenankan bergadang dan menginap sementara waktu. Membaca dan menelaah koleksi buku di dalamnya.
Imam al-Fath bin Khaqan (247 H), ulama putra bangsawan dinasti Abbasiyah. Tokoh kepercayaan Khalifah al-Mutawakil. Setiap hari, saat berkantor ke istana, beliau selalu menyelipkan buku di bajunya. Ketika jeda pertemuan dengan sang khalifah, bersegera buku dikeluarkan dan dibaca. Bahkan saat jeda untuk ke toilet, sambil jalan, buku itu terus dibaca.
Imam Ismail bin Ishaq (200-282 H), ulama pakar fiqih madzhab Maliki. Pemegang tampuk qadhi kota Baghdad. Dalam kesehariannya, tidak pernah lepas dari buku. Dimana pun dan kapanpun. Imam al-Mubarrid (al-Mubarrad), tokoh yang sering muncul di pelajaran nahwu-sharaf, bersaksi bahwa tidak pernah melihat Imam Ismail bin Ishaq, kecuali dalam keadaan membaca buku, membolak-balikan halaman buku, atau sedang mencari-cari judul buku di depan tumpukan buku.
Imam Ibnu Suhnun (202-256 H), ulama pakar hadis madzhab Maliki. Malam-malamnya dihabiskan untuk bergadang. Meriwayatkan hadis dan menuliskannya. Hingga tidak sempat dan lupa menikmati hidangan makan malam yang disajikan oleh istri tercinta.
Imam Tsa’lab (200-291 H), ulama pakar ilmu qiraat dan nahwu-sharaf. Dulu pertama kali saya dengar nama ulama ini saat belajar i’lal di Madrasah al-Asna Ringinagung Kediri. Dalam kesehariannya, Imam Tsa’lab tidak pernah libur dari belajar dan mengajar. Bahkan, ketika ada undangan, ulama kota Baghdad ini mengajukan satu syarat. Berkenan hadir jika diizinkan datang dengan buku seraya menelaahnya.
Sudah barang tentu, nama-nama ini baru sekian persen mewakili ulama abad II-III H. Namun demikian, dengan menngunakan “sociological imagination” kita dapat merasakan denyut spirit keilmuan di masa itu. Spirit yang sekarang hidup di dunia akademik Barat dan dalam beberapa abad terakhir, dicoba untuk dihidupkan lagi di dunia Timur.



