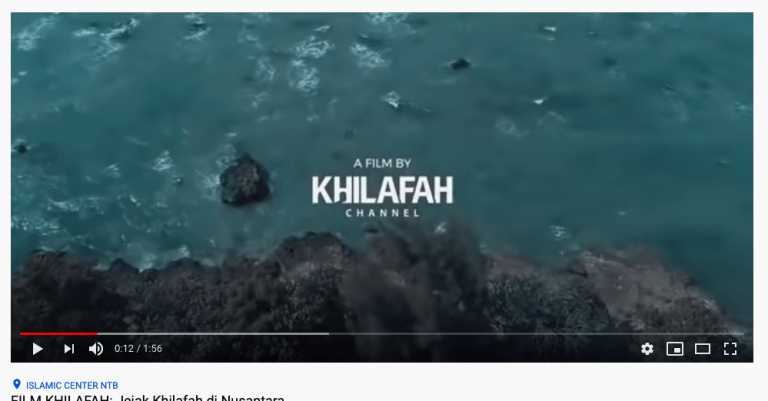
Oleh dua kawan dari Banjar dan Bandung, saya diminta berkomentar mengenai pemutaran film “Jejak Khilafah di Nusantara” yang dibuat oleh (bekas) aktivis Hizbut Tahrir Indonesia. Saya awalnya enggan untuk berkomentar. Tapi saya agak gelisah. Pada 1 Muharram 1442 Hijriah, siang hari, saya kemudian menonton beberapa cuplikan film tersebut.
Dari rangkaian fragmen yang saya tonton, unsur propagandanya lebih kentara ketimbang pelajaran sejarahnya. Beberapa fragmen itu seperti sudah cukup untuk melihat maksud dari apa yang ingin disampaikan pembuat film. Saya tidak berkompeten untuk menelisik lebih jauh bagaimana latar belakang pembuatan dan peluncuran film ini di tengah wabah dan krisis kepemimpinan. Yang akan menjadi sorotan opini ini ialah sikap kita pada sejarah Islam pada umumnya.
Apakah jejak khilafah Islam sejak Umayyah hingga Usmani ada di Nusantara? Jawaban singkatnya, tentu ada. Tapi, itu bersifat tidak tentu alias sporadis.
Imperium Usmani relatif memiliki jejak yang bisa dilacak, baik secara politik-diplomatis dan kultural-intelektual. Saya berani bertaruh, kaitan intelektual-budaya-keagamaan jauh lebih banyak bisa digali ketimbang aspek politik-diplomatis. Ini semata-mata karena arsip dan manuskrip yang tersedia menuntun kita untuk mengembara ke wilayah sejarah budaya global secara kreatif ketimbang melulu bersikukuh pada sejarah kekuasaan atau melihat periode sejarah berdasarkan siapa yang berkuasa di Istanbul.
Meskipun harus menilik sejarah politik, para sultan Usmani pasca-penaklukan penguasa Mamluk pada 1517 yang berperan sebagai para khalifah menggantikan kedaulatan khilafah di Kairo tidak perlu dianggap sebagai pusat politik Islam global. Anggapan awam yang menghinggap dalam benak para aktivis Muslim lintas-ormas ialah bahwa sultan memerintah politik Islam secara manunggal di seluruh dunia Muslim. Ini keliru. Gagasan pan-Islamisme dan ‘dunia Muslim’ sendiri lahir dan berkembang baru sejak abad ke-19. Belum lama. Sebelumnya dan apalagi sepanjang negara-bangsa terbentuk, realitas politik umat Muslim tidak pernah tunggal, tidak sentralistik.
Tengah abad ke-16, Sultan Aceh Alauddin al-Kahar pernah mengirim surat dan meminta bantuan Sultan Suleiman Kanuni untuk menghadapi kafir Portugis dalam rangka untuk melindungi lalu lintas haji dan perdagangan di Samudera Hindia. Suleiman meninggal alamiah di tenda di tengah perang Szigetvár di Hungaria dan tak sempat menerima surat dan utusan Aceh di Istanbul. Penggantinya, Selim II, lalu mengirim bantuan besar yang membuat hubungan Aceh-Usmani terkenang hingga kini, salah satunya beberapa meriam dahsyat dan bala tentara Turki. Abad ke-19, ketika Aceh meminta bantuan kembali karena menghadapi kumpeni Belanda, Imperium Usmani sudah menciut dan terlalu sibuk untuk mengatasi reformasi dan modernisasi internal.
Kondisinya pun sudah berbeda sama sekali. Belanda punya perwakilan diplomatik di Istanbul. Istanbul punya konsul di Batavia. Jika ingin diteliti lebih dalam lagi, hubungan antarimperium pada masa ini sangat pragmatis. Sementara para aktivis Muslim terbuai dengan romantisasi kebesaran dan persatuan umat yang belum tentu ada.
Mereka misalnya terbuai dengan narasi serial film Payitaht: Abdülhamid, yang menyorot sultan terakhir Usmani dengan iklim politik pada masa itu. Salah satu episodenya menyorot surat dari Aceh, seolah-olah Aceh ialah sejarah Turki.
Padahal, jalan sejarah Aceh dan Turki punya rutenya sendiri dan tidak bisa dianggap bahwa Turki selalu punya cengkeraman politik di Aceh. Sialnya, jika banyak sejarawan di Turki sendiri tidak menyambut gembira serial film semacam ini—contoh lainnya serial Muhteşem Yüzyıl yang lebih banyak menyorot intrik keluarga Suleiman Kanuni, atau bahkan film penaklukan Konstantinopel Fetih 1453—masyarakat Muslim umumnya suka, termasuk sebagian di Indonesia. Film lalu dianggap sebagai kebenaran, bukan hiburan semata.
Sekitar 2013, di Perpustakaan Manuskrip Süleymaniye ada seorang anak muda Indonesia yang mencari bukti bahwa Wali Sanga merupakan kiriman langsung bangsa Turki Usmani. Ia mencari manuskrip Ibnu Khaldun terkait hal ini. Tampaknya ia termakan oleh tulisan serampangan yang tersebar di Facebook yang mengungkap keterkaitan historis itu dan, sayangnya, banyak dipercayai di dalam lingkaran santri juga.
Saya heran dan menimpali anak muda itu, “Sampai kiamat pun, anda tak bakal menemukan manuskrip ini! Mustahil ada!” Saat itu saya tak menjelaskan lebih jauh tentang ketidaksinkronan antara tanggal kematian berbagai tokoh yang disebut, judul manuskrip yang palsu, dan karang-mengarang lainnya. Ini masa lanjut ketika beberapa kalangan santri ingin menguak jaringan ulama Nusantara dan Timur Tengah pada abad ke-15.
Meski hoax itu berkurang dalam tubuh Nahdliyyin, saya merasa banyak kalangan lain, termasuk Salafi dan Ikhwani yang menelan mentah-mentah keterkaitan Imperium Usmani-Wali Sanga itu. Salah satu yang belakangan aktif menyuarakan “Islam Nusantara” dengan langgam yang lain misalnya dikemukakan oleh dai kondang dari Yogyakarta, Salim Fillah. Fillah secara personal terkesan dengan metode dakwah ulama dan pejuang masa lalu. Ini yang membuat ia gencar pula untuk menggali keterkaitan antara Diponegoro dan khilafah Usmani. Sebelumnya, di lingkungan Muslim tradisional, simbol-simbol militer Usmani pada pasukan Diponegoro sudah lebih dulu luas beredar.
Di tangan Fillah, keterkaitan itu membuatnya menulis karya fiksi Sang Pangeran dan Janissary Terakhir. Merasa penasaran, saya lalu membaca bagian awal novel ini dan kecewa, karena ketidaksinkronan antara tahun meninggal pimpinan Yeniceri (Janissary) tahun berlangsungnya Perang Jawa yang melelahkan Belanda itu. Sebagai penyuka genre realisme, saya membaca karya fiksi ini merusak imajinasi saya. Padahal jika dikemas dengan runut sejarah yang baik dan cerita yang memikat, novel ini akan dibaca dan diterima luas. Kendati, kaitan historis di antara Yeniceri dan Diponegoro itu tidak ada. Tampaknya, oleh banyak pengikut sang ustad karangan fiksi ini dianggap sebagai fakta itu sendiri.
Salah satu masalahnya terletak pada minimnya verifikasi historis pada tokoh dan peristiwa masa silam. Beberapa waktu lampau, beberapa media daring menelisik ‘sisi gelap’ alkohol dan perempuan dalam kehidupan Diponegoro yang—dalam timbangan hagiografis para pencinta narasi jihad dan penaklukan Islam sepanjang sejarah—dianggap menodai. Sisi gelap ini sudah diungkap beberapa sejarawan. Tapi rupanya ini ditanggapi sebagai penyerangan terhadap Islam atau tokoh Islam oleh sebagian pihak. Diponegoro dianggap suci bersih.
Tak hanya sang pangeran, Yeniceri pun dalam cara berpikir Fillah, setidaknya, dipandang sebagai tentara Muslim yang suci dengan simbol keislaman yang kuat, bukan sosok serupa jenderal militer abad ke-20 yang penuh dengan intrik. Ini yang membuat sulit untuk menulis sejarah secara kritis berdasarkan timbangan sumber yang baik.
Jika mau ditimbang, setidaknya sejak satu dekade belakangan kini pergulatan akan arsip dan sejarah Islam terjadi dalam tubuh umat Muslim Indonesia. “Islam Nusantara” sebagai tema dan simbol Nahdlatul Ulama ditanamkan resmi sejak 2015, meskipun kesadarannya sudah lama berakar. Lambat laun, kelompok lain pun mengikuti dengan narasi, pembacaan dan imajinasi yang berbeda. Kelompok non-Nahdliyin pun belum tentu satu suara dalam merebut narasi sejarah Muslim di Nusantara ini.
Terlepas dari agenda masing-masing, kontestasi wacana ini menurut saya akan mendorong semangat baru bagi generasi lebih muda dalam menggali masa lalu: narasi sejarah pra-negara bangsa dengan skala dan konfigurasi yang jauh lebih luas antara berbagai agensi dan struktur, antara yang makro dengan yang mikro, antara yang lokal dengan yang global. Para sejarawan profesional yang “netral” tampaknya akan terus kecewa dengan hasil dari kontestasi “awam” itu, terutama karena hasilnya akan selalu bersifat politis dan kebanyakan tidak kritis. Siapa tahu generasi lebih muda ini cenderung akan menjadi kaum sejarawan profesional. []
Zacky Khairul Umam, mahasiswa doktoral sejarah dan kajian Islam di Freie Universitaet Berlin, Jerman; pernah belajar filologi dan sejarah Turki Usmani di Istanbul 2012-2014.



