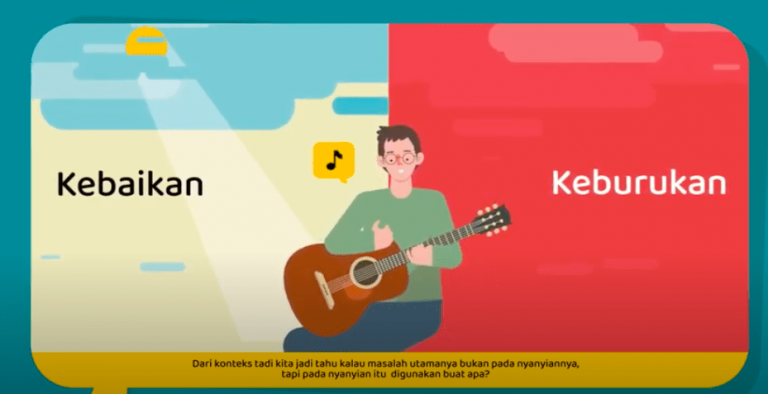
Apa yang tersirat dalam pikiranmu ketika kau menemui fase di mana mimpi yang sebelumnya begitu kau idamkan berubah bentuk jadi kutukan?
Pada siang bolong yang terik di bulan Ramadhan 2018, saya pergi ke kampus dan mendapati gedung kuliah begitu lengang. Muncullah ide menulis sebuah puisi amatir yang berisi puja-puji kepada Tuhan kala itu dengan maksud hati menuangkan rasa syukur. Tepat di teras belakang tempat anak-anak jurusan saya biasa latihan alat musik tiap sore, saya mengenang kembali kilas balik perjalanan panjang mendaftar di kampus ini, tepatnya di jurusan musik. Saya ingat betul, bagaimana perjuangan saya beradu argumen dan berhasil meyakinkan Ibu agar merelakan saya merantau di kota yang banyak dikata orang sebagai kota pelajar.
Bulan-bulan awal saya melakoni pengalaman pertama sebagai anak rantau rupanya tak semulus imaji. Penyesuaian dengan lingkungan baru, cara hidup baru, dan mesti belajar bejibun teori serta praktik di jurusan musik yang kompleks menjadi masalah serius, pasalnya saya bukan orang yang mudah bergaul dan tak pernah jauh dari keluarga.
Sebagai lulusan SMA biasa yang tidak memiliki basis pengetahuan musik yang memadai, saya jadi kalang kabut menghadapi teori dan praktik yang materinya begitu asing. Singkatnya, tahun pertama saya di kota orang kala itu naudzubillah pelik. Meski begitu, pada akhirnya saya tetap survive dan berhasil melewati satu dua semester dengan senang hati belaka.
Memasuki awal semester tiga, saya memasuki sebuah babak baru, titik di mana saya mulai menemukan perasaan baru yang begitu cepat bermutasi menjadi sebuah fragmen terpenting dalam kehidupan saya.
Berangkat dari keinginan memperbaiki dan membersihkan diri dari tumpukan dosa masa lampau, saya kemudian tergerak untuk, sebut saja, berhijrah. Seperti kebanyakan orang yang menimba ilmu agama via YouTube dan media sosial lainnya, saya lekas mendapatkan ‘guru’ dengan arahan algoritma yang tentu saja mengacu pada penceramah-penceramah kondang di media sosial.
Gelembung algoritma seperti menjejali saya dengan informasi homogen. Tak ada kajian literatur ataupun pembahasan mendalam yang saya ikuti. Seluruh isi pemahaman saya akan agama adalah bentuk kepercayaan yang ditelan mentah-mentah dari kumpulan video ceramah yang terakumulasi benar salah berdasarkan kesimpulan para penceramah panutan saya. Pandangan saya adalah pandangan yang berasal dari satu sisi wajah tafsir tanpa wacana pembanding. Tentu saja ini sangat buruk. Keyakinan semacam ini begitu rentan dan mudah terbakar bahkan oleh hal-hal paling remeh sekalipun.
Sejalan dengan semangat hijrah yang mulai tumbuh, pandangan hidup saya secara keseluruhan mengalami gegar budaya dan seolah cenderung harus dibenahi ulang agar sesuai dengan syariat Islam murni.
Saya menemui titik di mana musik jadi bagian riskan dalam kehidupan sehari-hari, sehingga menuntut saya agar segera meninggalkannya. Ya, musik tak lagi merdu di telinga, wajah buram dunia musik yang lahir dari budaya hura-hura bagi saya hanyalah melahirkan kesia-siaan. Setiap nada yang keluar instrumen musik yang dimainkan terasa seperti teriakan setan.
“Musik pastilah sangat dilaknat Allah dan Rasul, mengingat seorang penceramah pernah berkata bahwa ia adalah tunggangan setan untuk melalaikan manusia. Ia adalah media bersenang-senang kaum kafir yang lekat dengan dosa. Hal ini tentulah berseberangan dengan prinsip hijrah,” pikir saya waktu itu.
Maka tepat di hari yang begitu membingungkan, saya menemui sebuah dilema berat tentang keinginan untuk meninggalkan jurusan musik yang dulu saya pilih secara sadar dan melewatinya pun dengan perjuangan yang tidak mudah.
Pandangan saya yang telah begitu saklek pada apapun dalam hidup menemui jalan buntu. Seketika mimpi yang dahulu sempat saya agungkan keberadaannya berbalik jadi momok yang mengerikan, sebab tak mudah bagi saya untuk lepas karena banyaknya pertimbangan. Musik serasa membawa saya sejengkal lebih dekat dengan api neraka.
Sayangnya, nyali saya tak cukup sepadan dengan bayangan kegetiran hati orang tua saya yang telah mencurahkan kepercayaan dan beaya mesti menelan kekecewaan sebab saya memutuskan berhenti kuliah hanya demi gejolak spiritual sesaat. Maka, jalan tengah yang saya ambil pada akhirnya adalah menjalani sisa masa studi dengan setengah hati. Dan, belakangan, saya menyayangkan proses belajar di jurusan musik yang saya lewatkan begitu saja.
Bersamaan dengan memudarnya semangat hijrah dalam diri saya, pandangan hitam-putih dalam hidup saya pun mulai berubah. Saya lalu tesadar bahwa semua kepercayaan puritan yang lagi-lagi dipicu kebiasaan menerima secara serampangan dogma yang disampaikan dalam media sosial atau internet menciptakan keyakinan ekstrim. Ia seperti memberi harapan yang begitu bersinar namun sekaligus meliyankan aspek kehidupan lain, musik salah satunya. Saya gagal menyadari bahwa musik adalah salah satu jenis keindahan ciptaan Tuhan yang patut disyukuri juga keberadaanya, alih-alih mengutuk.
Dalam tradisi tasawuf, umpamanya, musik justru menjadi faktor esoteris yang membantu memusatkan konsentrasi dan menghilangkan kekacauan pikiran dalam pencarian makrifat oleh kelompok sufi. Pada masa ke-sunan-an, musik bahkan menjadi media dakwah yang terbukti membuat Islam diterima masyarakat Nusantara melalui wajah ramahnya.
Kemalasan saya untuk berpikir kritis dan batasan yang saya ciptakan sendiri melalui apa yang boleh dan tidak boleh menurut yang dikatakan para penceramah tanpa sadar menutup kemungkinan masuknya wacana lain. Alhasil, saya terus berkecimpung dalam narasi yang sama, aliran yang seragam. Ini terbukti ketika, saya menolak rekomendasi video dari teman tentang pembahasan isu gender di sebuah channel YouTube. Alasanya, karena penceramah panutan saya pernah berkata bahwa konten channel YouTube tersebut dibuat oleh seorang perempuan muslimah yang disebut liberal. Penceramah itu menduga konten tersebut mungkin menyelipkan pesan-pesan ‘melenceng’. Tanpa pikir panjang saya pun mengamini.
Ketidaksiapan saya dalam menghadapi kontestasi wacana di dunia digital itu secara ampuh melahirkan pemahaman yang keliru dan bukan tidak mungkin melahirkan tindakan yang bisa saja lebih ekstrim dari keinginan keluar kuliah.
Pada akhirnya, kegagalan saya dalam memahami diri sendiri berakibat pada hilangnya arah dan tujuan hidup. Di sanalah seharusnya ruang berpikir hidup dan pada akhirnya menghasilkan keyakinan diri yang lahir dari buah pikir sendiri. Jika mimpimu adalah bagian dari buah pikir yang lahir dengan penuh kesadaran, maka perjuangkanlah.



