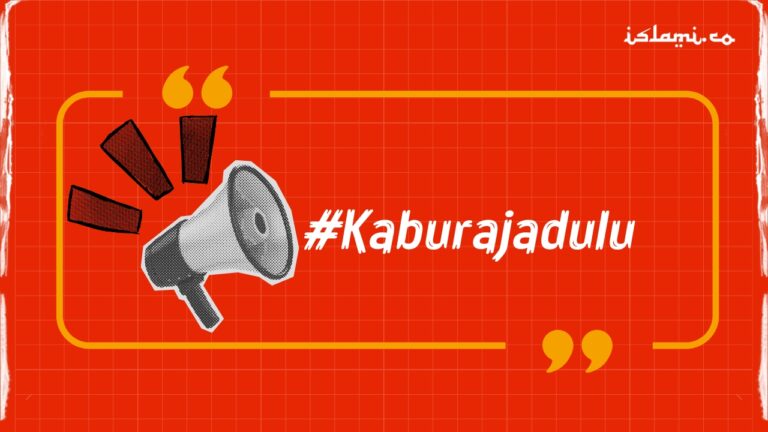
Beberapa hari ini netizen di beragam platform media sosial menunjukkan rasa frustasi atas beragam masalah dan krisis yang terjadi di Indonesia lewat tren #KaburAjaDulu sebagai ajakan untuk tinggal atau menetap di luar negeri. Ini adalah bentuk kekecewaan akan buruknya performa pemerintah yang dipandang inkompeten dan menelurkan kebijakan-kebijakan yang meresahkan masyarakat.
Diskusi dalam tagar #KaburAjaDulu bertabur pengalaman, pengamatan, maupun opini, yang kesemuanya tidak lepas dari pro dan kontra. Migrasi masyarakat Indonesia ke luar negeri, baik sebagai pelajar maupun pekerja, bagaimanapun juga tidak memiliki alasan tunggal.
Di antara keluarga, kerabat, atau kawan kita mungkin ada yang memutuskan menjadi pekerja migran di luar negeri. Tak terkecuali, di Taiwan. Tulisan berikut ini disarikan dari satu momen percakapan dengan seorang ibu pekerja migran di suatu tabligh akbar di Taipei dalam rangka Hari Santri Nasional (HSN) pada Oktober tahun lalu. Apa yang membuatnya memutuskan bekerja di Taiwan? Konteks apa yang menjadikan sektor pekerja migran ini bertumbuh di Taiwan, terlebih di kalangan perempuan?
Feminisasi Buruh Migran dan Care Labor di Taiwan
Indonesia adalah penyumbang jumlah migran terbesar di Taiwan. Berdasarkan data statistik terakhir Desember 2024 lalu dari National Immigration Agency (NIA) Taiwan, total jumlah warga Indonesia di Taiwan adalah 317.559 orang, dengan proporsi 210.495 perempuan dan 107.064 pria.
International Labour Organization atau ILO menyatakan bahwa saat ini perburuhan migran telah “terfeminisasi”, atau dalam kata lain, perempuan menjadi mayoritas pengisi sektor pekerja migran, baik di bidang formal maupun informal. Salah satu contoh, kebutuhan negara tujuan akan tenaga kerja perawatan (care labor) seperti perawat lansia dan pekerja rumah tangga membuat “kerja perawatan” yang masih diidentikkan dengan “kerja perempuan” membuat jumlah perempuan migran ini meningkat. Dalam buku Negara dan Buruh Migran Perempuan karya Ana Sabhana Azmy, tercatat dalam kurun tiga dekade, saat ini jumlah perempuan mencapai tiga kali lipat lebih banyak dibanding pekerja migran laki-laki.
Taiwan menjadi salah satu negara tujuan utamanya sejak akhir 1980-an, karena kala itu ia menjadi salah satu pusat ekonomi di Asia, dan ini menarik minat banyak warga Indonesia untuk bekerja di sana. Selain itu, dalam dekade ini, Taiwan akan memasuki era sebagai super-aging society atau masyarakat yang mayoritas berumur tua. Jumlah penduduk di atas usia 60 tahun mencapai 37% atau lebih dari sepertiga populasi Taiwan, yang menjadi salah satu pemicu meningkatnya kebutuhan pekerjaan caregiver masyarakat lansia tersebut. Jika Anda googling, akan mudah kita dapati kisah para pekerja migran di Taiwan yang sehari-hari menemani dan merawat para kakek ataupun amah (nenek atau bibi tua).
Tabligh Akbar sebagai Tempat Berkumpul Pekerja Migran Indonesia
Sebagaimana pernah saya tulis tentang Islam di Taiwan, tabligh akbar yang dijubeli jamaah Indonesia adalah hal yang lumrah terjadi. Kebanyakan jamaah mengikutinya di hari libur atau bagian dari cuti bulanan mereka. Hampir tiap bulan kiai-kiai kondang diterbangkan untuk mengisi majelis dengan jumlah jamaah yang masif. Bisa dibilang, tabligh akbar menjadi lokasi bertemu masyarakat migran Indonesia – khususnya nahdliyin – di Taiwan.
Tabligh Akbar Hari Santri Nasional PCINU Taiwan kala itu menghadirkan muballigh KH. Ahmad Fahrur Rozi, salah satu jajaran ketua PBNU yang juga pengasuh PP. An-Nur 2 Malang, dan Habib Ahmad Al Hadar dari Surabaya atau yang popular dengan nama Habib AEH. Suasananya tidak jauh berbeda dengan tabligh akbar pada umumnya di Indonesia: banyak umbul-umbul, tenda besar dipasang, panggung dan sound system besar, dan stand bazaar produk-produk warga Indonesia di Taiwan.
Selain di bawah tenda besar, ada banyak jamaah yang duduk-duduk di atas rerumputan agak jauh dari panggung. Warga lokal Taiwan banyak yang beraktivitas di sekitar venue, misalnya sambil menuntun kereta bayi, dog walking, jogging, dan beragam kegiatan lain. Jamaah memberi jalan jika ada yang lewat. Sesekali warga Taiwan menengok ke keramaian dan kerumunan yang ada, namun mereka tetap melanjutkan aktivitasnya.
Saya mencari tempat teduh untuk makan gorengan yang saya beli dari salah satu kios bazaar. Saya akui susah melepaskan kudapan satu ini meski di negeri orang. Kira-kira seratus meter di belakang panggung, ada pohon pendek dan seorang ibu paruh baya sedang duduk, mengudap camilan sambil melihat-lihat ponselnya. Saya izin duduk di sebelahnya, dan kami berdua berbincang.
Setelah menanyakan apa aktivitas saya dan berapa lama saya di Taiwan, ia mengaku berasal dari Banyuwangi, dan dulu, sekitar delapan tahun lalu, ia berangkat lewat salah satu agensi tenaga kerja di Malang. “Umurku saiki wis meh 45, mas,” tuturnya.
Sejak dua tahun ini, ia mengaku bekerja menjadi caregiver seorang lansia di Taoyuan. Sebelumnya, ia menjadi pekerja rumah tangga di sebuah keluarga, sekaligus merawat lansia yang tinggal bersama mereka. “Tapi setelah majikan amah-ku yang pertama meninggal, ada yang menawari kerjaan ini.”
Ia perempuan beranak dua. Anak pertamanya, saat ini sudah SMP di Banyuwangi. Ia meninggalkan mereka bersama bapak dan keluarganya di Banyuwangi.
“Yaopo ya mas. Kerjaan sekarang susah di Indonesia, apalagi saat itu umurku sudah segitu. Siapa mau mempekerjakan? Saya pernah kerja buruh pabrikan waktu belum menikah. Tapi setelah menikah dan punya anak, saya berhenti kerja. Terus bagaimanapun anak-anak butuh sekolah, kerjone suamiku ya tidak mesti, saya memutuskan berangkat. Enak di sini, gajine lumayan, bisa kirim uang buat anakku.”
Untuk menghadiri tabligh akbar ini, ia naik MRT dari Taoyuan menuju Taipei. Kira-kira hampir satu jam perjalanan. Menurutnya, kerja terus ikut majikan bisa bikin bosan. Setiap bulan, ia menyempatkan ikut Tabligh Akbar atau pengajian. “Senang saya ada kegiatan pengajian seperti ini.” ujarnya. Setelah lama berbincang, ia beranjak bergabung bersama jamaah lainnya di bawah tenda, mengikuti semarak shalawatan yang dipimpin Habib AEH.
Mengapa Harus Menjadi Pekerja Migran?
Jika Anda mengecek berita atau penelitian seputar pekerja migran di mesin pencari, mereka mendapat label sebagai “pahlawan devisa”. Salah satu sumber devisa ini adalah tingginya remitansi atau pengiriman uang dari para pekerja. Tapi tentu pertanyaan selanjutnya, apa masalah yang menyebabkan mereka memilih untuk bekerja di luar negeri? Mengapa mereka harus berkorban “menjadi pahlawan” di negeri orang?
Kisah di atas tentu tidak bisa digeneralisasi pada seluruh pekerja migran perempuan di Taiwan. Hanya saja, dari satu kisah tersebut, kita bisa melihat banyak lapis-lapis alasan yang diceritakan ibu tersebut: problem ageism dalam pekerjaan di Indonesia, beban ganda perempuan di lingkungan keluarga, sempitnya lapangan kerja, kesulitan ekonomi, juga tingginya biaya hidup juga pendidikan dibandingkan pendapatan di daerah asal.
Pekerjaan sektor domestik di Indonesia juga sangat rentan, dan RUU PPRT tak kunjung disahkan. Arus feminisasi pekerja migran sejalan dengan meningkatnya kebutuhan pekerja domestik di luar negeri. Perempuan, yang masih diidentikkan dengan sektor tersebut, mengambil peluang tersebut dengan segala risikonya.
Menjadi buruh migran mungkin bisa jadi menjadi pencapaian yang bisa dibanggakan, setidaknya secara ekonomi. Namun, beragam pemberitaan dan penelitian menunjukkan bahwa tidak sedikit pekerja migran yang tertipu, tereksploitasi, atau mengalami beragam problem selama di rantau, baik bagi pekerja legal, terlebih yang lewat jalur ilegal. Migrasi ke luar negeri bisa punya banyak cerita personal yang getir. Menjadi pekerja migran, dalam banyak hal, adalah pertaruhan nasib dan masa depan – yang sayangnya belakangan ini, makin terasa gelap di Indonesia.
(AN)



