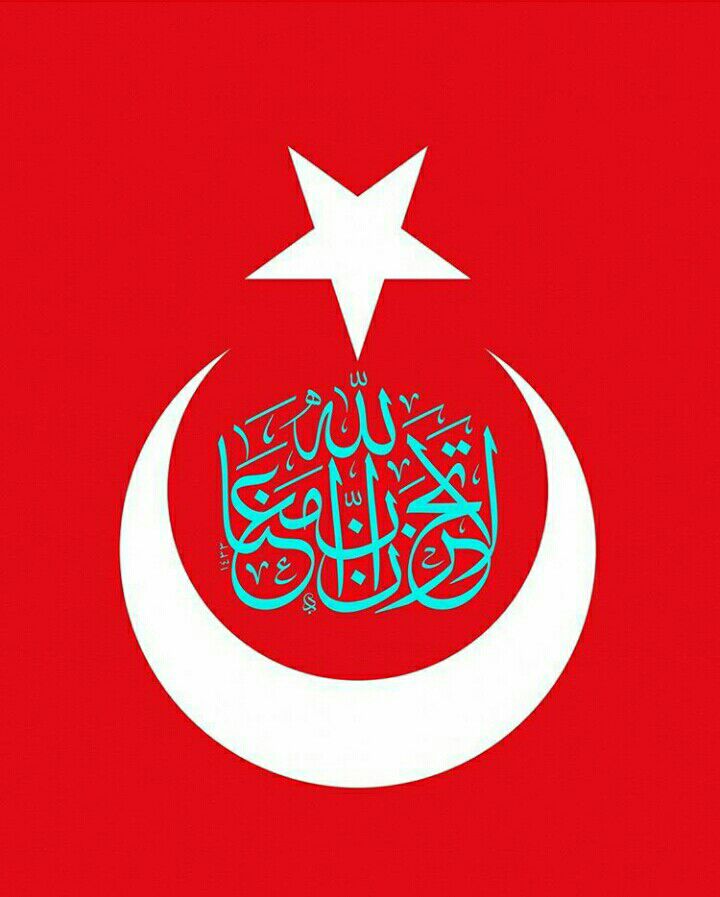
Tuan-tuan barangkali menanya: tidakkah syari’atul Islam telah mengatakan dengan nyata-nyata, bahwa agama itu mengatur negara pula, jadi bahwa agama menurut syari’at itu menjadi satu dengan negara? Akh, – di dalam hal inipun sebenarnya tidak ada ijmak yang bulat di kalangan kaum ulama. (Baca Tulisan sebelumnya: Bung Karno: Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara? Bag-1)
Di dalam hal inipun ada satu aliran, yang mengatakan, bahwa agama – agama, urusan negara – urusan negara. Misalnya di dalam tahun 1925 terbitlah di Kairo sebuah kitab tulisannya Sheik Abdarazik “Al wa usul ul hukm”, yang mencoba membuktikan, bahwa pekerjaan Nabi dulu itu hanyalah mendirikan satu agama sahaja, zonder maksud mendirikan satu negara, satu pemerintahan dunia, zonder pula memustikan adanya satu kalifah atau satu kepala umat buat urusan‑urusan negara. Sudah barang tentu Sheik Abdarazik ini dipersalahkan orang, diseret orang di muka Dewan Ulama Besar di Kairo, dijatuhi hukuman yang tidak ringan: ia diperhentikan dari jabatannya sebagai hakim, dan kalau saya tidak salah diperhentikan juga dari jabatannya sebagai profesor di dalam ilmu kesusasteraan di sekolah Al Azhar.
Tetapi adalah delictnya Sheik Abdarazik ini satu contoh betapa juga di dalam soal agama dan negara itu tidak adalah ijmak ulama.
Maka oleh karena itu, manakala di Turki kini bukan sahaja kepala-kepala pemerintahan, tetapi juga banyak ulama-ulama fiqh mengatakan, bahwa agama dan negara tidak wajiblah di tangan satu, manakala misalnya Stephan Ronart mendengar dari seorang ulama besar di Istambul bahwa faham negara itu baru kemudianlah “menjelinap” ke dalam Islam, – maka hal itu tidak lain daripada gambar ketidakadaan ijmak itu. Dan pada umumnya, – memang kita terlalu “meributkan” hal ini! Sebagian yang sudah saya tuliskan pula di P.I. nomor 13, maka terpisahnya agama dan urusan negara bukanlah di negeri Turki sahaja!
Di negeri Belanda, di Perancis, di Jerman, di Belgia, di negeri-negeri Inggeris, di Amerika di semua negeri-negeri di Amerika, di semua negeri-negeri ini agama dan negara tidak di satu tangan, dan,- di negeri-negeri koloni yang penduduknya beragama Islam, urusan agama Islam di situ juga tidak di tangan negara. Islam di India tidak menjadi satu dengan negara di India. Islam di Indonesia tidak menjadi urusan negara di Indonesia.
Lagi pula, di sesuatu negeri yang ada demokrasi yang ada perwakilan rakyat yang benar-benar mewakili rakyat, di negeri yang demikian itu, rakyatnya toch dapat memasukkan segala macam “keagamaannya” ke dalam tiap-tiap tindakan negara, ke dalam tiap-tiap undang-undang yang dipakai di dalam negara, ke dalam tiap-tiap politik yang dilakukan oleh negara, walaupun di situ agama dipisahkan dari negara. Asal sebagian besar dari anggauta-anggauta parlemen politiknja politik agama, maka semua putusan-putusan parlemen itu bersifatlah agama pula. Asal sebagian besar dari anggauta-anggauta parlemen itu politiknya politik Islam, maka tidak akan dapat berjalanlah satu usul juapun yang tidak lbersifat Islam. Tidakkah misalnya di dalam parlemen di negeri Belanda kaum Keristen merdeka menjalankan politik Keristennya?
Nah, inilah yang menurut keterangan pemimpin-pemimpinnya dituju oleh Turki-muda itu! Tersilah sekarang kepada rakyat sendiri, zonder tangannya negara, memeliharakan sendiri, menghidupkan sendiri, mengkobar-kobarkan sendiri ia punya “kemauan agama”, mengkobar-kobarkan sendiri ia punya “religieuse wil”, menyala-nyalakan sendiri ia punya jiwa keagamaan; ia punya rakyat berkobar-kobar ia punya ruh, ia punya jiwa Islam.
Jika rakyat berkobar-kobar ke-Islam-annya, tentu parlemen dibanjiri oleh ruh Islam; dan semua putusan parlemen adalah bersifat Islam; rakyat padam ke-Islam-annya, tentu parlemen sunyi dari ruh Islam dan semua putusan parlemen tidak bersifat Islam! Kalau berkobar-kobar ke-Islam-an itu, maka itulah benar-benar ruh Islam yang sejati, yang hidup sendiri, yang “laki-laki”, oleh karena berkobar-kobarnya itu karena tenaga sendiri, semangat sendiri, usaha sendiri, ikhtiar sendiri, jerih payah sendiri, tekad dan jiwa sendiri zonder asuhannya negara, zonder pertolongannya negara, zonder perlindungannya negara. Bukan lagi ke-Islam-annya itu satu ke-Islam-an “peliharaan” yang hidupnya karena selalu mendapat “cekokan obat” dari satu ke-Islam-an bikin-bikinan, yang selalu layu kalau tidak mendapat cekokan obat dari negara. Bukan lagi ke-Islam-annya itu satu ke-Islam-an yang “belum disapih”, yang segala gerak-geriknya masih perlu kepada bantuan, penjagaan, tuntunan, asuhan negara.
Dan, kalau ke-Islam-annya ini bisa berdiri sendiri zonder bantuan dan penjagaan, maka bukanlah ia pula satu ke-Islam-an, yang di dalam segala gerak-geriknya terhalang dan terhambat oleh hukum-hukum negara, sebagaimana seorang anak terhalang pula segala gerak-geriknya, dan tidak bisa menjadi manusia betul-betul, manakala seorang tua tidak tahu melepaskan asuhannya pada waktu si anak itu menjadi akil-baliq dan dewasa.
Begitulah maksud-maksud dan kehendak-kehendak pemimpin-pemimpin Turki-muda itu.
Adakah mereka punya maksud-maksud dan kehendak-kehendak itu timbul karena “teori” sahaja, atau adakah memang hal-hal dan keadaan-keadaan riil yang membawa mereka ke situ?
Inilah justru yang mau saja sajikan kepada sidang pembaca di dalam seri artikel-artikel yang sekarang ini.
Satu hal sudah saya beritahukan kepada pembaca, yakni posisinya negeri Turki di dalam pergolakan internasional di dalam tahun-tahun sesudah perang-dunia 1914-1918. Pada waktu itu soal-hidup sudahlah menjadi satu soal “to be or not to be”, satu soal “hidup atau mati” bagi negeri Turki dan bangsa Turki. Negara Turki kuat, bangsa Turki akan hidup terus, negara Turki tidak kuat, bangsa Turki akan lenyap tersapu habis dari sejarah dunia buat selama-lamanya!
Dari kanan, dari kiri, dari muka, dari belakang, dari atas, dan dari bawah musuh sedia menggempur hancur ia punya kehidupan sebagai natie, – tidak ada satupun hal di dunia ini dari mana ia boleh mengharap bantuan, melainkan dari tenaga sendiri, keuletan sendiri, kekuatan sendiri, senjata sendiri, bedil dan meriam dan organisasi kenegaraan sendiri. “We must ensure our existence”, kita musti memperkokoh kita punya diri, itulah kalimat termasyhur yang diucapkan oleh Ismet Pasja, Ismet Inonu yang sekarang, waktu ia berjabatan tangan dengan Kamal sepulangnya dari konferensi di Lausanne. Berhubung dengan keadaan internasional itu, maka perlulah sebagai kilat negara itu diperkokoh, dikonsolidasi, dipersenjatai, di-“harimau”-kan, zonder boleh memikirkan terlalu lama keberatan ini atau keberatan itu yang dikemukakan oleh fatwa-fatwa ulama-ulama. Merdeka, merdekakanlah negara itu dari ikatannya keberatan ini dan keberatan itu, karena musuh selalu sedia menerkam; tidak boleh satu detikpun hilang terbuang, tidak boleh satu-kejap matapun hilang terlengah!
Tetapi kecuali daripada desakan-desakan internasional ini, adalah pula keadaan-keadaan buruk di dalam negeri yang bukan sahaja melemahkan negara, tetapi juga melemahkan kehidupan rakyat jasmani dan rokhani yang sebagian besar adalah akibat-akibat dari tradisi-kuno dan anggapan-anggapan-kuno tentang agama Islam. Anggapan-anggapan-kuno inilah, – jadi bukan Islam sebagai Islam-, anggapan-anggapan-kuno inilah yang melemahkan rumah-tangga rakyat Turki itu di dalam urusan ekonominya dan sosialnya, di dalam “outlooknya” dan di dalam kepercayaannya. Akibat-akibat anggapan-anggapan-kuno inilah yang riil bagi pemimpin-pemimpin Turki-muda itu. Sebab, sebagai Dr. Noordman katakan di dalam ia punya buku tentang negeri Turki, bukan apa yang diajarkan oleh Islam itu yang menentukan sifat dan wujud perikehidupan rakyat, tetapi apa yang diadakan benar oleh anggapan-anggapan Islam, sebagai yang terjadi sepanjang jalannya zaman, itulah yang menentukan segala sifat dan wujud perikehidupan rakyat.
Prakteknya Islam, realiteitnya Islam, fiilnya Islam yang nyata, – itulah yang “dipegang batang lehernya” oleh pemimpin-pemimpin Turki-muda itu, bukan ajaran Islam, bukan isinya perintah dan larangan Islam, bukan teorinya Islam! Buat apakah orang membanggakan mempunyai “negara Islam”, membanggakan mempunyai satu negeri yang di situ “sabda-Allah” menjadi wet, kalau ekonominya kucar-kacir, sosiainya kacau-balau, politiknya satu anarkhi, keagamaannya megap-megap, prakteknya rumah-tangga rakyat bobrok dan busuk?
Buat apa bangga mempunyai satu “negara Islam” kalau “negara Islam” itu di dalam prakteknya kehidupan internasional dan prakteknya kehidupan sehari-hari selalu menjadi pembicaraan orang, tertawaan orang, cemoohan orang, yang menamakan negeri Turki itu “de zieke man van Europa”, yakni si orang sakit di Eropah? “Kita menamakan negeri kita negeri Islam, tetapi segala keadaan negeri kita itu menjadilah penghinaan Islam”, begitulah Mufidee Hanoum, isterinya menteri Farid Bey, bertaka kepada jurnalis Vincent Sheean yang menginterview kepadanya.
Dan apa sebab begitu? Oleh karena menurut keterangannya Kamal Ataturk sendiri “Islam di Turki itu telah menjadi satu agama konvensional karena diikatkan kepada satu negara yang konvensional”.
Oleh karena Islam itu “tidak dapat mengoreksi dirinya sendiri, karena tidak merdeka mengoreksi dirinya sendiri”.
Jadi oleh karena negara, negara yang lemah ini, negara yang tua-bangka ini, negara yang “historisch overleefd” ini, membawa Islam ke dalam kesakitannya, ke dalam kebobrokannya, ke dalam kejatuhannya, maka untuk menyembuhkan kedua-duanya, untuk menyembuhkan negara dan untuk menyembuhkan Islam, menurut pemimpin-pemimpin Turki hanyalah satu jalan yang rasionil: perpisahannya negara, negara yang lemah ini, negara Islam itu. [Bersambung]
Baca Tulisan sebelumnya:
Bung Karno: Apa Sebab Turki Memisah Agama dari Negara? (1)



