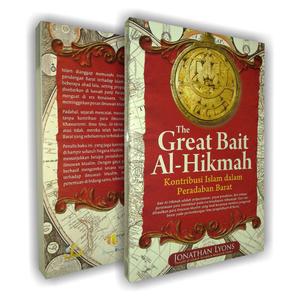
Salah satu keuntungan menjadi penerjemah atau penyunting buku adalah terpaksa membaca buku-buku yang biasanya mungkin tak akan rampung saya baca dengan cermat. Salah satunya adalah buku sejarah terbitan Nourabooks ini The Great Bait al-hikmah: Kontribusi Islam dalam Peradaban Barat (Jonathan Lyons, 2013 )
Sebagaimana lazimnya buku yang baik, buku ini selama beberapa waktu membuat saya terlempar ke masa-masa ketika peradaban Islam sedang pada puncaknya, ketika ilmu pengetahuan dan teknologi sedang marak-maraknya. Walau sebenarnya buku ini membahas tentang Adelard dari Bath, seorang penerjemah awal ilmu pengetahuan Islam ke dalam bahasa Latin, penggambaran tentang situasi mental dan keilmuan saat itu sangat memberi gambaran bagi saya yang jarang membaca buku sejarah, bahkan sejarah Islam.
Ada dua hal dari buku itu yang ingin saya bagi dalam kesempatan ini. Pertama, situasi yang terbalik antara masyarakat Barat dan Islam saat itu dengan masyarakat Barat dan Islam saat ini dalam hal menyikapi ilmu pengetahuan. Pada masa Adelard, masyarakat Barat sibuk dengan urusan agama (perang salib), dan gereja sedang kuat-kuatnya menancapkan kuku dalam setiap masalah bahkan pemerintahan, sementara masalah ilmu pengetahuan terabaikan. Mereka mengonsumsi teknologi (misalnya: astrolab) tanpa menguasai filsafat dan ilmu pengetahuan yang ada di balik teknologi tersebut (yang berasal dari peradaban Islam). Pengetahuan baru selalu mereka sikapi dengan penuh prasangka.
Sebaliknya, masyarakat Islam saat itu sedang semangat-semangatnya mengejar ilmu pengetahuan dengan dukungan penuh dari para pemimpinnya. Bait-Al-Hikmah, sebuah perpustakaan sekaligus biro penerjemahan, plus lingkar cendekiawan dan intelektual yang aktif melakukan ekspreimen-eksperimen ilmiah di dalamnya, dibangun oleh Harun Al-rasyid dan mencapai puncaknya di masa Al-Ma’mun, khalifah bani Abasiyyah.
Banyak karya yang diterjemahkan, disalin, dan ditelaah itu berasal dari Bahasa Sansekerta dan Yunani dalam bidang-bidang seperti filsafat, astronomi, kedokteran. Karya-karya dari Plato, Aristoteles, Hippokrates, Euklides, bahkan diburu ke berbagai wilayah, termasuk kerajaan saingan, untuk disalin dan dipelajari.
Perhatikan: yang dipelajari bukan hanya bidang-bidang yang kini lazim disebut “ilmu Islam” (yang isinya biasanya hanya fikih, sedikit sejarah Islam, ilmu tafsir dan hadis). Mereka juga tak alergi dengan pengetahuan dari orang “kafir”.
Apakah gairah terhadap ilmu-ilmu “asing” dan “mengganggu keimanan” seperti filsafat ini berjalan mulus tanpa tentangan? Jelas tidak.
Kontroversi selalu ada, bedanya, pemerintah saat itu, penguasa dinasti Abasiyyah saat itu, mendukung penuh perburuan intelektual ini dengan pelbagai kebijakannya.
Hal kedua yang ingin saya bagi: Pada masa Adelard, sebagian besar perkembangan intelektual mutakhir ditulis dalam Bahasa Arab (setelah sebelumnya masyarakat Islam berhasil menerjemahkan dan menyerap pengetahuan dan filsafat Yunani). Intelektual pada masa itu, mau tak mau harus menguasai bahasa Arab. Meski banyak intelektual dari Persia, Yunani, Turki, Kurdi dan tempat-tempat lain tetapi karya-karya intelektual hampir selalu ditulis dalam bahasa Arab.
“Para cendekiawan Barat Pertengahan yang ingin mengakses temuan-temuan terkini juga wajib menguasai bahasa Arab atau menggunakan karya-karya terjemahan dari mereka yang telah menguasai bahasa ini.” (Lyons, hal x)
Zaman telah berubah. Menurut saya, sekarang bahasa yang perlu dikuasai untuk mengakses temuan-temuan terkini adalah Bahasa Inggris.
Saat ini memang banyak penerbit yang memproduksi karya-karya terjemahan, tetapi tentu saja tak semua karya diterjemahkan. Apalagi karya-karya ilmiah sering kali adalah karya-karya yang tak laku dijual. Berkat internet, sebenarnya sangat mudah mencari artikel, buku, jurnal, video, apa pun yang menjadi minat kita, asal kita tahu cara dan bahasanya. Jadi, mari kita banyak belajar dan berani menembus batas.
Terus terang saya khawatir bahwa salah satu penyebab mengapa sebagian umat Islam Indonesia sangat gampang percaya pada teori konspirasi, begitu paranoid pada segala hal yang berbeda dari dirinya, adalah karena mereka tak punya cukup cara, tak punya banyak “kaca mata” dan sudut pandang lain untuk memahami keterpurukan umat Islam saat ini selain dengan menyalahkan pihak-pihak luar yang berbeda.
Saya sungguh berharap situasi ini bisa berubah. []
Rika Iffati Farihah adalah Penulis dan Penyunting Lepas.



