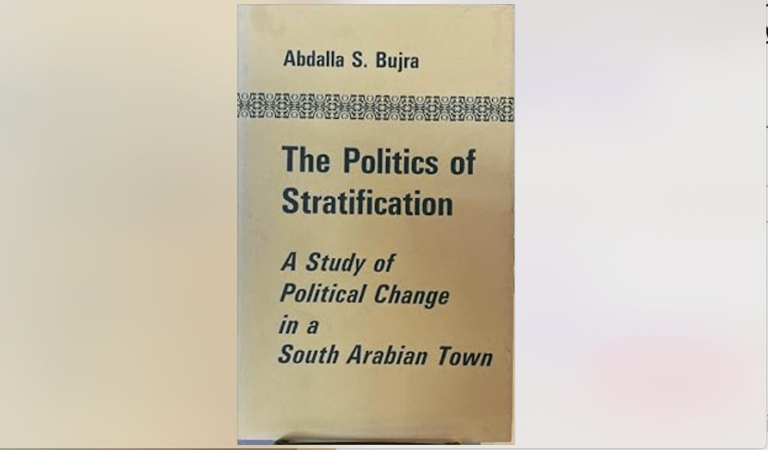
Saya penasaran kenapa gelar Sayyid begitu penting bagi orang Hadhrami di Nusantara pada periode kolonial. Saking pentingnya, mereka meminta pemerintah kolonial untuk melarang orang lain menggunakan gelar tersebut. Julukan Sayyid hanya boleh digunakan golongan tertentu, terutama bagi keturunan Rasulullah. Sementara itu, menurut lawannya, dari kubu al-Irsyad, istilah Sayyid tidak memiliki keistimewaan, siapa saja boleh gunakan, tidak ada bedanya dengan tuan, mister, atau sebutan penghormatan lainnya.
Buku yang ditulis Abdalla S. Bujra ini, The Politics of Stratification: A Study of Political Change in South Arabian Town, setidaknya menjawab rasa penasaran itu. Bujra melakukan studi antropologi tentang strata sosial di Huraidhah Yaman, serta bagaimana sistem strata itu beradabtasi dengan perubahan atau perkembangan ekonomi, politik, dan ideologi. Buku ini diterbitkan oleh Oxford tahun 1971.
Masyarakat Hadhrami, secara umum, terbagi dalam tiga kategoti: sadah, masyaikh dan qabila, dan masakin atau dhuafa. Sadah menempati strata sosial paling tinggi karena dianggap keturunan dari Nabi Muhammad SAW. Meskipun leluhurnya bukan orang Yaman asli, alias pendatang, modal darah Rasulullah itu membuat diri mereka secara sosial lebih tinggi dibanding pribumi sekalipun.
Sementara kelompok kedua: masyaikh dan qabilah, keduanya pribumi, leluhur mereka dihormati dan orang penting di Yaman. Khusus Masyaikh, selain representasi pribumi, mereka dihormati karena dianggap otoritatif dalam Islam. Sebelum kelompok Sadah migrasi ke Yaman, strata sosial masyaikh paling tinggi. Tapi karena tidak memiliki hubungan darah dengan Rasulullah, status sosial mereka menjadi kelas kedua setelah kedatangan para sayyid.
Berikutnya, masakin dan dhuafa dianggap sebagai strata paling bawah, mereka tidak punya klaim otoritas keagamaan, seperti sadah dan masyaikh, dan juga tidak punya senjata atau kekuatan semisal qabilah. Pekerjaan mereka rata-rata sebagai petani, pembantu, pengrajin, dan seterusnya. Mereka juga rentan menjadi objek jarahan ketika melintas di sebuah wilayah yang rawan dan minim perlindungan.
Sistem strata sosial seperti ini berlangsung cukup lama di Yaman. Sebagaimana dijelaskan Bujra, sistem ini dilanggengkan dengan membuat seleksi ketat dalam pernikahan. Maksudnya, masyarakat Yaman pada masa itu mentradisikan dan melarang perempuan dari strata tinggi untuk menikah dengan laki-laki yang strata sosialnya rendah. Kecil kemungkinan bagi laki-laki dari kaum masakin atau masyaikh misalnya bisa menikah dengan perempuan dari golongan sadah. Mengapa? Sebab kalau ada yang menikah dengan laki-laki yang status sosialnya rendah, otomatis level sosialnya juga akan turun. Begitu juga sebaliknya.
Karena itu, perubahan status sosial, dari level bawah menjadi atas, melalui pernikahan hampir mustahil terjadi. Apalagi sudah menjadi kebiasaan bagi kelompok yang status sosialnya tinggi untuk mempertahankan dan melarang anak perempuannya menikah dengan laki-laki yang tidak sama sratanya.
Perubahan strata sosial masih dimungkinkan terjadi melalui pengakuat kelompok yang dianggap stratanya paling tinggi. Ketika kaum sadah mengakui otoritas orang yang strata sosialnya berada di bawahnya, maka secara otomatis orang yang mendapat pengakuat itu level sosialnya juga naik. Misalnya, suku Basahl dari kalangan masyaikh, status sosial mereka semakin kuat dan terangkat karena pendapat pengakuan dari kaum Alattas (sadah). Peran leluhur mereka dalam menyebarkan agama diakui, apalagi dibuktikan dengan adanya makam leluhur.
Sebab itu, makam menjadi penanda penting untuk status sosial. Makam sekaligus menjadi salah satu cara untuk merawat ingatan masyarakat bahwa leluhur yang bersangkutan betul-betul orang yang berjasa besar dalam lingkungan mereka. Biasanya, sehabis shalat Idul Fitri masyarakat Huraidah ziarah ke makam leluhur Alatas, dan pada momen tertentu juga ziarah ke leluhur Bashal.
Beda halnya dengan Bakhamis, kelompok ini sebetulnya status sosialnya sama dengan Bashal (masyaikh). Leluhurnya (abdul rahim) berteman baik dengan leluhur alatas (umar). Bahkan leluhur Alatas mengajarkan kepada keturunannya untuk berkunjung ke rumah Abdul Rahim pada saat Idul Fitri.
Namun sayangnya, keturunan dari Bakhamis tidak membangun makam leluhurnya sebagai bentuk penghormatan terhadapnya, dan tidak melakukan aktivitas-aktivitas yang dapat merawat ingatan orang tentang jasa Abdul Rahim. Akibatnya, mereka tidak dikenal masyarakat sebagai orang yang ngerti agama, malahan status sosial mereka dianggap sama dengan Masakin, level sosial paling rendah di Huraidhah.
Perbedaan level sosial ini sangat terlihat berbeda dalam banyak hal, baik dalam pakaian, pekerjaan, dan kegiatan keagamaan. Misalnya, setelah shalat Idul Fitri, masing-masing kelompok berbaris dan antri untuk salaman dengan para sadah. Tapi sejak konflik Al Irsyad dan Sayyid di Batavia, sebagian anak2 muda udah mulai meninggalkan tradisi itu, setelah shalat langsung pulang, tidak salaman dulu.
Dalam konteks masyarakat yang seperti ini, para sayyid memiliki peran penting dalam konteks ekonomi dan politik Hadhramaut, khususnya Huraidah. Bujra menjelaskan, wilayah Huraidhah dibagi menjadi dua bagian: kota dan luar kota. Wilayah kota dihuni oleh kaum sadah, masyaikh, dan masakin. Sementara luar kota sebagian besar ditempati oleh qabilah-qabilah, atau suku tribal.
Wilayah kota secara umum dapat dikatakan aman, karena mereka berada dalam kuasa sultan yang dilengkapi petugas keamanan. Tapi kalau sudah keluar dari kota, tidak ada lagi jaminan keamanan. Apalagi kalau sudah masuk ke wilayah qabilah, penjarahan kerapkali terjadi. Petugas keamanan pada saat itu sangatlah terbatas. Mereka hanya mampu menjamin keamanan dalam kota.
Dalam konteks ini, peran Sayyid sangatlah vital. Mereka menjadi penjambatan komunikasi dengan para kabilah dalam hal membuat perjanjian keamanan, supaya lalu lintas pengiriman barang menjadi lancar dan tidak terganggu. Bersamaan dengan itu pula, mereka juga membuat kesepakatan untuk sama-sama menjaga tempat yang disucikan (hawthah), semisal makam-makam leluhur yang sering dikunjungi masyarkat.
Atas dasar perjanjian itu, wilayah yang berada di sekitar Hawthah juga menjadi aman. Transaksi ekonomi kerap terjadi di sini, sebab nyaris tidak ada gangguan dan penjarahan. Kalau ada kelompok atau individu yang melakukan perkelahian dan bentrok di wilayah ini, mereka akan diberikan sanksi.



