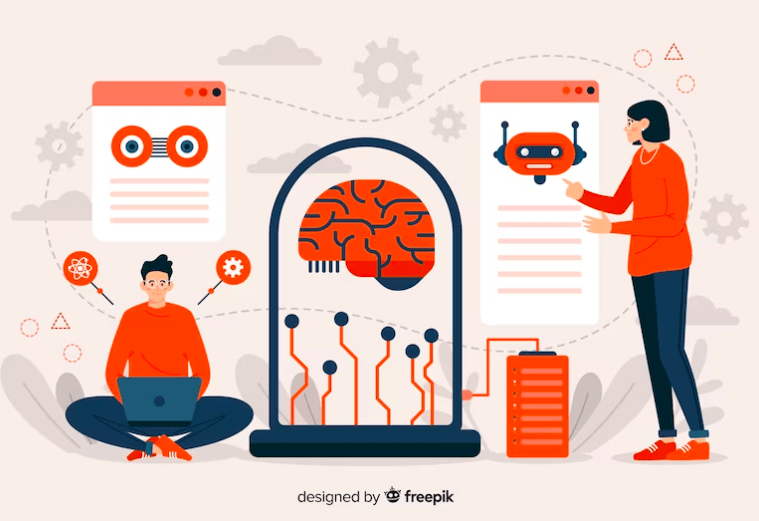
Di antara wacana yang belakangan ini muncul, terutama di jagat media sosial, adalah fenomena bahwa acapkali orang yang kemampuan akademiknya rendah atau tidak menonjol, alias biasa-biasa saja, tetapi sukses dalam kehidupannya. Paling tidak, sukses secara finansial dan karirnya. Ada juga banyak artikel yang menyatakan bahwa di antara kebiasaan yang dihindari oleh mereka yang berumur panjang atau mereka yang tidak cepat tua adalah stres dan dendam. Keduanya membuat daya tahan tubuh menjadi melemah dan sumber dari penyakit seperti darah tinggi dan lainnya.
Di sisi lain, salah satu fenomena yang kini menonjol di kalangan elite sosial politik dan ekonomi adalah sikap-sikap tak mau berbagi kekuasaan dengan membungkam kritisisme publik, tidak menegakkan prinsip meritokrasi dengan tidak mengakomodasi kelompok yang berbeda, kepada yang berprestasi sekalipun, dan tidak memberi ruang bagi kebebasan akademik dan mimbar. Semua itu terkait dengan kecerdasan emosional dan spiritual.
Kecerdasan Emosional dan Spiritual: Kesuksesan Tak Hanya Ditentukan Kecerdasan Intelegensia
Istilah kecerdasan emosional dimunculkan pertama kali oleh Daniel Goleman, sedangkan kecerdasan spiritual dimunculkan oleh Danah Zohar dan Ian Marshal. Dua kecerdasan ini pun mengubah cara pandang banyak orang, bahwa kesuksesan seseorang tidak hanya ditentukan kecerdasan intelegensia saja, tetapi dua kecerdasan itu. Kecerdasan emosional adalah kecerdasan mengelola emosi/perasaan, kecerdasan mengendalikan hati, baik di saat sukses maupun gagal.
Umumnya orang, di saat sukses sering tidak empati (yang dipentingkannya adalah untung dan selamat sendiri), juga bersikap sombong. Mereka tidak mengakui peran orang lain, orang tua dan Tuhannya sekalipun, baik disadari atau tidak. Mereka tak menghargai orang lain, bahkan menganggapnya tiada saja. Mereka tak mau berbagi kekuasaan dan ekonomi, dan melakukan penyelewengan kekuasaan. Sedangkan di saat gagal, malah sebaliknya, tidak punya lagi harapan, semangat dan ketekunan, dan tidak memandang kegagalan adalah proses belajar. Fokusnya adalah menyalahkan orang lain. Bahkan sebagiannya stres, dan puncaknya, bunuh diri pun menjadi pilihan.
Adapun kecerdasan spiritual adalah kecerdasan dalam menjalani hidup sebagai panggilan spiritual, di mana jiwanyalah yang memimpin badannya, bukan sebaliknya. Secara sederhana, kecerdasan spiritual adalah kecerdasan menjalani hidup dengan menjadi “anak-anak” Allah dalam arti spiritual, bukan fisik, yang dalam Islam dikenal dengan istilah menjadi “hamba-hamba”-Nya, bukan menjadi hamba selainnya seperti harta, tahta, dan cinta.
Maka, kadang mereka mendahulukan kebahagiaan spiritual ketimbang material, bahkan acapkali mengambil jalan terjal yang ideal/inovatif (menjadi seorang idealis), demi tuntutan spiritualnya yang kuat yang menguasai hatinya. Mereka pun bekerja di luar batas-batas formal (umumnya orang), jauh dari kata pragmatis, yang karenanya menjadi berprestasi dan punya karya-karya besar. Di saat tutup usia, mereka pun punya nama besar. Mereka berintegritas, di saat terancam secara ekonomi, bahkan nyawa sekalipun. Apalagi saat mereka mendapat cibiran/hinaan, mereka mengabaikannya.
Sekilas Dalam Islam
Dalam Islam, baik dalam bidang akidah maupun ibadah dan akhlak, di antara yang ditekankan, kalau bukan yang paling ditekankan, adalah kecerdasan emosional dan spiritual, selain intelektual. Alasannya basis kepercayaan/keyakinan, ibadah, dan akhlak/karakter adalah hati/kalbu, meski harus diperkuat akal.
Maka, menurut Imam al-Ghazali dalam Kîmîyâ as-Sa’âdah-nya (2013: 129-137), badan manusia bagaikan sebuah negara. Indra/anggota tubuhnya bagai perkampungan/provinsi kekuasaannya. Sementara nafsu (kecenderungan material, termasuk di dalamnya seks) adalah gubernurnya, dan nafsu agresif/superioritas (kecenderungan mengalahkan orang lain) adalah polisi/tentaranya. Hati nurani adalah raja (kepala negara)-nya, sementara akal adalah perdana menterinya. Posisi hati yang menjadi basis ilmu intuitif/wahyu dalam tubuh manusia lebih tinggi ketimbang akal yang menjadi basis ilmu rasional. Apalagi dengan indra yang menjadi basis ilmu empiris.
Raja, tegas al-Ghazali, memerlukan berdialog dengan akal, sementara akal berdialog dengan para gubernur dan tentaranya. Hati yang membimbing badan/indra untuk menjadi seorang yang saleh, taat beragama dan berintegritas (berakhlak baik) yang akan membawa manusia pada kebahagiaan batin. Di antara yang dirujuknya adalah QS. al-A’raf/7: 172 dan ar-Rum/30: 30, bahwa hati nurani yang menuntun manusia pada spiritualitas (berketuhanan, termasuk di dalamnya kecerdasan spiritual/emosional) adalah bawaan asli/fitrah manusia. Tanpa hati manusia akan merana. Juga ayat yang menyebut bahwa yang akan selamat di dunia dan akhirat adalah mereka yang hatinya selamat/lurus (QS. as-Syu’ara/26: 87-89) dan itu berarti memiliki kecerdasan spiritual.
Dalam Islam pun, kepercayaan yang harus dibangun seorang Muslim adalah tauhid rububiyyah dan ‘ubudiyyah, selain tauhid uluhiyyah, dan maqshudiyyah. Tauhid uluhiyyah adalah meyakini Tuhan itu hanya Allah semata. Segala sesuatu selain Allah adalah bukan Tuhan yang tak berarti, sebagaimana tampak dalam kredo (lâ ilâha illallâh). Sementara tauhid maqshudiyyah, sebagai konsekuensi dari tauhid uluhiyyah, adalah keyakinan dan sikap dengan menjadikan Allah sebagai sumber motivasi/tujuan, bukan pamrih kepada selain-Nya yang disebut sebagai syirik khafî (kemusyrikan yang samar). Ini berarti bersikap ikhlas, bagian dari kecerdasan emosi dan spiritual yang penting. Analogi dari sikap ini adalah air, maka hiduplah seperti air, yang dibutuhkan manusia, tetapi setelah digunakan, ia dicampakkan mereka begitu saja. Karenanya, dalam beramal, tak memasalahkan tiadanya pengakuan manusia, karena yang dipentingkan adalah pengakuan Allah dan catatan amal baik dari malaikat, seberapa pun motif pengakuan manusia bagian dari kebutuhan psikologis manusia dan andai didapat pun, itu dipnadang bukan tujuan utama.
Tauhid ‘ubûdiyyah, sebagai konsekuensi juga dari tauhid ulûhiyyah, adalah keyakinan dan sikap yang hanya menyembah (beribadah ritual-sosial) kepada Allah semata, tidak menjadi hamba selain-Nya (lihat QS. al-Fatihah/1: 5). Selain-Nya hanyalah makhluk/hamba Allah semata. Karenanya, manusia dalam perspektif ini tak boleh menjadi hamba selain Allah yang sebab itu, mereka akan mau melakukan apa pun, demi Allah, kendati dalam Islam, semua perintah Allah mesti manusiawi, rasional, dan membawa kebaikan pada mereka. Bukan saja tauhid ini membawa manusia menjadi idealis, berintegritas, dan banyak berkarya monumental sebagaimana telah diuraikan di atas, melainkan juga ada sisi keyakinan dan berprasangka baik, sebagai salah satu dari kecerdasan emosi.
Dalam tauhid ini juga terdapat keharusan sikap bersyukur, berterima kasih atas nikmat yang Allah berikan. Bukan saja menerima dan menyenangi nikmat yang diberikan-Nya di dalam hati, bukan kufur (sikap mengingkari) nikmat, melainkan juga bersyukur dalam tindakan dengan melakukan ibadah. Dalam Islam, minimal dengan melakukan salat dan puasa. Juga bagi orang yang kaya bersyukur juga dengan berzakat kepada sesamanya (kepada kaum miskin yang telah bekerjasama, baik yang bekerja untuk mereka maupun yang mengkonsumsi produknya).
Sementara tauhid rubûbiyyah sebagai konsekuensi juga dari tauhid ulûhiyyah, adalah sikap dan keyakinan bahwa yang mengurus alam semesta dan memeliharanya adalah Allah, termasuk manusia sebagai puncak ciptaan-Nya, sebagaimana yang ditekankan QS. al-Fatihah/1: 2 dan ayat kursi, QS. al-Baqarah/2: 255.
Manusia tidak boleh melakukan syirik kehendak, dengan memandang bahwa keinginan atau cita-citanya sebagai yang terbaik, karena yang terbaik adalah kehendak dan kuasa Allah. Dalam Islam pun manusia harus meyakini adanya takdir dan bersikap sabar atas semua takdir Allah, baik yang takdir baik/enak dalam pandangan manusia maupun yang buruk (sebagai musibah).
Di sinilah paling tidak ada dua kecerdasan emosi yang ditekankan, yaitu hidup sabar atas segala ujian, karena Allah akan bersama orang-orang yang sabar dalam menghadapi ujian hidup seperti dalam menghadapi musibah kematian dan kemiskinan (QS al-Baqarah/2: 155-156). Bahkan, sabar dalam hadis sebagai bagian dari cara Allah menghapus dosa hamba-Nya dan cara Allah memberinya pahala surga.
Juga di dalamnya terdapat anjuran memiliki kecerdasan emosi dengan berbaik sangka atas takdir Allah, karena Allah Mahatahu dan Mahakuasa sebagaimana terdapat dalam banyak ayat al-Qur’an. Tentu saja, dengan tetap harus melakukan usaha yang maksimal, karena takdir berada di ujung usaha. Di sini pula terdapat kecerdasan emosi dengan tekun berusaha, sebagaimana yang ditekankan banyak ayat dalam al-Qur’an dan juga hadis.
Sebagaimana dalam akidah, dalam ibadah juga terdapat tujuan menanamkan kecerdasan emosi dan spiritual. Tujuan puasa adalah agar orang-orang yang beriman bersyukur, selain bertakwa (berintegritas [QS. 2: 184]) dan mampu membesarkan Allah (mengecilkan di luar Allah). Salat juga agar manusia antara lain mampu membesarkan Allah dan berbagi kepada manusia di sekelilingnya, baik yang ada di kanan maupun di kirinya. Wallâhu a’lam. []



