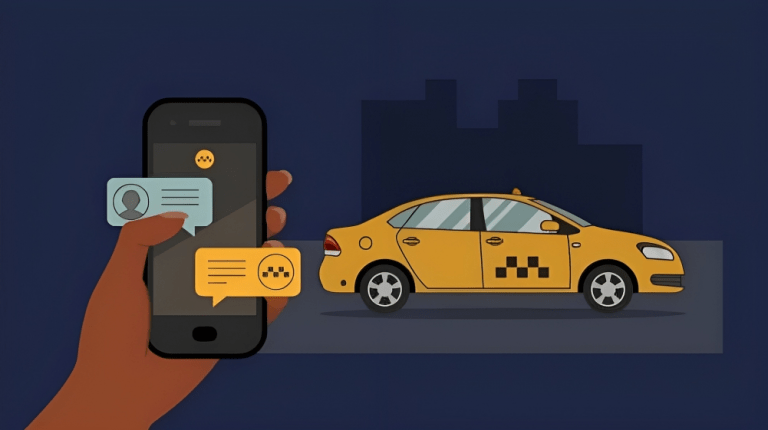
Seorang kawan membagikan pengalamannya menaiki taksi online di kota perantauan. Sebuah cerita yang menyadarkannya, bahwa kota rantau (baca: Depok) menyimpan sebuah realita yang tak pernah ia temui sebelumnya.
Sebuah pesan singkat dari seorang kawan masuk di WA, Minggu (1/10/2023). “Sida ngopi neng ndi, bro?”. Kami memang berencana ngopi hari itu. Untungnya si kawan ini mengingatkan. Saya membalas pesannya. Bukan hanya membalas, saya juga mengirim titik lokasi tempat ngopi kita nanti. Sebuah café yang cukup cozy, di bilangan Jl. Raya Margonda, Depok.
Agenda ngopi ini memang sudah menjadi rutinan mingguan kami. Bukan hanya berdua, kami berkumpul dengan kawan-kawan lain senasib sepenanggungan. Sesama perantau yang kebetulan diikat dalam satu almamater yang sama, di sebuah kampus negeri di pelosok Kabupaten Sleman, Yogyakarta.
Ngopi kali ini berbeda. Kawan saya ini datang membawa kisah pengalaman pertamanya di tanah orang, yaitu obrolan dengan supir taksi online. Seorang ibu-ibu paruh baya yang mengantarkannya ke asrama. Pikir saya, apa istimewanya? Namun, saya langsung tertarik ketika dia tiba-tiba misuh. Perilaku yang tidak pernah saya liat selama saya berteman dengan dia dua tahun di Jogja. Saya menyimpulkan. Pasti berkesan sekali ceritanya.
Supir Taksi Online yang Membuka Mata Seorang Perantau
Kawan saya satu ini, sebut saja namanya Amat (26), baru saja diterima sebagai mahasiswa S3 di salah satu kampus bergengsi di Indonesia. Kebetulan kampusnya ada di Depok. Ketika tahu dia diterima, saya sontak me-rename kontaknya dengan tambahan ‘Ph.D Cand.’.
“Ris, tak ceritani. Aku wingi numpak taksi online driver e ibu-ibu!”
“Ha njuk ngopo, mat?” Saya tak sabar menunggu punchline-nya.
Sembari menyeruput es coffee latte with brown sugar, ia menjelaskan bahwa selama di dalam taksi online, si ibu yang notabene supirnya, menceritakan salah satu keluh kesahnya selama menjadi supir taksi online. Ia pernah mendapatkan klien seorang ibu bercadar. Katanya, ibu itu hendak berangkat ke sebuah kajian kegamaan di sebuah titik di Depok.
Di tengah perjalanan, si ibu bercadar itu beberapa kali menasehati si ibu driver. Ia bahkan menuding si ibu driver telah menyalahi kodratnya sebagai perempuan karena bekerja, alih-alih mengurus rumah tangga, dan keluar tanpa didampingi mahrom. Makin lama, si ibu bercadar tampak lebih terlihat menghakimi alih-alih menasehati.
“Ibu-ibu itu ris bilang ke driver, ngapain sih ibu jadi supir taksi online. Keluar sendirian ngga ada mahrom. Ibu sama aja zina loh nanti!” Amat bercerita dengan intonasi yang tak wajar. Saya cukup yakin dia sedang berusaha meniru gaya bicara ibu yang ‘agamis’ itu.
Ibu penumpang itu sukses membuat kawan saya itu emosi. Kenapa bisa ibu driver yang sudah mengantarkannya ke kajian justru dibayar dengan penghakiman yang mungkin mengacaukan mental si ibu driver. Sebuah perasaan yang sebenarnya tidak sebanding dengan cuan yang dibawa pulang.
Disambut dengan Realita Keagamaan yang Miris
Tidak hanya sampai situ, ibu bercadar itu lantas memberikan saran untuk si ibu driver untuk tinggal saja di rumah. Ia harusnya mengabdi pada suami, mendoakan anak-anaknya, dan jangan melibatkan diri dalam zona-zona rawan maksiat. Seperti jadi supir taksi online mungkin maksud si ibu-ibu kajian.
Sesekali Amat misuh. Sesekali Amat mengutuk. Katanya, si ibu driver itu sampai menangis sesenggukan mendengarkan ‘penghakiman barbar’ yang dialamatkan padanya. Si ibu driver tak bisa membantah. Secara relasi kuasa ia kalah. Si ibu hanyalah supir yang tugasnya melayani klien sampai ke tujuan.
Mendebat si ibu bercadar hanya akan memperpanjang masalah dan berakhir dengan ‘bintang satu’ di aplikasi ojek online-nya. Konsekuensi yang secara konkret justru lebih mengerikan baginya.
“Terus kamu bilang apa sama si ibu driver itu, mat?” tanya saya.
Amat menjawab kalau dia berusaha memberi alternatif respon kepada si ibu driver. “Ibu bilang aja sama dia, kenapa anda juga keluar tanpa mahrom? Dan kenapa anda masih lanjut di mobil saya kalau tidak sepakat dengan status kerjaan saya?” ujar Amat masih dengan intonasi yang tak wajar.
Amat juga mengatakan pada si ibu driver, harusnya ibu juga bilang, “Bagaimana jika anda mendapatkan driver laki-laki? Apakah itu justru lebih jelas hukumnya, berduaan di satu ruangan dengan yang bukan mahrom?”
Tapi saya yakin, si ibu driver tidak mempunyai kapasitas keilmuan fiqih sedalam itu. Jangankan kepikiran dalil fiqihnya, niat untuk mendebat saja mungkin sudah sirna. Sekali lagi, ia hanya supir taksi online yang berjuang agar keluarganya kenyang, dan kebetulan sedang berhadapan dengan seorang ibu-ibu agamis yang ‘kekenyangan’ dalil.
Tapi ya sudahlah. Amat kadung bercerita dengan level emosi yang keliatannya sudah berada di titik nadir. Ia hanya tak menyangka, ibu-ibu dengan atribut keagamaan semegah itu justru sangat fasih menghakimi sesamanya. Saya juga sangat yakin, ibu-ibu agamis itu tidak memahami apa latar belakang kenapa si ibu driver sampai mengambil jalur jalanan sebagai lahan mencari penghidupan.
Di sela keheningan, saya memotong dengan pertanyaan yang out of the box.
“Itu kok bisa muncul obrolan begitu, kontesknya apa mat?” tanya saya heran. Kok bisa baru kenal tapi si ibu sudah pede berkeluhkesah.
Ia kembali menyeruput es coffee latte with brown sugar. Setelah berdehem, ia menjelaskan bahwa si ibu driver adalah orang Semarang dan si Amat adalah orang Sragen. Menyadari kesamaan identitas sebagai warga Jateng, bahasa obrolan yang semula ‘saya-anda’ berubah menjadi ‘kulo-panjenengan’. Memang, kesamaan identitas sangat berkorelasi pada level kenyamanan komunikasi sehingga bisa membongkar sekat-sekat yang tabu.
Jangan-jangan Ada Banyak Penghakiman Serupa di Tempat Lain
“Kira-kira di tempat lain ada yang seperti itu ngga ya, mat?” Saya memancing Amat.
“Mbuh, ris.” Ia tampak kehabisan energi menjawabnya.
Masih di bulan yang sama, King’s College London mengeluarkan sebuah survei yang salah satu respondennya adalah Indonesia. Survei ini mengungkap nilai-nilai apa yang menjadi prioritas untuk anak di keluarga. Para responden yang notabene adalah para orang tua di Indonesia lantas ditanya hal-hal apa saja yang paling penting diajarkan ke anak-anak di rumah.
Hasilnya, mereka ternyata sangat peduli dalam hal kepercayaan agama. Sebanyak 75% responden dari Indonesia menyatakan bahwa agama penting diajarkan untuk anak-anak. Namun survei mengungkap, kesadaran akan pentingnya pendidikan agama pada anak tidak berbanding lurus dengan kesadaran akan pentingnya edukasi toleransi.
Survei menunjukkan bahwa orang tua Indonesia mengesampingkan dua nilai penting, yaitu toleransi dan sikap tidak egois. Jika memang survei itu benar adanya, si ibu bercadar itu mungkin salah satu orang tua yang tanggap agama, namun darurat kemanusiaan.
Dan tampaknya, masih banyak orang dengan atribut keagamaan yang mewah namun miskin rasa empati dan menghargai. Saya jujur gregetan. Namun, Amat tampak lebih emosional.
Saya menyenggol Amat sembari berkata bahwa mungkin kejadian serupa sangat bisa terjadi di tempat lain. Hanya saja tidak terangkat ke ruang publik. Sebelum pulang, saya titip pesan ke Amat, kebetulan dia ini pernah nyantri dan sedang mengambil Doktoral di bidang Pendidikan di kampus barunya. Saya pesen ke dia untuk mengedukasi moral orang-orang agar beragama dengan sehat dan mendamaikan.
“Siap, ris. Yo bareng-bareng to mosok aku dewean.” katanya tertawa. Intonasinya berubah normal.
Sesaat sebelum memasuki parkiran, ia menyeloroh,“Kunci motorku ndi yo, ris?” ujarnya dengan mimik serius.
“Weeelaah.” Batinku.



