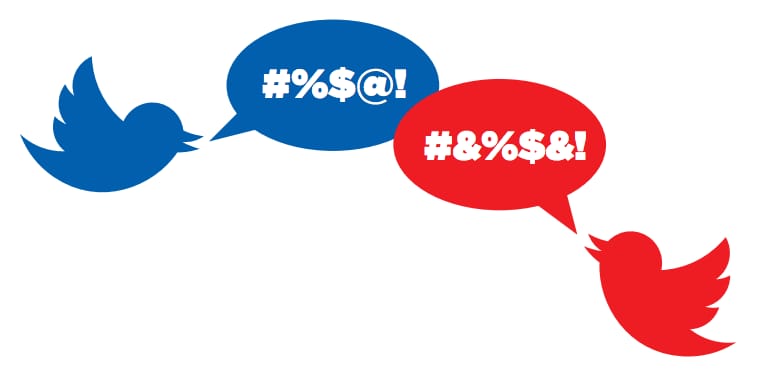
Judul bagian ini memang saya takik dari ucapan Pramoedya Ananta Toer yang sangat terkenal, dengan sedikit gubahan: “Berbuat adil sejak dalam pikiran.” Mengapa bersikap adil kepada dalil-dalil naqli (al-Qur’an dan hadis) sangat penting–pada konteks ini—sejak dalam hati (bukan hanya sejak dalam pikiran)?
Begini.
Dalam ilmu Ushul Fiqh–metodologi yang melahirkan khazanah fiqh—memang dikenal istilah talfiq, yakni mengambil sebagian pendapat ulama A (tentu meninggalkan sebagian pendapat lainnya), mengambil sebagian pendapat ulama B (tentu meninggalkan sebagian pendapat lainnya), dan seterusnya, lalu menjadikannya sebuah pedoman fiqh. Secara prinsipil, mekanisme talfiq ini hanya boleh dilakukan kaum alim ‘allamah –sesama ahli Ushul Fiqh dan Fiqh—dengan keyakinan bahwa mereka sadar dan tahu betul muru’ah talfiq yang dijalankannya. Ia tak boleh dilakukan oleh kaum awam, karena dikhawatirkan hanya akan menjadikannya tebang pilih terhadap khazanah pendapat ulama-ulama fiqh sesuka hati dan pikirnya untuk mentashih hawa nafsu.
Misal, ya.
Dalam kitab Bidayatul Mujtahid karya Ibnu Rusyd, disebutkan bahwa adanya wali bagi perempuan adalah bagian dari rukun nikah dalam pendapat Imam Malik, Imam Syafii, dan Imam Ahmad. Kita tahu bahwa maqashid dari rukun wali ini untuk menjamin si perempuan bisa mendapatkan suami yang baik dengan perlindungan walinya yang dewasa. Jadi, wali berperan besar terhadap ikhtiar mendapatkan kualitas pasangan bagi anaknya demi kecerahan masadepan rumah tangganya. Serta, tentu, untuk menghindarkan fitnah sosial di kemudian hari jika sampai sang wali tidak menyetujui, apalagi tak mengetahui pernikahan anaknya.
Tetapi dalam pandangan Abu Hanifah yang hidup di Kufah dengan lingkungan kaum pekerja perkebunan yang melibatkan banyak orang dengan latar yang majemuk –hingga negeri-negeri jauh—khusus bagi perempuan yang telah dewasa (secara pemikiran dan emosional) dibolehkan menikah tanpa wali. Maqashid wali tadi dianalogikan terwakili dalam kualitas pemikiran dan emosional si perempuan dewasa sehingga ia bisa memilih dengan baik calon pasangannya demi kemaslahatan rumah tangganya kelak.
Ikhtilaf adalah hal biasa dan jamak dalam khazanah fiqh kita sejak dahulu kala. Jadi, tak usah diperdebatkan dengan ontran-ontran berlebihan yang rawan memicu perpecahan dan permusuhan yang terlarang.
Bagi seorang alim ‘allamah, ia niscaya bisa memahami dengan jernih alasan-alasan logis yang membuka kemungkinan bagi pencapaian masalahat di balik suatu fatwa fiqh. Namun, tentulah hal demikian musykil dijangkau para awam. Titik kemusykilan inilah yang menjadikan pintu talfiq tertutup buat mereka dengan menimbang risiko madaharat-madharatnya.
Dengan perspektif begitu, talfiq lalu bisa diterima sebagai “jalan ijtihad” yang juga mengandung tujuan-tujuan kemaslahatan. Perbincangan tentang talfiq ini saya maksudkan semata untuk memperlihatkan betapa terbukanya khazanah fiqh untuk berdinamika sepanjang zaman; bukan untuk merangsang Anda berperilaku suka-suka dalam berfiqh dan bertaklid. Tidak begitu…
Bila kepada khazanah fiqh saja kita mesti senantiasa berperilaku adil –dengan niat semata menggapai kemaslahatan dan kemaslahatan yang lebih besar lagi—(bayangkan!) apalagi kepada khazanah dalil-dalil naqli. Sudah pasti, ia berderajat lebih kokoh dan tinggi. Kehati-hatian, kerendahan hati, dan ketulusan mestilah senantiasa dikedepankan di dalam hati, juga pikiran.
Sikap adil sejak dalam hati (kemudian pikiran) kepada dalil-dalil naqli ini bisa saya contohkan pada peta ayat-ayat muhkamat (terang makna dan maksud hukumnya) dan mutasyabhihat (samar makna dan maksud hukumnya).
Tidak ada ulama Ushul Fiqh yang tak memahami dan mengkaji peta penting ini. Di dalam al-Qur’an, keterangan perihal peta ini bisa ditemukan dalam surat Ali Imran ayat 7 beserta banyak kitab tafsirnya.
Pada suatu malam, di tweeter, saya menemukan thread seorang perempuan yang menyatakan telah belajar bertahun-tahun ilmu agama (mungkin maksudnya metodologi tafsir dan Ushul Fiqh) –bahkan menyebut murid Kyai Abdul Moqsith Ghazali, salah satu cendekiawan muslim kontemporer yang saya hormati. Meski begitu, ada cuitannya yang mengusik hati saya, yakni pernyataanya bahwa ia melepas jilbab (artinya selama ini ia berjilbab) dengan penuh kesadaran karena meyakini secara keilmuannya bahwa berjilbab tidak wajib berdasar pada “ayat tentang jilbab (maksudnya surat an-Nur 30-31) adalah mutasyabihat.”
Saya njenggirat! Sikto, sikto, sebentar.
Saya tak memberikan respons apa-apa di thread-nya–sungguh saya malas berdiskusi, apalagi berdebat di sosmed. Saya akan berikan pandangan di sini saja.
Pertama, para ulama Ushul Fiqh paham betul tentang peta ayat muhkamat dan mutasyabihat ini. Dari kitab ringan ‘Ilm Ushul Fiqh karya Abdul Wahab Khallaf yang amat kondang hingga kitab besar Al-Itqan fi ‘Ulumil Qur’an karya Imam Jalaluddin al-Suyuthi, kajian tentang tema itu tersedia.
Kedua, se-mutasyabihat apa pun ayat al-Qur’an, bagi mukmin, takkan meragukan, apalagi menampik, bahwa ayat-ayat tersebut juga berasal dari Allah Swt, bagian dari KalamuLlah, sehingga status dan muatannya pastilah juga suci dan benar mutlak. Ini perkara rohani yang sangat prinsipil bagi sang mukmin.
Ketiga, sebab itu, seluruh ayat al-Qur’an mesti selalu bisa diterima dengan tunduk dan ta’dhim sepenuh-penuhnya, mau itu muhkamat dan mutassyabihat –ataupun para ulama sedang berbeda pendapat tentang peta lingkupnya. Sikap tunduknya hati ini –cerminan dari iman, tentu saja—secara umum semata menisbatkan pemahaman pokok bahwa (1) semua ayat al-Qur’an adalah muhkamat; (2) tidaklah mungkin ada satu ayat pun yang meaningless, tanpa maksud dan arah yang jelas (qath’i, muhkamat), walaupun pada sebagian ayat hanya Allah Swt lah yang mengetahui maksudnya (3) sehingga semua ayat al-Qur’an pastilah mengandung perintah, ajaran, pesan, makna, maksud, atau arah yang dikehendakiNya –diajarkan Islam, dan (4) di dalam mutasyabihat pun ada ke-muhkamat-an –baik saat berdiri sendiri secara maudhi’i (atomik, satuan) maupun secara tematik (maudhu’i-ijmali). Tidak ada satu ayat pun, se-mutasyabihat apa pun, yang tidak mengandung ketetapan ajaran dan hukumNya.
Keempat, jika seseorang memegang selalu spirit rohani dan pemahaman keilmuan ini, niscaya ia takkan pernah mengangkat dirinya ke tahta merasa lebih tahu, lebih otoritatif, lebih benar, lebih relavan di hadapan ayat-ayat mutasyabihat. Ia akan selalu tunduk, ta’dhim, terlebih dahulu kepada kebenaran dalil-dalil naqli itu secara keseluruhan; bersikap adil di hadapan semua kandungan dalil, mau yang terang makna dan maksudnya (muhkamat) ataupun yang samar makna dan maksudnya (mutasyabihat) –bahkan yang paling tak bisa dipahami, misal arti Alif-Lam-Mim atau hal-hal metafisik macam kiamat dan akhirat.
Kelima, efek bersikap adil begini sungguhlah besar sekali. Bahwa ia lantas menjalankan suatu metodologi ilmu dalam menggali dan memahami pesan-pesan dalam ayat-ayat mutasyabihat, ia niscaya akan sangat mengedepankan kehati-hatian, wira’i, tawadhu’, dan kebijaksanaan, sehingga darinya takkan lahir penyimpulan-penyimpulan hukum yang ceroboh, vulgar, kontroversial, memperturutkan hawa nafsu.
Apa yang kita nyalakan dalam hati dan pikiran di hadapan dalil-dalil naqli pada akhirnya akan menghantar kita kepada dua golongan ini saja –yang diabadikan dalam Ali Imran ayat 7:
Pertama, golongan ahli ilmu yang cenderung kepada kesesatan (atau hatinya berpenyakit) dan memproduksi/mengikuti takwil-takwil yang memicu fitnah. Ayat tersebut menyebutnya “fi qulubihim zaighun”. Fitnah dimaksud bisa berupa menjadi makin sumirnya makna ayat, menghadirkan kebimbangan, keraguan, manipulasi, silang-sengkarut, kegaduhan, dan pertikaian. Ini terjadi bisa karena keawaman semata namun kewanen atau memiliki ilmu tetapi dibajak hawa nafsu.
Prof. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Munir mengatakan adanya empat jenis bagi golongan ini: pertama, golongan yang bersengaja menciptakan kerancuan-kerancuan terhadap takwil-takwil al-Qur’an seperti dilakukan kelompok Zanadiqah dan Qaramithah akibat hati yang menolak kebenaran dan otoritas al-Qur’an, kedua, golongan yang menyangka ayat-ayat mutasyabihat hanya sesuai makna zahirnya, hingga (misal) ayat seperti wajhuLlah (Wajah Allah Swt) diartikannya sebagai “Allah Swt memiliki wajah sebagaimana makhlukNya” ala kaum Mutajassim, ketiga, golongan yang berusaha dengan sungguh-sungguh (arti kata yattabi’una) menakwil dan mengikuti penyimpulan maksud ayat menurut dirinya sendiri tanpa merujukkan kepada ayat-ayat muhkamat (dengan sok tahu betul, memutlakkan), dan keempat, golongan yang bersikap terlalu banyak mengemukakan pertanyaan-pertanyaan tentang hakikat makna yang terkandung dalam ayat-ayat mutasyabihat –yang tentulah bersumber pada besarnya keragu-raguan dalam hati.
Prof. Quraish Shihab dalam tafsir Al-Mishbah memberikan contoh terkait dari sikap sejumlah kaum Nasrani Najran yang mengatakan bahwa Nabi Isa As adalah anak Allah Swt dengan merujuk pada al-Qur’an surat An-Nisa’ ayat 171: “Kalimat Allah Swt dan Ruh dariNya.” dengan tanpa merujuk kepada ayat muhkamat seperti yang dikandung surat al-Ikhlas: “(Allah Swt) tidak beranak dan tidak diperanakkan.”, surat Az-Zukhruf 59: “Dia (Isa As) tiada lain adalah seorang hamba yang Kami berikan nikmat (kenabian) dan Kami jadikan dia contoh bagi bani Israil.” dan surat Ali Imran ayat 59: “Sesungguhnya perumpamaan (penciptaan) Isa As bagi Allah Swt adalah seperti (penciptaan) Adam. Dia Swt menciptakannya dari tanah, kemudian Dia Swt berkata padanya “Jdilah!” maka jadilah sesuatu itu.”
Kedua, golongan ahli ilmu yang dijuluki “ar-rasikhun fil ‘ilmi”. Merekalah yang dimaksud surat Fathir ayat 28: “Yang takut hatinya kepada Allah Swt adalah orang-orang yang berpengetahuan (ulama).”
Menurut Prof. Quraish Shihab–senada dengan keterangan Prof. Wahbah Zuhaili—kata “ar-rasikhun” berasal dari kata “rasakha”, yakni sebuah benda berat yang jatuh dari ketinggian hingga menancap ke tanah dengan sangat kuat, kokoh, tidak goyah lagi sedikit pun. “Ar-rasikhun fil ‘ilmi” mengandung makna sebagai golongan mukmin yang ahli ilmu, yang berkat kedalaman dan keluasan ilmunya menghantarnya kepada makin kokohnya iman kepada Allah Swt.
Mereka di ujung ayat Ali Imran 7 itu dijuluki “ulul albab”, yakni pemilik “saripati” (ilmu) yang tak lagi terhalangi oleh kulit-kulit atau selubung-selubung apa pun, entah kesombongan, hawa nafsu, dan tendensi harta duniawi.
Dikarenakan hati golongan ini senantiasa takut kepada Allah Swt, tunduk penuh kepadaNya, hal pertama kali yang mereka ikrarkan kepada semua ayat al-Qur’an, termasuk ayat-ayat mutasyabihat, adalah “kami beriman kepadanya (termasuk mutasyabihat); semuanya (muhkamat dan mutasyabihat) datang dari sisi Tuhan kami.”, lalu melanjutkan dengan dua doa utama: “Ya Tuhan kami, janganlah Engkau gelincirkan hati kami setelah Engkau karuniakan petunjuk kepada kami dan anugerahkanlah kepada kami rahmat dari sisiMu” dan “Ya Tuhan kami, sesungguhnya Engkau mengumpulkan manusia untuk (menerima pembalasan pada) hari yang tiada keraguan padanya.”
Tentu kita bisa membayangkan, semata kecemerlangan rohani level luhunglah yang mungkin menyumberkan sikap iman, tunduk, ta’dhim, dan takut yang begitu hebatnya kepada Allah Swt serta seluruh ayat-ayatNya tanpa kecuali.
Prof. Quraish Shihab menambahkan bahwa kaum ar-rasikhun atau ulul albab ini memiliki empat ciri pada dirinya: pertama, takwa yang mendalam kepada Allah Swt, kedua, rendah hati kepada sesama, ketiga, zuhud (terpelihara dari deraan ambisi hawa nafsu duniawi), dan keempat, ahli mujahadah/riyadhah sebagai jalan (lelaku) kesungguhan olah jiwa untuk menundukkan hawa nafsunya.
Sangat wajar bila dari golongan luhung begini mustahillah menyeruak sikap tebang pilih kepada ayat-ayatNya ataupun takwil-takwil tak wajar dan melampaui batas yang beraroma memperturutkan hawa nafsu, ambisi, tendensi syahwat-politis-ekonomis duniawi, hingga melesakkan fitnah-fitnah yang membuat gaduh dan kacau. Mustahil!
Saya ingin menambahkan satu poin di penghujung bahasan ini: ayat-ayat muhkamat dalam surat Ali Imran ayat 7 itu disebut “ummul kitab”. Kata “umm” berarti ibu (induk), yakni sosok/tempat yang kepadanyalah anak-anak kembali/pulang/merujuk. Ketika ayat-ayat muhkamat dinyatakan olehNya sebagai “ibu, induk”, itu mengandung makna bahwa ayat-ayat muhkamat hendaklah selalu dijadikan jantung rujukan oleh semua ayat mutasyabihat beserta seluruh takwil dan tafsirnya –apa pun, bagaimanapun, kapan pun, oleh siapa pun—agar semua keterangannya memiliki landasan kepastian makna, pesan, ajaran, dan hukum. Ijinkan di titik ini kembali saya refresh bahwa (jangan sampai lupa) di dalam ayat-ayat mutasyabihat pun ada ke-muhkamat-an; di dalam ke-dzanniy-an ayat-ayat mutasyabihat pun mengandung sifat qath’iyyah dalalah; dan karenanya seluruh ayat al-Qur’an adalah muhkamat, qath’iyyah, tanpa kecuali. Ya, tanpa kecuali!
Mari bersikap adillah sejak dalam hati, lalu diikuti pikiran, kepada semua dalil naqli tanpa tebang pilih. Jikapun ada ayat-ayat dan hadis-hadis yang belum bisa kita pahami secara rasional dan mantap, cukuplah cahaya iman di hati menjadi penolong kita untuk tetap bersikap ta’dhim dan ittiba’. Sungguh, ilmu kita semua, mau kita sebut sangat luas dan dalam, hanyalah sedikit di hadapan maha samudranya ilmu Allah Swt (coba cermati surat Al-Kahfi 109). Bekal yang sedikit, cum nisbi, di hadapanNya yang Luas dan Agung, cum Abadi, bagaimana mungkin membuat kita berani lancang dan ceroboh?
Semoga kita dibimbingNya selalu. Amin.
Wallahu a’lam bish shawab.



