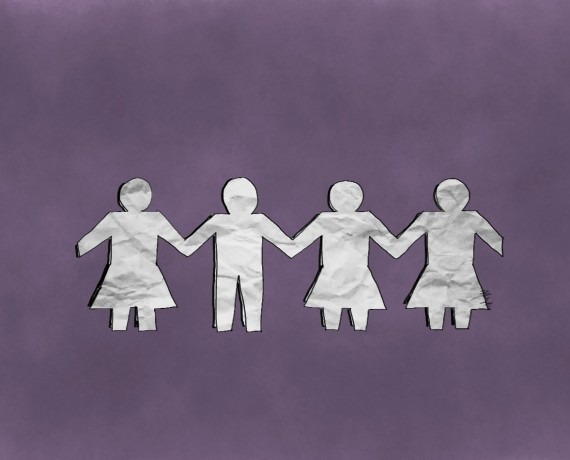
Sebuah media online yang mempromosikan kesetaraan dan perlakuan adil utamanya pada kelompok minoritas baru-baru ini memposting ulang sebuah artikel yang memuat kritik terhadap praktik poligami. Tulisan tersebut diawali dengan kisah nyata bagaimana seorang istri yang menolak poligami, yang kemudian justru malah disalahkan atas kekacaubalauan rumah tangganya.
Prahara rumah tangga tersebut menggambarkan bahwa mengiyakan dan menolak poligami selalu dilematis bagi para istri. Secara umum, saya mengapresiasi bagaimana penulis memperlihatkan dilema seorang perempuan dalam jebakan patriarki yang acap kali diibaratkan seperti memakan buah simalakama, atau berada di posisi serba salah.
Namun dalam narasi pembuka, dengan mengatakan bahwa “kita ingin mengadopsi gaya negara Arab yang kaya dalam hal poligami, sementara kondisi kantong kita sendiri adalah negara berkembang” (sebelumnya tertulis: kantong kita lebih dekat pada masyarakat Afrika pada umumnya), justru membuat pesan inti tentang kritik praktik poligami menjadi buyar. Khawatirnya, orang akan menafsirkan bahwa cukup menjadi lelaki kaya untuk dapat berpoligami. Terlebih, di lingkungan urban kota, propaganda poligami melalui workshop diberandol cukup mahal, berkisar 3-5 juta rupiah. Itu pun iming-imingnya sangat komplit, dari strategi meyakinkan istri agar tidak menolak poligami hingga manajemen keluarga bahagia.
Dengan asumsi bahwa kebanyakan para pengguna media sosial kita hanya membaca sekilas narasi singkat yang ditampilkan pada laman Instagram, yang mungkin terjadi adalah orang-orang akan buru-buru menyimpulkan bahwa lumrah bagi siapapun yang memiliki uang seperti orang kaya dari Arab untuk memaksa istrinya untuk mengizinkan suaminya berpoligami.
Padahal syarat inti dari poligami bukan faktor materi, namun bagaimana suami dapat bersikap adil terhadap para istri. Konsep adil sendiri sangatlah luas bukan hanya sekadar memberi nafkah tapi juga kepuasan batin, kasih sayang, dan sebagainya. Konsep ini lah yang sering diakali oleh para pelaku poligami, hingga pemaksaan terhadap istri pertama agar mau dimadu.
Pada paragraf lain di tulisan yang sama juga tertulis bahwa Islam identik dengan poligami. Memang betul bahwa poligami dipraktikkan oleh banyak lelaki muslim, tapi menyimpulkan praktik poligami langsung dengan Islam sebagai tradisi, menurut saya tidak tepat. Tafsir ayat-ayat dalam surat An-Nisa yang merujuk pada poligami sendiri diterjemahkan berbeda oleh banyak ulama. Justru hikmahnya adalah Islam datang untuk membatasi jumlah perempuan yang dapat dinikahi, dan menghentikan kesewenangan para pria zaman Jahiliyah dulu yang memberlakukan perempuan layaknya barang. Sehingga tidak bisa kita dengan gampangnya menyederhanakan tafsir ayat poligami yang kompleks dengan satu-dua kalimat saja.
Berkaitan dengan perbandingan praktik poligami di Arab dan di Afrika, hal ini juga perlu dicermati lebih jauh. Tidak serta merta laki-laki Arab yang rata-rata kaya dapat menjalankan poligaminya dengan lancar, tanpa konflik. Justru sebaliknya, dari tahun ke tahun semakin banyak perempuan di sana yang menolak untuk dimadu. Oleh karenanya, para pria Saudi cenderung memilih perempuan warga negara asing untuk menjadi istri kedua.
Di sisi lain, seiring dengan tingkat inflasi yang ikut naik, biaya pernikahan pun menjadi lebih tinggi. Bagi laki-laki yang tidak memiliki penghasilan cukup, mereka akhirnya melakukan praktik poligami serampangan demi menurutkan hawa nafsunya dengan cara kawin kontrak bersama perempuan dengan status ekonomi lemah. Ekspektasinya, istri kedua mereka yang kurang dari segi pendidikan dan ekonomi nantinya tidak dapat mengajukan gugatan tuntutan penghidupan.
Contoh nyatanya kita bisa lihat bagaimana pria-pria hidung belang dari Arab ini memanfaatkan situasi untuk menjerat para perempuan Sunda sebagai istri kedua berstatus kontrak di daerah Puncak, yang hingga kini terus berlangsung tanpa adanya tindakan tegas dari pemerintah setempat.
Di Afrika sendiri, warganya jauh lebih heterogen dari segi ras, keyakinan, hingga budaya. Praktik poligami dilakukan dengan dasar tradisi sosial yang sangat kental, bukan sekadar perintah agama. Di sana berkembang keyakinan bahwa semakin banyak seorang pria memiliki istri dan anak, hal itu dipercaya akan membuat ia beserta keluarganya panjang umur. Pelaku poligami pun beragam, dari penganut Kristen hingga animisme, bukan hanya dari kalangan muslim semata.
Sedangkan untuk persoalan kemiskinan, kita tahu bahwa tingkat ekonomi mayoritas negara Afrika memang jauh lebih rendah dengan negara-negara Arab, utamanya Arab Saudi. Tapi, menggunakan fakta tersebut untuk selanjutnya membuat komparasi yang terkesan diskriminatif juga sangat disayangkan.
Perlu diingat bahwa benua Afrika menghadapi persoalan sosial ekonomi yang kompleks sejak dulu kala. Selain terjajah ratusan tahun dan dieksploitasi kekayaan alamnya oleh para kolonial, akses yang kurang merata pada hampir semua pelayanan dan kebutuhan dasar, utamanya pendidikan membuat warganya kesulitan untuk memaksimalkan potensi diri melalui sekolah, yang akhirnya membuat mereka tak punya pilihan hidup lain selain menikah dan bekerja keras sejak usia kanak-kanak.
Sebuah studi dari James Fenske (2015) memperlihatkan bahwa pemberian kesempatan secara luas bagi para warga di sana untuk menempuh pendidikan dapat turut membantu mengurangi pernikahan anak, yang secara berkelanjutan mengurangi persentasi pernikahan poligami dan akar kemiskinan sistemik.
Hasil riset tersebut seakan memperlihatkan bahwa poligami bukanlah satu-satunya faktor penyebab langsung kemiskinan yang merata di Afrika. Bahkan bisa dibilang semacam lingkaran tak berujung karena perempuan yang mau dipoligami biasanya berharap tingkat kesejahteraan keluarga mereka naik setelah dinikahi, namun di sisi lain setelah menikah, justru mereka masih kesulitan keluar dari jebakan kemiskinan karena memiliki terlalu banyak tanggungan.
Melihat situasi yang kompleks seperti tadi, kita hendaknya dapat bersikap bijak dan lebih berhati-hati memilih diksi saat mengutarakan opini. Harapannya, agar orang yang awam dalam pengetahuan agama tidak kemudian dengan mudah mendiskreditkan Islam dengan praktik poligami yang dilakukan oleh oknum pemeluknya. Selain juga menghindarkan asumsi bahwa kekayaan materi sebagai syarat kunci dilakukannya poligami oleh seorang suami.
Padahal menakar isu poligami tidak bisa melalui satu perspektif semata. Perlu pemahaman mendalam untuk mendiskusikan hubungan kompleks antara penafsiran dan praktik ayat poligami, kemiskinan, dan dinamika sistem struktur sosial yang berkembang dalam peradaban global. (AN)
Wallahu a’lam.



