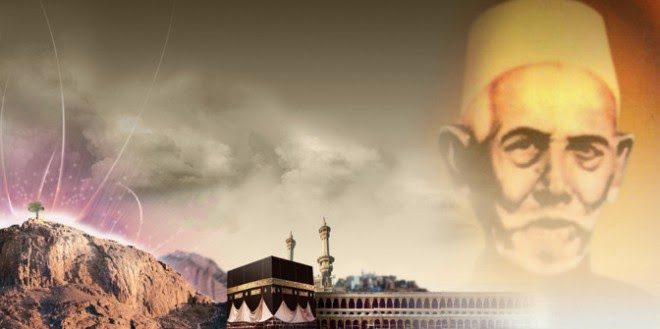
Perkembangan tafsir Nusantara pasca Abdurrauf al-Singkili agaknya sedikit meredup, karena banyaknya karya yang didominasi oleh kajian fiqih sentries. Fenomena ini bisa dilihat dan dibuktikan dari rentan kehidupan al-Singkili (abad ke-17) dengan Syekh Nawawi Banten (abad ke-19). Jarak yang cukup jauh tersebut menurut pandangan penulis merupakan kekosongan dari geliat tafsir Nusantara. Maka tak salah jika kemudian, tafsir al-Munir li Ma’alim al-Tanzil Maroh Labidz karya Syekh Nawawi Banten, sebagaimana yang akan penulis ulas di dalam tulisan ini menempati urutan yang kedua pasca terbitnya karya al-Singkili tersebut.
Boleh dibilang, masterpiece Syekh Nawawi di bidang tafsir ini merupakan komentar terhadap al-Qur’an secara keseluruhan yang terdiri dari dua jilid. Walau begitu, Tafsir Maroh Labidz, merupakan tafsir terlengkap berbahasa Arab setelah Tarjuman al-Mustafidz karya al-Singkili. Jika memandang pada sisi kelengkapannya, maka secara tak langsung tafsir ini ditabal sebagai tafsir kedua yang dimiliki oleh ulama Nusantara.
Ada yang menarik dari temuan penulis mengenai latarbelakang penyusunan kitab ini. Di mana banyaknya permintaan kepada Syekh Nawawi untuk menuangkan pemikirannya lewat kitab tafsir. Awalnya beliau enggan untuk menulis karena merasa tidak punya otoritas dalam bidang itu. Namun karena semakin banyaknya permintaan dari berbagai khalayak, disusunlah kitab tersebut dengan pendekatan yang berbeda dengan tafsir-tafsir sebelumnya.
Perbedaan paradigma dan metoda yang dibangun oleh Syekh Nawawi di dalam tafsir Maroh Labidz ini bukan tanpa alasan yang jelas. Setidaknya fakta historis mengungkap bahwa kala itu Mekkah sudah dikuasai oleh paham wahabi yang mau tak mau ada selektifitas ajaran dan pemikiran yang tak seragam. Kenyatan tersebut tentu berbeda tatkala Syarif Usman masih menjadi penguasa di Haramain. Sehingga dengan mempertimbangkan itu, Syekh Nawawi pun harus meminta rekomendasi dan persetujuan dari lembaga otoritas keagamaan yang pada waktu itu berpusat di al-Azhar Kairo.
Di sampaing karena faktor sebagaimana penulis kemukakan di muka, ada faktor lain yang tak kalah penting, yaitu reformasi pemikiran yang menurut Nor Huda dianggap sebagai penentang praktik sufisme. Mau tak mau Syekh Nawawi pun juga harus mengikuti arus mainstream yang ada. Sehingga dengan demikian, distingsi dari tafsir Maroh Labidz ini terletak pada spirit dalam membangun reformasi pemikiran. Karena tafsir itu pula kemudian Syekh Nawawi mendapat gelar “Sayyid Ulama al-Hijaz”, sebuah gelar tertinggi dalam ruang lingkup akademik yang di dalam istilah akademik modern dikenal dengan Guru Besar atau Profesor.
Referensi utama yang digunakan oleh Syekh Nawawi dalam menulis karyanya di bidang tafsir ini merupakan referensi standar sebagaimana tafsir-tafsir pada umumnya. Namun yang paling menarik untuk diperhatikan dengan seksama adalah pada segi substansial, di mana beliau banyak diilhami oleh Tafsir al-Kabir karya Fakhruddin al-Razi.
Bahkan menurut Peter G. Riddell yang dikutip oleh Nor Huda, setidaknya 70% pemikiran al-Razi diadopsi oleh Syekh Nawawi di dalam tafsirnya tersebut. Sedangkan sisanya adalah tafsir Jalalain yang menempati referensi sekunder, terutama dalam hal ulasan mengenai kedudukan suatu kalimat menurut perspektif kajian Nahwu-Sharraf di dalam tafsir tersebut.
Untuk mengetahui pendekatan yang dilakukan oleh Syekh Nawawi di dalam Maroh Labidz, kiranya perlu juga mengetahui beberapa indikator variabel referensi babonnya, yaitu Tafsir al-Kabir karya al-Razi. Seperti jamak diketahui bahwa tafsir al-Razi banyak mengulas persoalan ilmu kalam, ilmu fiqih, filsafat, dan masalah-masalah teologis lainnya di dalam karyanya itu. Ini pula yang mengantarkan al-Razi sebagai salah seorang ulama yang dalam banyak hal selalu mengedepankan sisi rasionalitas, dan karena usahanya itu ia seringkali berbeda pandangan dengan para ulama pada masanya.
Keunikan al-Razi di dalam mengemukakan pendapat terletak pada kepiawaiannya dalam melakukan aproaching persuasive sebagai salah satu metode. Hal ini terlihat pada suguhan kisah-kisah yang mampu dipahami oleh kalangan awam serta suguhan sistematika teori rumit nan filosofis yang mampu mengajak dialog para kaum cendekiawan, baik pada masanya atau jauh setelahnya. Barangkali itulah yang menyebabkan Syekh Nawawi begitu tertarik untuk menjadikan tafsir al-Kabir sebagai referensi babon di dalam penulisan tafsirnya.
Tetapi walaupun begitu, Syekh Nawawi tidak an sich menerapkan pendapat al-Razi dalam artian hanya meng-copy-paste. Ada semacam penyeleksian yang begitu akurat, sehingga kadang-kadang Syekh Nawawi tidak hanya mengamini pendapat yang dilontarkan oleh al-Razi, namun di lain pihak ia juga menyanggah dengan argumentasi yang lebih kuat serta lebih relevan dengan realiatas konteks kekinian.
Dalam konteks perdebatan teologis misalnya, Syekh Nawawi memberikan ilustrasi rasional sebagaimana yang dipaparkan al-Razi, terutama dalam persoalan istiwa’ yang menjadi polemik antara kaum rasionalis versus kaum literalis. Hingga kini rasionalitas Syekh Nawawi dalam menjelaskan kalimat istiwa’ dengan pendekatan takwil itu dapat kita rasakan atmosfirnya berkat usaha para muridnya dalam menyebarkan pemikirannya tersebut ke Asia Tenggara.
Dengan demikian tak salah, jika kemudian Asia Tenggara terutama Nusantara menjadi basis dari paham Ahlusunnah Wal Jamaah dengan pijakan al-Asy’ari dan al-Maturidi sebagai madzhab teologi. Wallahu A’lam bis Shawab. []
Mohammad Khoiron, Akademisi di Pascasarjana Universitas Nahdlatul Ulama Jakarta, dan Sekretaris Aswaja Center NU DKI Jakarta.



