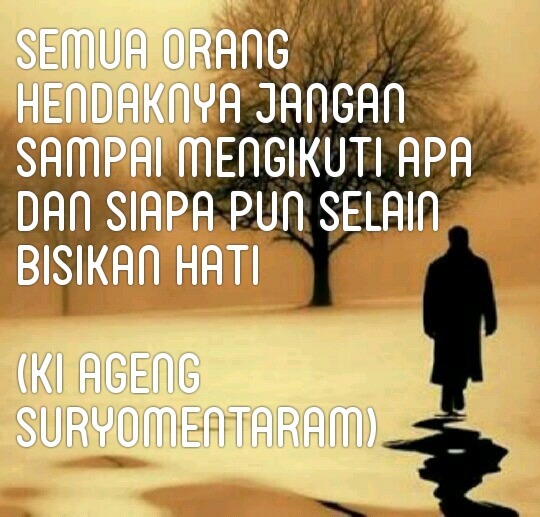
Ki Ageng Suryomentaram, filsuf Jawa abad 19, memiliki konsep yang menarik tentang bagaimana sebaiknya seseorang ketika tengah belajar, dan apa pula yang mestinya dilakukan oleh seorang pengajar. Dalam Buku Langgar halaman 26 termaktub salah satu surat Ki Ageng kepada sahabatnya, Kakang Sumarsono, yang diharapkannya dapat menggantikan dirinya sebagai narasumber untuk memberikan kuliah umum di Semarang.
Surat ini disampaikan Ki Ageng kepada seseorang yang menurutnya sudah layak menjadi pengajar, tentu saja mesti dipahami dengan kacamata dan pemahaman orang yang sudah dewasa dalam hal ajar mengajar. Jadi, tidak semestinya jika surat Ki Ageng ini dimaknai secara harfiah. Apalagi oleh orang yang di dalam merespon segala sesuatu dan peristiwa masih berlandaskan rasa suka atau tidak sukanya.
Berikut ini adalah kutipan suratnya secara utuh. Tanpa basa-basi, Ki Ageng langsung menegaskan lima hal yang tidak seyogyanya dilakukan oleh mereka yang sedang belajar.
Pertama, “Wong-wong mau aja nganti anggugu menyang guru-guru sejene. Jalaran guru-guru iku ngelmune padha kleru kabeh. Aku wis weruh. Gilo klerune guru-guru mau: Ngelmune mesthi sing condong karo pepinginane, nganggo dikon cegah kayata; mangan, turu, cumbana, sapiturute. Utawa banter nglakoni kayata; sabar, mantep, temen, sapiturute. Kuwi guru apa kaya ngono kuwi? Hla, apa patut digugu?”
(Sebagai pribadi, semua orang hendaknya jangan sampai mengikuti apa dan siapa pun selain bisikan kata hati terdalamnya. Karena niat apa pun selain yang berasal dari kata hati terdalam, meski dengan dalih mengikuti ajaran dari para guru, pasti keliru. Saya dapat pastikan, fatal sekali kesalahan para guru yang ajarannya dibiarkan diikuti oleh orang banyak dengan cara seperti itu.
Ya, karena ilmu para guru tersebut pasti condong kepada keinginan pribadinya, meskipun melalui pantangan seperti; jangan makan, jangan tidur, jangan bersenang-senang, dan lain sebagainya. Atau memerintahkan laku seperti; sabar, yakin, sunguh-sungguh, dan lain sebagainya. Guru macam apa itu? Memangnya pantas pengajar seperti itu diikuti?)
Kedua, “Wong-wong mau supaya anggugu karepe dhewe, jalaran sok anggugu kitab, gugu Kanjeng Sultan Agung, Prabu Brawijaya, Jayabaya, utawa layang-layang babad. Lha, rak ya pating jengkelit ta? Uwong jare gugu mrana-mrana.”
(Setiap orang hendaknya mengikuti apa yang telah dibisikkan oleh hati terdalamnya. Jangan begitu saja mengikuti pengetahuan yang tertulis dalam buku-buku, mengikuti Kanjeng Sultan Agung, Prabu Brawijaya, Jayabaya, atau cerita-cerita rakyat yang disebut babad alias kronik. Akan menjadi tidak karu-karuan bukan? Masa orang mesti mengikuti sesuatu yang tidak sesuai dengan kata hatinya sendiri?)
Ketiga, “Wong-wong mau aja nganti anggugu pangarep-arepe dhewe. Kayata; awake dhewe nek ngono enthuk kamulyan, utawa anak putune, utawa bangsane. Hla, apa ora pating besasik? Ana wong jare andongakake sapa-sapa, utawa awake dhewe.”
(Setiap orang hendaknya juga tak menuruti berbagai keinginan pribadinya. Misalnya; kalau aku melakukan begitu, mungkin akan mendapatkan kemuliaan. Jika bukan aku yang mendapatkan kemuliaan, ya mungkin anak cucuku yang akan memperolehnya kelak. Kalau bangsaku tidak melakukan… Ah, apa jadinya jika berbagai keinginan itu dituruti? Masa orang hanya mengharap-harapkan orang lain atau dirinya sendiri?)
Keempat, “Wong-wong mau aja ngleluri sapa-sapa; tegese tiru-tiru. Kayata; bapa biyung, kaki nini. Utawa tiru-tiru wong sing luwih-luwih. Rak ya salang surup ta, nek wong kok angluluri kuwi hara? Haraya, ana apa ngalura-ngaluri?”
(Setiap orang hendaknya juga tidak menjadi pembebek dari siapa pun. Artinya, jangan hanya meniru-niru! Misalnya; meniru orang tua, meniru nenek moyang. Atau meniru orang-orang yang dianggap memilki kelebihan. Nah, bisa menjadi salah kaprah bukan? Masa orang mesti membebek kepada orang lain? Masa iya harus menjadi pembebek?)
Terakhir, “Wong-wong aja nganti memundi, kayata; wong, kitab, kramatan, Borobudur, kaelokan, sapanunggalane. Cekake awake dhewe iki wis becik dhewe. Tegese; wis ora ana barang utawa wong sing diajeni. Hla, apa ora kuwalik cengele, ana wong kok ngajeni mrana-mrana?”
(Setiap orang hendaknya juga jangan mengkultuskan siapa pun. Misalnya; orang atau kitab yang dianggap suci, berbagai keramat, Borobudur, segala yang dikagumi, dan lain sebagainya. Artinya, tak ada apa dan siapa pun yang pantas dikultuskan. Nah, apakah tidak terbalik tengkuknya, masa ke mana-mana orang mesti mengultuskan sesuatu?)
Baru kemudian dengan lugas Ki Ageng menulis, “Nek Kakang Sumarsono mangerti ing dhuwur iki, mesthi banjur kaduga mejang. Apa witikna wong-wong mau dipitayakake nyang guru-guru. Ing mangka mejang iku volksopvoeding. Nek ora nganggo wejangan iki, pole mesthi dadi wong gumunan; ming ana wong awas wae gumun, ming ana wong ora tau mangan wae gumun, ming ana wong mandi bae gumun, ming ana wong gawe Borobudur bae gumun, ming ana montor mabur bae gumun, basa awake dhewe ora digumuni.”
(Kalau Kakang Sumarsono telah memahami intisari yang saya maksudkan di atas, Insya Allah telah memiliki kesiapan untuk menjadi nara sumber. Ya, karena memberikan kuliah itu volksopvoeding alias mendidik masyarakat, maka tiap-tiap orang tidak semestinya diarahkan untuk mengikuti selain kata hati terdalamnya masing-masing.
Jika tidak demikian, maka ujung-ujungnya hanya membuat orang untuk mudah terkaget-kaget; ada orang dapat mengetahui sesuatu sebelum terjadi, tercengang; melihat orang yang sepertinya tidak pernah makan, heran; melihat orang yang sepertinya dapat menyembuhkan berbagai penyakit, kagum; melihat orang bisa membangun Borobudur, takjub; melihat pesawat terbang, heran; tapi terhadap keberadaan dirinya sendiri malah tidak pernah dipedulikan keistimewaannya.)
“Leting dongeng, aku ngarep-arep banget menyang Kakang Sumarsono supaya tumuli angganteni mejang ana Semarang. Perlu banget, lho. Dene nek aneng Ngayogya wis ana sing ngganteni. Aku ngarep-arep diwangsuli lho. Nek Kakang wus kaduga (tak pestekake lho), atiku ayem. Seje dina bokmenawa aku bisa ketemu. Nirtiti, Arinta: WG Suryomentaram.”
(Singkat cerita, saya sangat berharap suatu ketika Kakang Sumarsono dapat menggantikan saya untuk memberikan kuliah umum di Semarang. Ini serius, karena kalau di Yogyakarta kan sudah ada yang bisa menggantikan saya. Saya sangat mengharapkan balasan surat ini. Begitu Kakang Sumarsono sudah menyatakan siap—saya mengharapkan kepastiannya—hati saya tenteram. Mudah-mudahan lain hari kita bisa ketemu. Sampai sini dulu, Adikmu: Wong Gedhe Suryomentaram.)
Surat Ki Ageng di atas meskipun dengan diksi yang berbeda, bahkan terkesan sebaliknya, menurut saya sebangun dengan aforisma Syaikh Ibn ‘Athaillah Sakandariy dalam Al-Hikam, “Man ‘abbara min bisaathi ihsaanihi ashammathu isaa’ah. Waman ‘abbara min bisaathi ihsaanillaahi ilaihi lam yashmut idza asaa’a.” (Pengajar yang merasa dirinya sebagai orang baik, akan diam—bahkan menutupinya—saat melakukan kesalahan. Sedangkan pembelajar yang sadar akan kebaikan Allah terhadap dirinya, tidak akan pernah diam—setidaknya mengakui dan meminta maaf—ketika telah melakukan kesalahan). Wallaahu a’lam bishshawwab.



