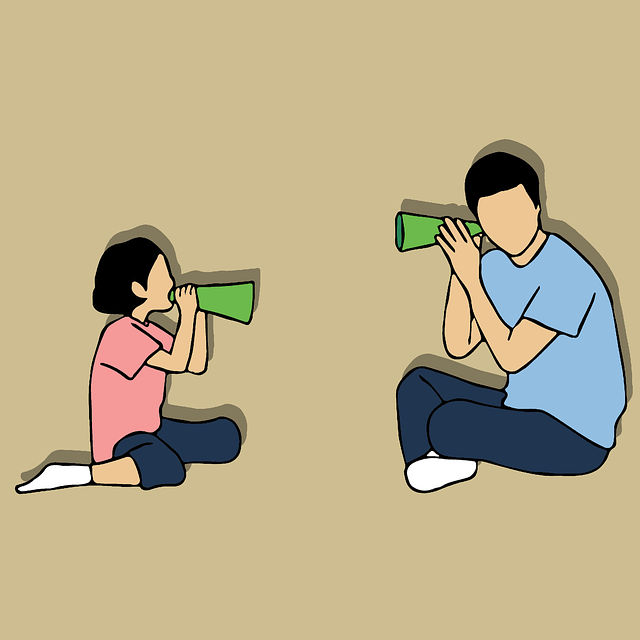
Saya tidak punya kepakaran di bidang tafsir. Tetapi, belakangan terakhir banyak melihat tumpang-tindih pengutipan ayat ataupun hadist oleh orang tua terhadap anak di beberapa keluarga dengan corak latar sosial, ekonomi dan kebudayaan yang berbeda. Dan masing-masing pengutipan yang dilakukan itu mengekspresikan tujuan-tujuan yang berbeda pula: ada yang mengekspresikan pengukuhan otoritas, ada yang mengekspresikan pendidikan akhlaq anak, dan ada yang mengekspresikan pengukuhkan kontrol.
Dengan kata lain, ada kelenturan dalam praktik pengutipan dan penerapan ayat dan hadist tentang orang tua. Walaupun ayat dan hadist tentang orang tua sangat menggema di Masjid, media sosial dan berbagai kesempatan religius, namun mengapa pada praktik dan pengutipannya bisa sedemikian lentur? Apakah dari gema yang sedemikian besar itu tidak memuat keberagaman kontekstualisasi hubungan orang tua dan anak? Atau memang kecenderungan manusia untuk memilih penafsiran yang hanya menguntungkannya kental terjadi dalam praktik pengutipan ayat dan hadist ini?
Tulisan ini tidak bermaksud memberikan penafsiran yang memadai atas kelenturan tersebut, namun bermaksud untuk menunjukkan bahwa ada masalah serius yang belum terlesaikan antara hubungan: ayat dan hadist tentang orang tua, dinamika intergenerasi, dan praktik parenting. Ada sebuah paradoks yang umum terjadi:
Pada satu sisi, ayat dan hadist tentang orang tua digunakan sebagai ‘panduan’ soal ketertataan sel terkecil masyarakat (keluarga). Di lain sisi, ayat dan hadist tentang orang tua tidak jarang digunakan sebagai instrumen yang membenarkan sikap otoritarian dan membolehkan orang tua untuk tidak bersikap dialogis―sebuah prakondisi bagi anak di mana trauma dan luka psikologis dapat terjadi di kemudian hari.
Walaupun muatan ayat dan hadist tentang orang tua secara literal hanya menekankan pada pentingnya menghormati dan berbakti pada orang tua, namun resonansinya dalam kehidupan sehari-hari merentang hingga ke aspek gaya bahasa, konflik antar generasi, dan aspek sosial-ekonomi.
Ayat dan hadist tentang orang tua akan menemukan dilemma interpretasi, misalnya, ketika praktik parenting diwarnai dengan gaya bahasa yang doktriner, instruktif, intimidatif dan komunikasi yang kering empati terhadap apa yang anak sukai dan rasakan.
Kalau si anak, katakanlah, memiliki wawasan tafsir Qur’an/Hadist yang luas, atau memiliki wawasan hermeneutika yang memadai, maka si anak mungkin masih bisa ‘memahami’ faktor-faktor halus yang menyebabkan parenting-nya seperti itu, dan masih bisa merumuskan alasan untuk tetap menghormati orang tuanya, meski ia sadar bahwa pada derajat tertentu kenyataan yang dihadapinya itu agak bertentangan dengan apa yang idealnya terjadi.
Kalau si anak tidak mememiliki dua wawasan itu, maka potensi burn-out, kecewa, marah, dan perasaan tak dihargai dan tertekan dapat menjadi alasan yang lebih kuat baginya untuk menyampingkan anjuran ayat dan hadist tentang orang tua. Dan pada gilirannya, ketidak-hormatan atau bahkan tindakan agresif terhadap orang tua akan mudah terjadi.
Lebih banyak mana, antara anak jenis pertama dan anak jenis kedua? Masing-masing dari kita sudah tau mana yang jumlahnya lebih banyak. Dan pada situasi yang dialami anak jenis kedua inilah, ayat dan hadist tentang orang tua menemukan dilemma interpretasi: pada satu sisi dianggap melanggengkan ketertataan sel terkecil masyarakat dan mengamalkan perintah Allah & Rasul, namun di lain sisi justru memiliki potensi besar untuk memelihara lingkaran kekerasan terhadap anak, entah yang berupa verbal ataupun psikologis.
Masalah serupa juga dapat ditemukan dalam ayat atau hadist tentang berbakti pada orang tua. Misalnya, dalam konteks keluarga muslim modern perkotaan. Ambillah contoh begini:
Ada sepasang muda-mudi yang mesantren. Di pondok, mereka belajar fikih, nahwu, tasawuf, tauhid, dan lain-lain. Setelah lulus, mereka menikah, lalu merantau ke kota. Setelah 15 tahun di kota, sejahteralah hidup mereka dengan rupa-rupa harta dan privilege sosial modern yang dimiliki. Mereka punya anak, dan dipondokkanlah anaknya di salah satu pesantren salaf di kampung terpencil―jauh dari hiruk-pikuk dan gemerlap kota. Setelah 7 tahun mondok di kampung, si anak pulang ke rumah.
Dalam skenario itu, gap perbedaan makna ‘berbakti orang tua’ yang dimiliki si anak dan orang tua sangat ditentukan oleh dua faktor: pertama, seberapa lunturnya nilai-nilai pesantren oleh nilai-nilai urban-modern yang orang tua alami. Dan kedua, seberapa meresapnya nilai-nilai pesantren dan nilai-nilai kampung yang dipeluk si anak.
Di sadari atau tidak, nilai-nilai urban modern dapat memengaruhi orang tua melalui kehidupan sehari-hari (seperti orbrolan tetangga, televisi, belanja ke mall dan lain-lain). Dalam pengaruh ini, makna ‘menghormati orang tua’ dapat mengarah pada ukuran-ukuran yang sangat materil seperti seberapa banyak jumlah uang dan seberapa mahalnya benda yang diberikan.
Sementara itu, dalam pengaruh nilai-nilai pesantren dan nilai-nilai kampung, si anak dapat mencita-citakan kehidupan yang sunyi dan asketis. Baginya, ‘menghormati orang tua’ adalah soal seberapa bermanfaat dan seberapa tulus pemberian yang diberikan. Bukan soal nominal.
Konflik antara orang tua dan anak dapat terjadi kalau ayat dan hadist tentang orang tua dipahami dalam dua konstruk budaya yang berbeda: yang satu konsumeris, yang satu asketis. Pada gilirannya, perbedaan tersebut dapat menjadi bom waktu ketika si anak dan orang tua mengalami penuaan, dan filial piety mulai terjadi (yakni, anak harus membalas budi orang orang tua ketika mereka lansia).
Dalam skenario itu, pandangan yang umumnya diterapkan adalah: “apapun kondisinya, anak harus tetap menghormati dan berbakti pada orang tua. Mutlak.” Tetapi pandangan ini membuka celah pertanyaan bagi ayat dan hadist tentang orang tua: apakah ayat dan hadist tentang orang tua adalah jenis teks suci yang terbuka pada ukuran-ukuran kehidupan apapun? Walaupun itu termasuk ukuran-ukuran kapitalistik?
Di lain sisi, pandangan itu juga dapat menarik pengkultusan orang tua pada ambang batas yang sangat subjektif. Dampaknya, kebenaran sering kali juga ikut termonopoli pada standar-standar yang subjektif. Ada yang mengatakan bahwa dalam situasi seperti ini maka yang dikedepankan adalah akhlaq, bukan ilmu ataupun nalar. Pada situasi tersebut, ‘akhlaq’ akhirnya menjadi istilah yang lentur: ia dapat digunakan untuk mendiskreditkan anak yang vokal memberikan koreksi, tapi sekaligus juga dapat digunakan untuk memuji anak yang nurut-nurut aja meskipun hidupnya telah terbonsai oleh kekerasan verbal dan mental.
Pada situasi itu, kita masih belum memiliki mekanisme yang memadai untuk mengorganisir bagaimana akhlaq, standar kebenaran dan etika seharusnya diposisikan secara proporsional agar hubungan orang tua dan anak yang dialogis dan konstruktif dapat terbudayakan. Sebaliknya, absennya mekanisme itu justru sering kali ditutupi oleh klaim normatif yang hanya menguntungkan satu pihak.
Dari dua contoh skenario yang telah disebutkan, ada beberapa pertanyaan yang bisa diajukan lebih jauh: Apakah Al-Qur’an dan Nabi Muhammad memang menyajikan ayat dan hadist tentang orang tua agar dihayati secara literal? Kalau ada konteksnya, lalu sejauh apa batasan konteks tersebut? Apakah batas konteks tersebut hanya berada ketika orang tua menyuruh hal-hal negatif dan melanggar syariat?
Kalau praktik parenting yang meninggalkan dampak negatif di anak (baik itu praktik wacana, gaya ataupun gestur nir-empati dalam bahasa) tidak termasuk sebagai batasan konteks, maka apakah mungkin Allah dan Rasullah tidak mempertimbangkan potensi praktik toxic parenting dan resiko-resko psikologis yang dialami si anak?
Atau, jangan-jangan, hal itu justru disebabkan karena bias penghayatan kita yang lebih berkecenderungan pada penafsiran literal dibanding penafsiran yang rigit (baik dari segi historis ataupun kultural) karena pertimbangan keuntungan yang dapat dinikmati oleh salah satu pihak dari karakter penafsiran tertentu? bukankah jika demikian maka akan ada salah satu pihak lain yang dirugikan atasnya?
Masih ingat ayat dan hadist soal kepemimpinan laki-laki lebih unggul dibanding perempuan? Redaksi literal ayat dan hadist itu banyak dipolitisasi oleh sebagian kalangan, baik untuk tujuan memelihara patriarki ataupun untuk tujuan Islam politik. Pun, banyak produk-produk tafsirnya yang ternyata bias maskulin. Penafsiran yang literal dan penafsiran yang bias maskulin itu kemudian dibongkar habis-habisan karena dianggap melanggengkan praktik ketidak-adilan gender.
Apakah ayat dan hadist tentang orang tua juga mengalami hal serupa?
Yang jelas, sekecil apapun angka statistik kasus toxic parenting itu tidak dapat ditoleransi. Kita tidak bisa menutup mata bahwa kadang praktik toxic parenting juga melibatkan narasi-narasi agama. Di sini, ayat dan hadist tentang orang tua masih menjadi puzzle yang penting untuk dipercahkan agar tidak mudah dicatut untuk memelihara relasi timpang antara orang tua dan anak.



