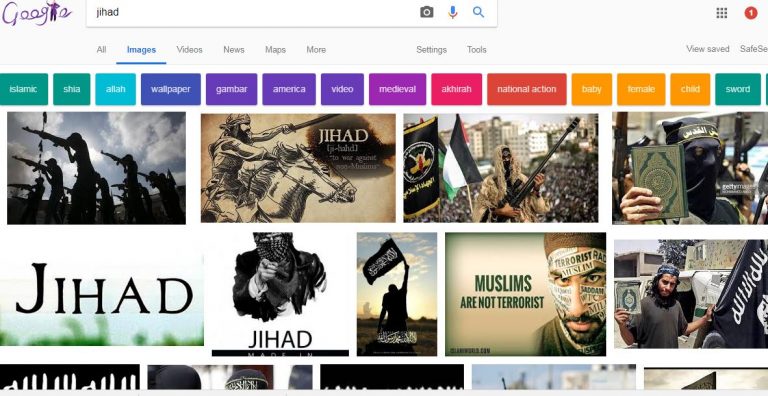
Moderasi beragama, atau pengurangan kekerasan dalam beragama, punya spektrum yang luas. Cakupannya tidak hanya soal penghapusan terorisme dan radikalisme, tapi juga mencakup dari mulai toleransi dalam bermasyarakat, hingga memastikan bahwa semua orang mendapat kesejahteraan yang adil. Sebabnya, ketimpangan sosial sering kali menyulut api cemburu yang berujung pada intoleransi dan konflik sosial.
Dalam konteks itu, Islam sebagai agama punya kewajiban untuk mewujudkan rahmatan lil alamin-nya dengan pendekatan yang tidak berhenti sekedar pada aspek ibadah dan kesalehan vertikal. Dengan kata lain, ada tanggung jawab sosial yang perlu dihitung sepadan sebagaimana laku ibadah vertikal.
Untuk mewujudkan hal itu, maka dibutuhkan cara berislam yang jelas. Jelas rantai keilmuannya, jelas bengunan metodologisnya, jelas kepakarannya, dan jelas tirakat belajarnya. ‘Kejelasan’ ini dibutuhkan agar si muslim punya kecakapan dalam mengidentifikasi dan mengurai kompleksitas masalah kehidupan yang ada.
Artinya, ia tidak gagap dalam membedah ataupun bersikap ketika berhadapan dengan masalah-masalah seperti: tumpang tindih antara budaya dan agama; antara dimensi vertikal dan dimensi horizontal dalam doa lintas iman; ataupun menjalin misi perdamaian ke Israel. Dengan adanya kejelasan cara dalam berislam, dimensi ilahiyah dan insaniyyah dapat terjembatani dengan konstruktif tanpa perlu membenturkan ataupun mengorbankan salah satunya.
Saat ‘kejelasan’ itu dipegang oleh umat Islam secara luas, maka umat Islam akan punya cukup kedewasaan untuk mempraktikkan―apa yang dalam bahasanya Gus Dur― “memberikan sumbangan, namun tidak lantas mengklaim.”
Kejelasan itu ada pada santri. Masalahnya, saat ini kredibilitas santri sedang ditantang secara terbuka oleh the new santri yang rantai keilmuan, bangunan metodologis, kepakaran, dan tirakat belajarnya dipertanyakan. Bila otoritas keagamaan berpindah ke the new santri, maka moderasi beragama mustahil dicapai.
Istilah ‘santri’ punya akar sejarah yang panjang di kehidupan Nusantara khususnya, dan Asia Tenggara umumnya. ‘Santri’ merujuk pada orang yang melakukan laku tirakat belajar pada guru tertentu dalam periode yang tidak sebentar. Dalam hal ini, pesantren menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari makna ‘santri’ itu sendiri.
Akan tetapi, istilah ‘santri’ saat ini mengalami upaya pelonggaran makna karena dicatut oleh kelompok belajar agama berbasis daring yang mencomot kata ‘santri’ sebagai identitas kesalehan fanatis hasil belajar agama yang sebentar.
Per-Oktober 2020, Pangkalan Data Pondok Pesantren milik Kementerian Agama mencatat ada 4.077.161 santri, baik itu yang mukim dan tidak mukim. Angka ini tentu diasumsikan berada pada rentang usia jenjang sekolah menengah pertama hingga usia kuliah. Bandingkan dengan jumlah pengikut Hannan Attaki yang mencapai 8.3 Juta dan Felix Siauw yang berjumlah 4.7 juta di Instagram, yang jangkauannya bisa merentang dari mulai usia sekolah menengah pertama hingga usia dewasa mapan.
Angka itu menandakan bahwa, otoritas kepakaran yang ditawarkan pesantren punya kualitas kematangan yang solid namun punya jangkauan yang sangat terbatas―baik karena faktor geografis ataupun karena aturan pondok yang membatasi mobilitas si santri. Sebaliknya, otoritas berbasis likes yang ditawarkan non-pakar di media sosial punya kualitas yang rapuh namun punya jangkauan audiens yang luar biasa.
Makalahnya Zuliati Rahmah yang berjudul Revealing Millenials’ Styles and Religious Teachers’ Readiness: Rethinking Education for Digital Natives yang disampaikan di AICIS 2019, menemukan bahwa media sosial adalah sarana belajar agama yang paling diminati anak muda. Kampus dan pesantren dikalahkan posisinya oleh media sosial. Berkaca dari temuan itu, ada potensi bahwa the new santri akan menjadi corak beragama yang normal di masa depan. Resiko perubahan ini juga beriringan sejalan dengan berubahnya cara pandang hidup masyarakat akibat digitalisasi.
Perubahan media sama dengan perubahan pola pikir, dan perubahan pola pikir sama dengan perubahan cara pandang. Siklus ini terus terjadi dari mulai era oral Nabi Musa, era tulisan Syekh Mahfudz Tremas, era TV Zainuddin MZ, hingga era media sosial Felix Siauw.
Pesantren adalah institusi yang cara pandangnya berakar dari era tulisan. karakternya cenderung analitik, ketat dalam berbahasa, rapih dalam berlogika, sangat berhati-hati dalam membuat prejudis, rendah hati dalam beriman dan selalu digawangi oleh seorang pakar (Kiai). Kakater-karakter tersebut melebur dalam muatan kitab kuning, fiqh, nahwu shorof, tasawuf, dan tradisi setoran yang ditempa setiap hari.
Sementara itu, media sosial punya karakter puitik, hiperbolis, terfragmentasi, terpersonifikasi dan cenderung ekshibisionis. Itu sebabnya, agama di media sosial disampaikan dalam bentuk video pendek atau gambar yang tidak utuh, disertai musik yang syahdu, bertabur diksi-diksi yang menggugah emosi, penuh pencitraan, memantulkan ilusi kesakralan yang sebenarnya hanya komoditas informasi, dan terseleksi oleh algoritma yang hanya menampilkan konten yang mengafirmasi kepercayaan atau kebencian kita terhadap suatu hal.
Artinya, energi utama beragama a la media sosial adalah emosi dan ilusi. Bukan kejelasan rantai keilmuan, metode belajar dan kejelasan kiai pendamping. Di saat yang sama, masalah ini dapat menjadi bola salju ketika disentuh oleh upaya pengkotak-kotakan, baik itu untuk tujuan politik ataupun tujuan partisan. ‘Moderasi beragama’ seperti apa yang dapat dicapai oleh cara berislam yang demikian? Tentu tidak seperti apa-apa, karena memang mustahil dicapai bila caranya seperti itu.
Untuk menghadapi tantangan yang telah diuraikan, ada beberapa hal yang bisa dilakukan santri dan pesantren. Pertama, pesantren perlu mendudukkan dengan tuntas apa itu ‘digital,’ dan bagaimana mengonversi muatan pengetahuan agama dari tradisi tulisan ke tradisi digital tanpa mengubah cara pandang si audiens. Di samping itu, upaya ini juga diperlukan untuk menertibkan ‘influenser’ yang cara kerjanya berporos pada ekshibisionisme yang jelas bertentangan dengan prinsip tasawuf.
Kedua, bila poin nomer satu telah berhasil didudukkan, maka pesantren perlu membuat strategi dakwah digital yang melibatkan santri dengan usia tertentu yang punya cukup pengaruh, baik itu dari segi daya tarik visual, pendidikan, ataupun pencapaiannya. Ini diperlukan untuk dapat bersaing dengan pendakwah non-pakar yang punya pesona luar biasa namun kualitas yang rapuh.
Ketiga, dakwah daring yang telah dilakukan perlu diimbangi dengan kegiatan luring agar proses moderasi beragama yang diinginkan bisa memecah efek ‘kacamata kuda’ (filter bubble) yang berasal dari algoritma media sosial. Pesantren atau komunitas santri dapat menginisiasi ruang-ruang dialog, baik itu lintas agama, budaya, ataupun ideologi, agar audiens awam yang telah terjaring dakwah daring pesantren benar-benar terpapar oleh keberagaman yang esensial.
Keempat, tradisi intelektualisme pesantren seperti keketatan dalam berbahasan, kerapihan dalam berlogika, kemampuan analisis, dan keimanan yang rendah hati perlu disediakan dalam sajian yang dapat diakses oleh masyarakat umum, khususnya kalangan awam. Hal ini diperlukan agar kemampuan mengurai dan mengidentifikasi masalah kehidupan bisa dimiliki oleh semua orang. Di samping itu, upaya ini juga berperan sebagai literasi informasi yang secara tidak langsung diwarnai oleh pesantren.
Artikel ini terbit atas kerjasama dengan Biro Humas, Data, dan Informasi Kementerian Agama RI



