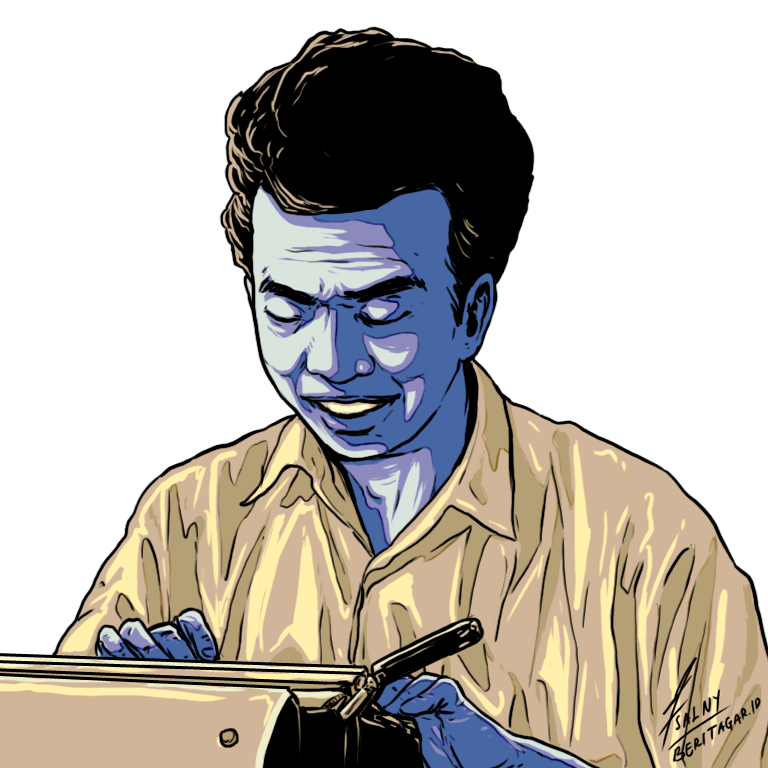
Pada penghujung Maret 1973, sebuah sepeda motor menabrak Ahmad Wahib yang baru pulang dari kantor Majalah Tempo tempatnya bekerja. Itu terjadi di persimpangan jalan Senen Raya – Kalilio di siang hari, tak jauh dari kantor Tempo yang kala itu masih bertempat di kawasan Senen Raya.
Wahib dilarikan ke Rumah Sakit Gatot Subroto, tapi kondisinya terlalu parah, ia dirujuk ke RSUP. Di tengah perjalanan menuju RSUP ia meninggal. Ia mati muda, pada usia menjelang 31 tahun.
Djohan Effendi, mendengar kabar kematian karibnya esok hari pada satu April dini hari dari seorang kawan yang menghubunginya melalui sambungan telepon dengan terbata-bata. Goenawan Mohamad, pemimpin redaksi, tak kalah terkejut mendapati kabar itu.
Setelah Wahib mangkat, Goenawan, Putu Wijaya dan Syu’bah Asa menuju kamar kontrakan Wahib di sebuah gang sempit di jalan Kebon Kacang. Di kontrakan itu mereka menemukan catatan-catatan harian Wahib. Goenawan tidak berani lancang menyentuh.
Ia mengaku tak mengenal dekat Ahmad Wahib. Sepanjang delapan bulan Wahib bekerja sebelum akhirnya mangkat, dia mengingat Wahib sebagai anak muda yang sangat pendiam, pemalu, dan sederhana. Dari Syu’bah Asa, kepala bagian urusan keagamaan dan yang membawa Wahib ke Tempo, ia mengenal Wahib.
“Ahmad Wahib selalu tersenyum, sangat peka dan sensitif. Sehingga kadang saya tidak sampai hati menyuruh dia meliput yang tidak ada hubungannya dengan agama. Tapi karena saya tidak boleh pilih kasih, saya suruh Syu’bah Asa yang berikan tugas,” sembari berkelakar ia mencoba menggambarkan sosok Wahib yang ada dalam ingatannya.
Lain Goenawan lain Djohan, setelah mendengar kabar meninggalnya Wahib sebagai kawan yang kenal dekat dengan Wahib, ia segera terpikir untuk menyelamatkan catatan harian tersebut. Ahmad Wahib sendiri selama hidup tidak pernah menunjukkan catatan itu padanya, tapi tanpa sepengetahuan Wahib Djohan diam-diam sering membaca.
Segera ia pergi ke kontrakan Wahib, menyelamatkan bundelan yang berisi artikel dan catatan harian yang ditulis Ahmad Wahib. Djohan lantas meminta izin keluarga Wahib untuk mengamankan bundelan tersebut. Catatan tersebut kemudian diterbitkan menjadi sebuah buku.
***
Satu lagi kesan yang Goenawan ingat dari Wahib adalah kedalaman, “Dia pemalu, saya menangkap ada yang dalam dari orang ini saat ia berbicara, dengan malu-malu.”
Ingatan-ingatan itu Goenawan sampaikan 39 tahun setelah kematian Wahib, saat memberi sambuatan pada penghargaan Sayembara Ahmad Wahib.
Sementara, bundelan terikat rapi yang Djohan temukan di kontrakan Wahib ternyata berisi artikel dan tujuh belas buku catatan harian. Di bawah pengawasan Djohan Effendi, buku harian Wahib disunting oleh Ismet Natsir.
Pada 1981, suntingan itu diterbitkan oleh LP3ES menjadi buku berjudul Pergolakan Pemikiran Islam, Catatan Harian Ahmad Wahib. Mukti Ali, yang pernah menjabat sebagai Menteri Agama pada kabinet Pembangunan II, memberi pengantar.
Dalam pengantarnya, Mukti ali mengenang Wahib sebagai anak muda yang ‘seringkali mengeluarkan pendapat-pendapat yang tidak biasa didengar oleh banyak orang, terutama yang berkaitan dengan masalah-masalah agama.’ Perkenalan mereka terjalin oleh diskusi mingguan diadakan yang di rumah Mukti Ali di kawasan Demangan, Yogyakarta. Diskusi itu digelar tiap Jumat sore antara pertengahan tahun 1967 hingga 1971.
Kesan yang ia tangkap saat itu, Wahib sedang menghadapi pergulatan pemikiran yang keras dalam proses pencariannya. Kelompok diskusi tersebut diberi nama “Lingkaran Diskusi Limited Group”, nama yang menurut Mukti Ali dicetuskan oleh Ahmad Wahib.
Anggota inti kelompok diskusi, yang selalu hadir dan menentukan tema diskusi, adalah Djohan Effendi, Mukti Ali, Dawam Rahardjo, dan Ahmad Wahib.
Kawan-kawan lain yang juga kerap hadir di diskusi tersebut adalah Syu’bah Asa, Kuntowidjojo, Wadjiz Anwar, Kamal Muchtar, Saifullah Mahyuddin, Djauhari Muhsin, Muin Umar dan Simuh. Mereka membicarakan masalah-masalah yang berkatian dengan agama, budaya dan masyarakat.
Dalam forum yang berisi mayoritas anak muda dua puluhan tersebut tak jarang muncul pertanyaan-pertanyaan terkait teologi yang dianggap tidak umum oleh orang Islam kebanyakan. Dalam pengantarnya, Mukti Ali, yang telah meninggal pada 2004, menulis, “Ada kritik terhadap Lingkaran Diskusi ini dan juga terhadap saya yang mentolerir pembicaraan-pembicaraan yang tidak umum itu. Kritik dilontarkan terutama oleh kawan-kawan yang menganggap masalah-masalah yang didiskusikan itu merupakan soal-soal yang sudah ‘selesai’atau tidak perlu dikutik-kutik lagi.”
Anggota forum Limited Group ini juga menjadi poros utama pemikiran-pemikiran progresif di HMI Jawa Tengah, tempat Ahmad Wahib, Djohan Effendi dan Dawam Rahardjo berorganisasi.
Mukti Ali memaklumi kritik-kritik tersebut sekaligus menganggap kelompok diskusi semacam itu tetap diperlukan untuk mengetahui alam pikiran anak muda. Baginya amat disayangkan bila anak muda – anak muda itu dibiarkan memendam pertanyaan dan gugatan yang justru menyangkut hal-hal dasar dalam agama yang ada dalam pikiran mereka.
“Mereka sedang dalam proses mencari. Dan dalam proses pencarian itu tentu saja pendapat-pendapat mereka masih belum mapan. Justru dalam forum diskusi bisa dilakukan dialog yang terbuka tanpa mereka merasa digurui dan dihakimi.”
Adalah hal yang menarik bagi Mukti untuk mempelajari mengapa anak-anak muda yang dengan latar belakang pendidikan berbeda-beda itu memperlihatkan pikiran-pikiran yang serupa, yakni pikiran yang ‘menyimpang’ dari pendapat umum di masyarakat Islam. Namun ia memandang ‘penyimpangan’ itu dengan nada optimis.
“Saya percaya bagaimanapun ‘anehnya’ pikiran-pikiran mereka, tambahan pengetahuan dan pengalaman akan mematangkan pemikiran mereka.”
Di antara anggota diskusi tersebut ternyata Ahmad Wahib diam-diam merekam pergulatan pemikirannya.
“Cetusan-cetusan dari pergulatan pemikiran itu tampak dan sangat mewarnai catatan hariannya. Karena itu tidak mengherankan apabila banyak hal-hal yang ditulisnya cukup membuat dahi kebanyakan orang berkerut.”
Baginya, buah pikiran-buah pikiran Ahmad Wahib yang ‘cukup membuat dahi kebanyakan orang berkerut’ tersebut tidak mengherankan mengingat latar belakang Wahib. Ahmad Wahib berasal dari Madura yang terkenal sebagai lingkungan agama yang taat di saat yang sama ia adalah mahasiswa eksakta dan kegiatan organisasinya bersentuhan dengan masalah-masalah agama dan kemasyarakatan. Latar belakang itu ia rasa mendorong Wahib untuk banyak merenung.
“Dan dalam renungan-renungan yang ia lakukan itu, almarhum terlibat dalam pergulatan pikiran yang keras.”
Mukti Ali dalam pengantarnya juga menyatakan orang-orang boleh setuju atau menolak pemikiran Ahmad Wahib, tetapi ia berpandangan catatan harian Ahmad Wahib itu cukup mengesankan. “Bahkan mungkin akan merangsang dan menggoda pikiran kita. Paling tidak, bisa memahami pergulatan pikiran seorang anak muda yang sedang mencari.
***
Catatan harian Ahmad Wahib bermula pada 14 September 1962, ia menuliskan pengalamannya tinggal di asrama mahasiswa Katolik yakni Asrama Realino, Yogyakarta. Di Yogyakarta, Wahib juga bergabung dengan Himpunan Mahasiswa Islam (HMI). Organisasi itu mempertemukannya dengan Djohan Effendi kemudian mereka menjadi sahabat dekat.
Menurut Djohan, tak banyak yang Wahib tulis sepanjang tahun 1962-1965. Wahib mulai intens menulis pada 1966. Ia mulai merenungkan permasalahan politik dan agama meski dalam kalimat pendek-pendek 4-5 kalimat atau kadang-kadang agak lebih panjang. Tapi catatan sepanjang 1966-1968 masih terputus-putus, kurang jelas arah dan kaitannya sehingga sulit untuk ditangkap maksudnya, begitu tutur Djohan.
Catatan harian itu kemudian disalin dalam bentuk ketikan oleh Mufti Madjidi, kawan lama Wahib sejak mereka berkegiatan bersama di IPMI Yogkarta, yang sudah terbiasa dengan tulisan tangan Wahib. Hasil ketikannya mencapai 662 halaman.
Catatan sejak 1962-1968 dipotong sehingga hanya menyisakan 300an halaman yang berisi catatan dari 1969-1973. Satu dua tulisan pada akhir 1968 masih disertakan. Kumpulan catatan tersebut lantas diberi judul-judul agar memudahkan pembaca menangkap maksudnya, dan dibagi menjadi empat bab.
Buku catatan harian itu membicarakan aspek kebudayaan, keagamaan dan politik di Indonesia. Buku tersebut dibagi tematis menjadi empat bab: ‘Ikhtiar Menjawab Masalah Keagamaan’, sepanjang 176 halaman yang mengambil porsi terbanyak dari buku ini, ‘Meneropong Politik dan Budaya Tanah Air’ sepanjang 68 halaman, ‘Dari Dunia Kemahasiswaan dan Keilmuwan’ sepanjang 50 halaman, dan ‘Pribadi yang Selalu Gelisah’ sepanjang 33 halaman.
Segera buku yang berasal dari catatan harian tersebut menjadi perdebatan publik saat itu.
M. Rasjidi, mantan Menteri Agama pada era Kabinet Sjahrir, menulis tanggapan. Ia menulis tanggapan setelah percakapan yang terjadi di antara jemaah Masjid Arif Rahman Hakim di Salemba Raya sebelah kantor Rektor Universitas Indonesia saat ia menjadi imam dan khatib salat Jumat. ‘Karena nampaknya para jemaah Masjid Arif Rahman Hakim sangat merasakan akibat dari penerbitan buku tersebut, maka pada waktu itu juga saya meminta sebuah naskah yang kebetulan tersedia.’
Buku catatan harian Ahmad Wahib ia anggap senafas dengan buku Harun Nasution berjudul Islam Dipandang Dari Segala Aspeknya yang ia analogikan sebagai buku ‘telah mengusap wajah Islam dengan debu yang basah, sehingga wajahnya nampak dalam keadaan seburuk-buruknya.‘
Sebelumnya, Rasjidi juga pernah menulis bantahan terhadap Nurcholis Madjid, yang Ahmad Wahib sudah berinteraksi saat di HMI, dan Harun Nasution. Keduanya ia sebut sebagai golongan anti-Islam yang kebarat-baratan dan menyiarkan citra Islam yang memuakkan dengan mengambil pendapat-pendapat orientalis dan orang-orang Barat yang sekuler.
Setelah membaca catatan harian setebal 350 halaman itu, Rasjidi menyimpulkan Wahib sebagai pemuda cerdas yang tidak mendapat bimbingan, atau malah memang didorong untuk melantur dalam kesesatan. Dia juga menuding Ahmad Wahib mencaci pesantren sebagai sarang homoseksualitas tetapi pada waktu yang sama memuji-muji Romo A Romo B yang bersikap ramah kepadanya. Tudingan itu merujuk pada catatan Wahib pada 18 September 1969.
“…Aku Pernah hidup di lingkungan pondok pesantren yang diracuni dengan skandal-skandal homoseksualnya. Aku pernah hidup dengan sekeluarga dengan suatu keluarga abangan yang memelihara anjing. Aku pernah satu rumah dengan keluarga Katolik yang cukup fanatik. Aku pernah mempunyai teman seorang komunis yang paling rapat bergaul denganku di sekolah menengah (sekarang ia meringkuk di tahanan golongan A).
Aku pernah mengaji, mohon-mohon berkat di kuburan keramat sebelum aku sadar seperti sekarang. Aku pernah masuk di gang-gang pelacuran dengan bulu kudukku berdiri. Aku pernah mengaggumi bagaimana penjual-penjual jamu di alun-alun Yogya berbohong. Setiap arena itu mengaruniai aku ide-ide baru yang tidak kumiliki sebelumnya…”
Rasjidi menerbitkan tanggapannya di Majalah Kiblat. Meski menuliskan tanggapan, Rasjidi mendaku tidak untuk membantah isi buku pemikiran Wahib yang adalah seorang anak muda yang belum pernah ia dengar karyanya sebelumnya. Ahmad Wahib adalah anak muda yang ‘semestinya dipimpin dan tidak dibiarkan dalam kesesatannya.’Karena itu ia menyangsikan apa yang dikerjakan oleh Limited Group yang dibina oleh Mukti Ali.
“Apa yang dikerjakan oleh Limited Group yang berdialog tanpa bahan dan alat.”
Buku catatan harian Ahmad Wahib, yang disunting oleh dua kawannya, dan diberi kata pengantar oleh Mukti Ali yang notabene adalah mantan Menteri Agama, bagi Rasjidi tak lebih dari tragedi belaka.
***
Wahib lahir pada 9 November 1942 di Sampang, Madura. Ayah Wahib, Sulaiman, seorang pemimpin pesantren dan dikenal luas oleh masyarakat sekitar. Namun, ayahnya jua agamawan yang berpikiran terbuka. Sulaiman orang pertama di lingkungannya yang mengawinkan anak perempuan tanpa tetek bengek adat. Sulaiman mendalami pemikiran-pemikiran Muhamad Abduh.
“Ayahku adalah seorang pemberontak pada zamannya. Di masa mudanya dia telah mengeritik beberapa kitab-kitab agama yang dinilainya tidak sesuai dengan Al-Quran dan hadist.”
“Ayahku merupakan tokoh santri pertama di Sampang yang menyekolahkan anak puterinya ke sekolah umum. Dan beliaulah tokoh santri pertama di Sampang yang mengawinkan anaknya sekadar seperti yang diwajibkan agama, suatu hal yang saya sendiri masih mempersoalkannya, tetapi merupakan keberanian Ayah untuk membikin alternatif lain pada lingkungannya.”
Alih-alih mengirimkan Wahib ke pesantren, Sulaiman juga menyekolahkan anaknya ke sekolah umum. Setamat sekolah atas, Sulaiman pun mengizinkan Wahib mengambil jurusan sains di bangku kuliah.
Wahib lulus dari sekolah atas di Pamekasan, Madura pada 1961 lalu melanjutkan pendidikannya ke Fakultas Ilmu Pasti dan Alam (FIPA) Universitas Gajah Mada. Tahun permulaan di Yogyakarta ia tinggal di asrama mahasiswa Katolik, Asrama Realino. Kesempatan itu membuatnya berinteraksi dekat dengan komunitas Jesuit setempat. Ia tinggal di asrama tersebut hingga 1964.
Di Yogyakarta, ia bergabung dengan HMI. Organisasi tersebut mempertemukannya dengan Djohan Effendi. Djohan, yang lebih tua dari Wahib kembali belajar di Yogyakarta apda 1963 setelah sebelumnya lulus dari Pendidikan Hakim Islam Negeri (PHIN) Yogyakarta dan kembali ke Kalimantan pasca tamat dari PHIN. Dengan lekas mereka menjadi sahabat dekat hingga mereka hijrah ke Jakarta nanti.
Di HMI tampaklah darah Sulaiman yang menurun pada Wahib. Keaktifan dan pemikiran membuat Wahib masuk ke jajaran tertinggi para pemimpin HMI Jawa Tengah dengan cepat. Dan, meski di lingkungan elit HMI tersebut ia masih tergolong pendatang baru, darah Sulaiman membuatnya tidak takut bersikap berbeda. Ia malah berani mengkritik pimpinan-pimpinan HMI yang dianggap salah. Salah satu sikap ini yang membuat Wahib dan Djohan menjadi kolega yang kompak.
Wahib tumbuh menjadi anak muda dengan rasa ingin tahu yang besar. Opini orang-orang tanpa melihat usia dan reputasi ia dengarkan dengan senang hati. Itu membawanya pada pergaulan yang luas. Djohan menyebutkan para tetua yang kerap Wahib kunjungi dan menjadi akrab.
“A.R. Baswedan seorang tokoh eks Masyumi, Ki Muhammad Tauchi seorang tokoh Taman Siswa, Samhudi seorang anggota AHmadiyah Lahore yang mempunyai pandangan keagamaan agak unik, Karkono bekas anggota Konstituante dari PNI yang akhirnya keluar dari PNI.”
Pasangan Wahib dan Djohan kerap mengunjungi mereka bersama-sama. Ada kesamaan ciri yang membuat Wahib dan Djohan menjadikan orang-orang itu sebagai rekan atau kolega berdiskusi: keberanian untuk bersikap dan berbeda. Dalam diri A.R. Baswedan ada Darah pemberontak yang menarik hati mereka. Baswedan mendirikan Partai Arab Indonesia pada tahun 1930-an, langkah Baswedan tersebut mendapatkan cemooh dan tantangan dari kalangan Arab sendiri kala itu.
Samhudi, dari Ahmadiyah Lahore yang pilihan keyakinannya dianggap banyak orang menyimpang, dan itu membuat banyak anak muda dan para petinggi HMI kala itu untuk menghindari persahabatan dengannya, tak membuat Wahib dan Djohan mengindar demi reputasi. Alih-alih, mereka jadikan Samhudi tempat berdiskusi untuk mendapatkan pencerahan dari siapapun asalnya.
Juga Wajiz Anwar, dosen IAIN Sunan Kalijaga saat itu. Selesai dari Gontor, Wajiz melanjutkan pendidkan ke Mesir, merasa tak puas ia pergi ke Jerman untuk mempelajari filsafat. Pendapat-pendapat yang dikeluarkan Wajiz kerap menggoda dan memprovokasi pikiran mereka. Kelak, saat hijrah ke Jakarta dan tak menyelesaikan studinya di Yogja, Wahib mengikuti kuliah-kuliah filsafat di STF Driyakara.
Di HMI sendiri, keberanian mereka dalam bersikap dan mengkritik tak disenangi. Sekitar tahun 1967, mulai terjadi serangan-serangan dalam tubuh HMI terhadap Wahib dan Djohan. Mereka kian mengeras dan serangan kian agresif. Akhir tahun 1969 mereka keluar dari HMI. Pada 1971, Wahib pindah ke Jakarta.
***
Abdurrahmad Wahid, meski tak bertemu Ahmad Wahib, mengaggumi buku catatan harian Wahib yang terbit. Ada ketulusan dan keberanian yang tercermin dari catatan-catatan itu.
“Ketulusan untuk memperoleh kebenaran dengan pertaruhan tertinggi. Keberanian menghadapkan diri sendiri kepada masalah-masalah keimanan terdalam.”
Keberanian menghadapi diri sendiri atas masalah-masalah keimanan terdalam itu ia maknai sebagai pengakuan penuh Wahib atas keraguan mendasar yang ada dalam hati. Ia menangkap kemampuan Wahib untuk belajar dari siapa saja.
“Semua itu adalah hal-hal yang saling bertentangan tetapi berkembang dalam hidup Wahib.”
Yang juga mengesankan dari buku Wahib adalah, “Kenyataan akan tingginya intensitas pergulatan pemikiran dalam diri Ahmad Wahib.”
Namun, Abdurrahmad menyayangkan pengantar yang diberi oleh Mukti Ali dan pendahuluan oleh Djohan Effendi di buku tersebut. Mereka dianggap gagal menjelaskan ‘aspek-aspek detil pergulatan’ yang kepada orang lain yang tak mengenal Wahib. Seharusnya, Mukti yang ia anggap sebagai mantan pembimbing intelektual-keagamaan dan Djohan karib terdekat Wahib, menjelaskan sisi-sisi tidak terlihat itu. Karena jika membaca buku catatannya saja suilt bagi pembaca untuk mendapatkan gambaran yang utuh akan Wahib.
“Bagi pembaca yang tidak mengenalnya secara pribadi sulit mendapatkan gambaran yang utuh mengenai diri Ahmad Wahib hanya dari bukunya ini.”
Pembaca tidak bisa mengetahui dari mana pergulatan pemikiran itu bermula, apa saja hal-hal yang terjadi dalam hidup Wahib yang membentuk wataknya, juga “Sejauh mana pemikir muda ini disengsarakan kejujuran yang mutlak itu?”
Tanggapan itu Abdurrahman tulis di Tempo yang terbit September 1981.
“Kita tahu dia harus bergulat, tetapi apa lingkup pergulatannya, kesakitannya sewaktu menjalani proses tersebut, harapannya yang dirumuskan sebagai ujung pergulatan?”
Situasi yang tidak dijelaskan oleh orang-orang terdekatnya tersebut membuat pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran utuh diri Ahmad Wahib.
Namun ia tetap bisa merasakan arti pergulatan tersebut bagi Ahmad Wahib, rekan-rekannya, atau bahkan mungkin bagi perkembangan Islam. Ia menangkap kuatnya dorongan Ahmad Wahib untuk terlibat dalam masa depan agama yang Wahib cintai dengan sangat. Keresahan, kritik dan pertanyaan Wahib akan agamanya ia tangkap sebagai bentuk cinta.
“Pemberontakan yang dilakukannya justru bertujuan mengukuhkan agamanya yang diyakininya itu.”
“Kalau ia dapati kekurangan sedemikian mendasar di dalamnya, mengapa Ahmad Wahib tidak menolaknya? Bahkan sebaliknya, ia lebih dalam mencintainya — bagaikan orang mencintai pelacur walaupun tahu apa yang dikerjakan pelacur itu sehari-hari.”
Greg Barton, Indonesianis yang meneliti mengenai Islam di Indonesia, di dalam disertasinya memasukkan Ahmad Wahib, bersama-sama dengan Abdurrahman Wahib, Djohan Effendi dan Nurcholis Madjid, ke dalam cendikia yang memberikan sumbangsih pada gerakan pembaharuan pemikiran Islam yang sering dirujuk sebagai Neo-Modernisme Islam.
“Seperti Modernisme, Neo-Modernisme secara dasariah merupakan tanggapan dalam pemikirann Islam terhadap tekanan, tantangan serta peluang-peluang modernitas.”
Bagi Barton, intelektual Muslim Indonesia pada umunnya lebih terbuka dna jujur dalam menghadapi tantangan modernitas, dibanding kelompok-kelompok Muslim di wilayah lain. Itu terbukti dari cepatnya pemikir Muslim Indonesia merespons tantangan-tantangan Modernitas.
Barton menyepakati pandangan Djohan yang ditulis dalam pendahuluan buku catatan harian Ahmad Wahib, bahwa WAHib adalah tokoh “di balik layar” yang vital dan berpengaruh dalam perkembangan Neo-Modernisme.
“Kita tidak bisa mengabaikan kenyataan bahwa perspektif yang ditawarkan Ahmad Wahib bukan saja untuk kehidupannya sendiri tapi juga untuk Djohan Effendi.”
Penulis: Fatimah Zahrah, Jurnalis Lepas. Alumni Fakultas Falsafah dan Peradaban Universitas Paramadina.
*Tulisan ini tayang pertama kali di sini atas kerjasama beritagar.id dan islami.co

