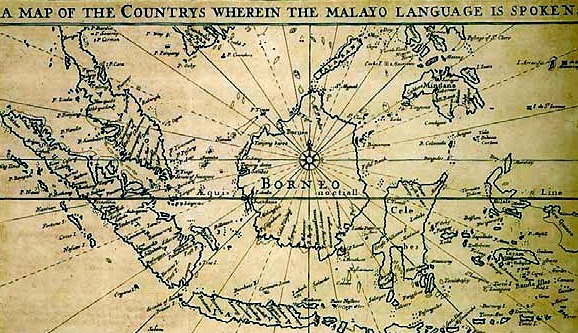
Nusantara bukan hanya kolam susu, di mana tongkat kayu dan batu jadi tanaman sebagaimana kata Koes Plus, tapi juga tempat tumbuh suburnya kearifan dan nilai-nilai luhur kemanusiaan universal. Ambil contoh di Jawa saja misalnya, melalui salah satu ungkapan, “Sopo weruh ing panuju, sasat sugih pager wesi” (siapa yang tahu tujuan hidupnya, maka secara otomatis seakan-akan ia telah menjadi orang kaya dan terlindungi keamanan dirinya) bisa diuraikan sebagaimana berikut.
Raden Mas Panji Sosrokartono, kakak kandung Raden Ajeng Kartini yang kita peringati setiap tanggal 21 April, membabar ungkapan di atas dengan catur paradoks. Sebenarnya istilah catur paradoks ini kurang tepat, dan saya menduga bukan “orang jawa” yang mengistilahkannya. Karena catur pepeling (istilah ini menurut saya lebih tepat, yang berarti empat anjuran) dari RMP Sosrokartono ini sesungguhnya adalah satu kesatuan terkait dengan laku “Sopo weruh ing panuju, sasat sugih pager wesi” tersebut. Tetapi karena istilah catur paradoks sepertinya juga dapat membantu orang yang “bukan jawa” memahami substansinya, maka tidak ada salahnya jika kita memakainya demi kebutuhan termaksud.
Catur Paradoks
Pepeling pertama, “Sugih tanpa banda” (kaya namun tidak bergantung pada harta benda) berjalinan erat dengan pepeling kedua, “Nglurug tanpa bala” (menyambangi musuh tanpa bantuan orang lain), adalah penjelasan dari laku sasat sugih.
Artinya, orang yang sudah tahu dan menyadari sepenuhnya tujuan hidup (weruh ing panuju) dengan sendirinya ia akan menjadi pribadi yang kaya. Dan itu terefleksikan oleh laku dalam menjalani hidup yang tidak bergantung kepada siapa pun selain dirinya sendiri dan Tuhan yang menjadi tujuan hidupnya. Jika harus berkompetisi, bahkan berperang sekalipun, ia tidak akan pernah membutuhkan bantuan orang lain, karena bantuan dari Tuhan yang menjadi tujuan hidup telah mencukupinya. Meskipun wujud bantuan Tuhan ini juga bisa berupa orang-orang yang sangat loyal kepadanya, misalnya.
Pepeling ketiga, “Digdaya tanpa aji” (sakti mandraguna tanpa bergantung pada senjata) berjalin kelindan dengan pepeling keempat, “Menang tanpa ngasorake” (menang tetapi tidak sampai merendahkan yang dikalahkan), merupakan penjabaran laku sasat pager wesi.
Artinya, orang yang sudah tahu dan menyadari sepenuhnya tujuan hidup (weruh ing panuju) dengan sendirinya juga akan menjadi pribadi yang terlindungi keamanannya. Dan itu terefleksikan oleh laku dalam menjalani hidup yang tidak pernah berlaku sombong namun sekaligus juga tidak sempat rendah diri, karena ia telah berakhlak dengan akhlak Tuhan yang Maha Rahman (takhalluq bikhuluqirrahmaan).
Jika harus berkompetisi, bahkan berperang sekalipun, ia tidak akan pernah merasa terancam dan tidak pula berlaku sewenang-wenang, karena menyadari sepenuhnya bahwa dirinya hanyalah perpanjangan dari tangan Tuhan yang Maha Rahman.
Dan, catur pepeling dari RMP Sosrokartono di atas sesungguhnya juga merupakan warisan dari para leluhur manusia nusantara pada umumnya, termasuk Jawa yang bertumpu pada keseimbangan dengan memantang pantangan ma lima dan menjalankan laku wa lima, misalnya.
Pantangan Wa Lima dan Laku Wa Lima
Pantangan ma lima yang sangat terkenal dalam masyarakat Jawa, khususnya di pedesaan hingga hari ini, adalah “Ojo maling, madat, madon, marung, main” (jangan mencuri, narkoba, berzina, hura-hura, berjudi).
Ojo maling, artinya kita tidak diperkenankan memanfaatkan apalagi memiliki sesuatu yang kita tidak punya hak atasnya. Ojo madat, artinya kita tidak boleh menjadikan narkoba menjadi pelarian karena tak memiliki kesanggupan berkompetisi dalam hidup. Ojo madon, artinya kita dilarang berzina. Ojo marung secara harfiah artinya janganlah makan di warung, merupakan himbauan agar kita tidak konsumtif apalagi berhura-hura. Ojo main, artinya agar kita menghindari segala bentuk perjudian dalam hidup.
Selanjutnya, bagaimana supaya kelima pantangan di atas bisa diindahkan tanpa keterpaksaan, leluhur manusia nusantara di Jawa juga menyeimbangkannya dengan warisan runutan laku wa lima. Yaitu wani, wedi, wingit, wisik, wicak (berani, takut, hati-hati, waskita, bijaksana).
Pertama-tama, kita semua ditekankan agar memiliki sikap wani, yaitu berani dalam melakukan dan menghadapi apa pun. Toh pada titik tertentu, dengan sendirinya kita juga akan mengalami wedi, alias takut sebagai akibat dari keberanian yang berlebih. Misalnya karena terlalu berani dalam mengendarai kendaraan bermotor lalu ngebut dan mengalami kecelakaan, maka setelah sembuh kemungkinan besar akan tumbuh rasa takut di dalam dirinya untuk kebut-kebutan lagi dalam berkendara.
Setelah mengalami wani dan wedi sebagaimana dicontohkan di atas, maka atas dasar pengalamannya tersebut, orang pun berlaku wingit. Wingit secara harfiah dapat diartikan sedih, namun terkait dengan wa lima ini penekanan maknanya adalah hati-hati atau waspada.
Setelah orang waspada dalam bertindak, maka ia pun akan wisik. Wisik secara harfiah dapat berarti menerima ilham atau mendapat bisikan halus dari semesta. Karena itu orang yang wisik ini pun kemudian tumbuh sebagai pribadi yang waskita, yaitu pribadi yang memiliki ketajaman pandangan terhadap pelbagai hal dan peristiwa.
Puncak dari seluruh laku wa lima adalah wicak, alias bijaksana. Nah, ketika seseorang telah menjadi bijaksana, maka di dalam memandang dan menyikapi hidup tentunya tak hanya hitam putih. Dengan demikian, ketika harus berkompetisi ataupun berperang bahkan, jika pun menang maka ia tak akan pernah merendahkan yang telah dikalahkannya. Begitu pula saat menjadi mayoritas dan berkuasa, orang yang bijaksana tentu akan senantiasa berlaku mengayomi dan melindungi yang minoritas, sehingga tak mungkin berlaku sebagai tiran. Wallahu a’lam bishshawwab. []
Muhaji Fikriono adalah penulis buku Hikam untuk Semua dan Puncak Makrifat Jawa. Bisa ditemui di @Hikam_Athai

