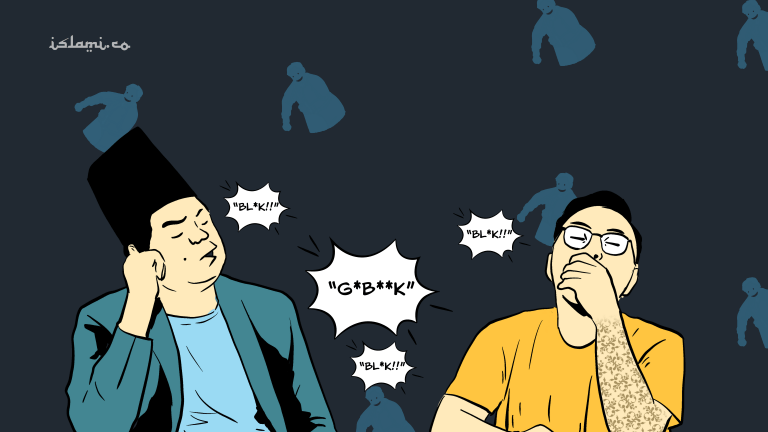
Saya tidak menyesal tidak memilih 02, walaupun saya juga tidak kehilangan harapan jika harus menghadapi kenyataan Prabowo-Gibran jadi penguasa. Sebagai fakta politik ia memang harus diterima, tetapi juga perlu dikaji ulang dalam kapastitas realitas sosial.
Prabowo Subianto, betapapun, bukanlah orang biasa. Pengalaman dan relasi kekuasaannya dengan orde militeristik Soeharto menunjukkan bahwa ia memang orang terpilih.
Juga, statusnya sebagai Menteri Pertahanan di era Presiden Jokowi. Prabowo rupanya bukan saja memendam skill administratif di bidang pertahanan, tetapi sekaligus menyingsingkan ufuk keajaiban. Buktinya, dirinya bisa bertahan sejauh ini.
Sekali nyawapres dan tiga kali nyapres menegaskan betapa tebalnya imunitas Prabowo hingga dipuja oleh sebagian (walaupun besar) pengguna Tiktok, disponsori elite penguasa, didukung agamawan istana, dibopong Ormas, dibaiat oleh aktivis yang masih hidup yang dulu sempat ia culik, dan akhirnya berada di puncak kekuasaan bersama putra sulung penguasa sebelumnya, Gibran Rakabuming Raka.
Gibran sendiri sebetulnya juga merupakan orang pilihan. Tidak semua anak Indonesia bisa serakabuming Gibran. Hidupnya penuh dengan akselerasi dan privilege, sedemikian berlimpahnya hingga orang mengira bahwa sistem demokrasi Indonesia kini telah berganti dinasti. Maka ketika ia mengatakan “saya tiga bulan lalu bukan siapa-siapa,” itu sepenuhnya salah besar.
Gibran adalah anak sulung Presiden Jokowi. Adiknya Gibran adalah Ketua Umum PSI (yang dipilih secara aklamasi setelah dua hari sebelumnya menjadi anggota partai). Iparnya Gibran adalah Walikota Medan. Pamannya Gibran adalah petinggi Mahkamah Konstitusi (MK) yang kini sedang memperjuangkan haknya untuk kembali menjadi ketua setelah dipaksa mundur karena mematahkan palu MK.
Dengan modal sosial dan simbolik sebegitu loh jinawi (yang pada gilirannya bisa dikonversi menjadi modal ekonomi), Gibran tentu saja potensial menjadi pewaris tahta bapaknya. Pengaruh Presiden Jokowi terlalu absolut untuk gerakan sosial dan akademik yang mencoba kritis terhadap institusi kekuasaan. Ketika warga sipil melakukan unjuk rasa, mereka rentan dianggap tidak tahu apa-apa tentang ikhtiar Presiden memperbaiki kehidupan bangsa.
Sekarang petanya menjadi semakin jelas. Prabowo dan Gibran akan menjadi penguasa. Keduanya bakal menentukan arah negara Indonesia, setahun, dua tahun, tiga tahun, empat tahun, atau lima tahun ke depan.
Jika membaca visi-misi dan menyimak jejak kampanye mereka berdua, prioritas Prabowo-Gibran memang mudah dicerna publik. Selain meneruskan program strategis Presiden Jokowi, makan siang dan susu gratis adalah program unggulan terpenting bagi penguasa selanjutnya.
Bahkan saking pentingnya, makan siang gratis menjadi syarat utama seleksi menteri-menteri Prabowo, mengalahkan masalah-masalah struktural lainnya yang berada di menara gading bagi warga negara kelas (di)miskin(kan).
Di titik ini agaknya pikiran yang menyimpul Jokowi mewariskan politik dinasti itu telah melupakan satu hal krusial: bahwa dalam kultur dinasti, relasi biologis bukanlah jaminan kebahagiaan, bukan juga kunci keberlangsungan sebuah keluarga. Apalagi jika menyangkut kekuasaan politik. Anak sama bapak bisa bunuh-bunuhan. Dengan saudara ipar bahkan bisa saling berkhianat dan saling tusuk.
Melihat betapa solidnya keluarga Presiden Jokowi, hal itu tentu masih jauh untuk terjadi. Kalau tidak solid, mana mungkin majalah sekelas Tempo bisa mengakses informasi valid keluarga inti Jokowi hingga membeberkannya kepada publik terkait konflik domestik.
Paling mentok suatu saat, ntah dari mulut atau jempol siapa, hal yang mungkin terjadi adalah kata-kata setamsil, “Pak Prabowo itu ya, kalau gak ada Pak Jokowi, kasian deh..”
Apa yang bisa diambil?
Saya teringat seorang teman yang kini sedang studi di Belanda. Katanya, rumus kebahagiaan di tengah dinamika sosial itu sederhana, yaitu ambil lucunya atau ambil hikmahnya. Bisa juga ambil dua-duanya.
Lucunya, komika Coki Pardede mengaku memilih Prabowo-Gibran karena panggilan hati nurani. Demikian halnya dengan Tretan Muslim.
Seorang kawan lain yang menjadi salah satu bagian tim digital (berbayar) profesional untuk 02 suatu hari menjelang libur Natal 2023 bilang kepada saya, begini:
“Aku beneran salut sama Bang Tretan. Dia kemarin pas di IKN ngomong kalau ngedukung Pak Prabowo tanpa dibayar.”
Lepas dari kepolosan kawan saya (radhiyallahu anhu), dua hal itu bagi saya adalah puncak kelucuan, selain fenomena artis-artis arus utama lainnya yang berada di barisan serupa, dengan imam besar smart people Deddy Corbuzier.
Berdasarkan realitas digital itu, tidak sedikit saya mendapat himbauan “mendukung itu yang jelas-jelas menang aja.” Dalam hati rasanya saya ingin bilang, “kalau udah jelas menang ngapain didukung? Emangnya para selebriti itu sedang kerja budaya?”
Seleb itu wilayahnya adalah panggung hiburan. Peran utama mereka di sektor industri kreatif ya menghibur orang. Kalau mengajar itu namanya dosen atau guru.
Oiya, tentu saja, tidak semua artis itu menjadikan hiburan sebagai tujuan utama. Banyak juga yang menggunakan hiburan sebagai gimmick belaka. Tujuan utama mereka tetap berada pada bagaimana mengedukasi publik dan mencerdaskan kehidupan bangsa yang semestinya jadi tugas negara.
Tapi Pilpres 2024 ini betul-betul menunjukkan betapa budaya akademik bisa runtuh digempur budaya tontonan dengan selebriti sebagai agent of power. Referensi orang bukan lagi berdasar pada kemampuan berpikir dan menelaah informasi secara mandiri, tetapi rezim algoritma media digital yang performativitasnya setara kitab suci.
Kelucuan selanjutnya atau puncaknya paling puncak adalah pendukung Prabowo di platform Tiktok mengira kalau Aksi Kamisan di seberang istana merdeka baru terselenggara tidak lebih lama daripada durasi antara status keanggotaan sampai pelantikan Kaesang Pangarep sebagai Ketum PSI. Masih butuh penjelasan?
"Pengguna X mengira seluruh penduduk Indonesia ada di X."
"Dirty Vote ramai di X, echo chamber. Dan gak berdampak di TikTok, grassroots."
Sejak 2009 di Twitter, komentar seperti ini hanya di TikTok.
— Rumail Abbas (@Stakof) February 15, 2024
Keyakinan awam saya lalu membisik, setidaknya, lima tahun mendatang akan lahir pemikir-pemikir dan penulis muda yang kritis, bernas, walaupun tangguh.
Arus diskursif menjadi lebih hidup. Forum diskusi tampak lebih gemah-ripah dengan berbagai setrategi kucing-kucingannya.
Hegemoni Tiktok sebagai rezim search engine pada gilirannya akan runtuh. Aksi-aksi turun ke jalan pun semakin masif, baik yang kontra status quo, maupun tandingannya. Ini paling tidak yang bisa menjadi hikmahnya.



