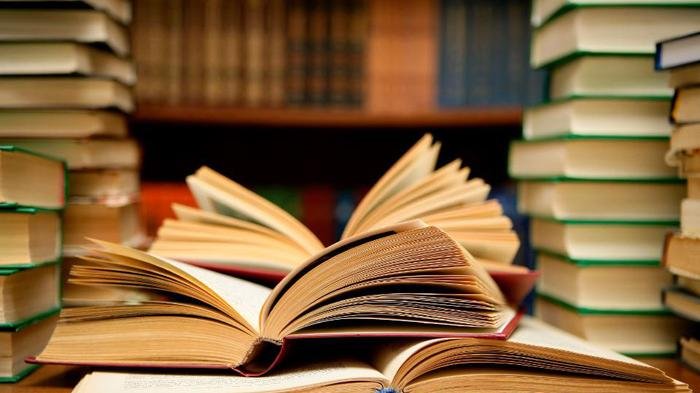
Kemarin (27/7), kekeliruan atas penjelasan soal Trinitas dalam buku pelajaran sempat viral di beberapa platform media sosial. Dalam buku tersebut dijelaskan bahwa mengenai agama Kristen Protestan dan Katolik, yakni “Tuhannya adalah Allah, Bunda Maria, dan Yesus Kristus sebagai tiga yang tunggal atau Trinitas”.
Konten galat tersebut ditemukan dalam buku Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan SMP kelas VII, dan beredar luas sehingga memancing komentar keras, bahkan ada desakan untuk menarik seluruh buku yang sempat beredar tersebut. Akhirnya, Kemendikbud memberikan klarifikasi dan menarik kembali buku tersebut, sekaligus berjanji melibatkan para pihak yang lebih kompeten, agar penjelasan terkait ajaran agama tersebut lebih komprehensif.
Klarifikasi dari Kemendikbud terbilang diplomatis. Sebab, Kemendikbud tidak menjelaskan bagaimana kekeliruan tersebut bisa terjadi. Hal ini dirasa perlu, karena kita harus mendapatkan penjelasan bagaimana kesalahan tersebut bisa terjadi, lebih dari sekedar pengakuan kesalahan dan penarikan buku.
Secara umum, sebenarnya kesalahan ini tidak dapat ditoleransi sebagai human error. Karena, Negara, dalam hal ini Kemendikbud, seharusnya tidak melakukan blunder atas informasi galat terhadap ajaran agama “resmi” di Indonesia. Kemendikbud semestinya berkolaborasi dengan otoritas semua agama untuk memastikan defenisi yang dimuat sudah sesuai dengan ajaran yang berlaku.
Sebagai pemeluk agama non-Kristen dan Katolik, mungkin cacat produksi dalam buku pelajaran tersebut juga memperlihatkan sesuatu yang penting, yakni pengetahuan terhadap ajaran agama lain masih terdapat kekeliruan. Kondisi tentu seharusnya menjadi perhatian kita, sebab prasangka hingga kebencian yang muncul dari pemahaman kita yang keliru terhadap ajaran agama liyan.
Bertanya Melampaui Prasangka
Salah satu organisasi anak muda yang berbasis di Yogyakarta memiliki program keren. Salah satu kegiatan reguler mereka adalah perjumpaan anak-anak muda yang berbeda agama secara rutin. Menariknya, di dalam aktivitas tersebut mereka diminta untuk prasangka atau bertanya tentang ajaran agama selain yang mereka peluk.
Pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh anak-anak muda tersebut tidak saja mendalam, kritis, bahkan sebagian juga menggelitik. Mereka diminta untuk berani dan terbuka atas sekian prasangka, stigma, bahkan kebencian yang selama ini mengendap dan meracuni pikiran mereka hingga hari ini.
Sekilas mungkin bertanya adalah hal yang mudah untuk dilakukan oleh siapa saja. Tapi, jika pertanyaan terkait agama selain yang kita peluk tentu tidak semudah yang dibayangkan. Ada banyak hal yang saling berkelindan dan kompleks dalam benak kita untuk mengutarakan pertanyaan tersebut, mulai dari malu, tabu, ketakutan, hingga kebencian.
Jelas, semua itu bukan hal yang mudah untuk dilampaui untuk bertanya sesuatu yang selama ini ada dalam imaji dan benak kita, terlebih menyangkut agama orang lain. Namun, anak-anak muda di atas bisa menjadi pelajaran bagi kita yang selama ini (mungkin) tidak pernah dilakukan.
Bahkan, lewat pertanyaan yang berani, mendalam, dan kritis tersebut, para anak muda itu belajar sesuatu hal yang selama ini terselubungi dengan prasangka, ketabuan, hingga kebencian. Belajar dari ajaran agama lain seharusnya menjadi awal untuk membangun relasi yang setara, sebab kita tidak akan mudah terhasut dengan informasi sesat.
Kemendikbud sudah seharusnya ditegur keras akibat kegalatan dalam buku tersebut. Sebab, Informasi soal agama tertentu yang dapat dipertanggungjawabkan dalam buku pelajaran, sudah seharusnya merupakan tugas dan mendapat jaminan dari Negara, dalam hal ini adalah Kemendikbud dan instansi lainnya yang menyelenggarakan pendidikan.
Kekeliruan kemarin tentu saja dapat menyesatkan para murid di sekolah, dan bisa saja tidak pernah mendapatkan klarifikasi setelahnya. Oleh sebab itu, untuk menghindari kesalahan tersebut terjadi kembali, ada baiknya para stakeholder berani untuk “bertanya” sebagaimana yang telah dicontohkan para anak muda di atas.
Internet dan Persoalan “Resmi”
Persoalan kekeliruan kemarin juga memperlihatkan para penyusun buku sepertinya belum memiliki kompetensi yang cukup, terutama dalam mengolah informasi. Kemendikbud sudah seharusnya lebih ketat dalam memproduksi pengetahuan yang nantinya akan dikonsumsi oleh para peserta didik.
Kompetensi para penyusun buku pelajaran mungkin perlu diperhatikan kembali oleh Kemendikbud, selaku operator pendidikan di Indonesia. Sebab, jika kita berkaca pada dinamika bagaimana pengetahuan agama di masa awal kehadiran internet di masyarakat muslim maka kita bisa belajar bahwa persoalan ajaran agama adalah titik kritis dalam relasi masyarakat.
Dalam artikel Jon W. Anderson berjudul New Media in the Muslim World: the Emerging Public Sphere, menjelaskan bahwa sejarah awal kehadiran internet di masyarakat muslim adalah menghadirkan ajaran-ajaran di dalamnya. Menariknya, setelah pendedahan ajaran di berbagai website yang diolah para muslim di tanah Eropa, yang kebanyakan adalah para akademisi atau pekerja eksekutif di sana.
Keperluan mereka dalam mendedahkan ajaran agama di internet demi mempermudah berbagi pengetahuan dan informasi, terutama soal ibadah dan berbagai ajaran agama lainnya. Menariknya, informasi yang didedahkan semakin banyak dan berasal dari beragam asal usul, sehingga tidak jarang terjadi gesekan dan perebutan siapa yang “lebih benar”.
Konflik tersebut yang disebut oleh Anderson sebagai Officializing strategies, yang merujuk pada teori Michel Foucault, filsuf asal Perancis, menjelaskan bagaimana perebutan label sebagai “Yang Resmi” untuk menjadi rujukan umat Islam. Uniknya, perebutan tersebut dimulai dari usaha mendedahkan ajaran agama, yang diawaki oleh orang yang tidak memiliki kapabilitas dan kecakapan ilmu keagamaan yang cukup, dan hanya berujung konflik belaka.
Jangan sampai kawan-kawan para peserta didik yang sedang mengecap bangku pendidikan harus dijejali mis-informasi yang fatal terkait agama lain. Informasi yang salah dapat menjebak mereka pada kesalahan dalam memahami relasi mereka dengan pemeluk agama lain, sebagaimana konflik yang digambarkan Anderson di atas, yang menunjuk ketidakcakapan dalam mendedahkan informasi agama dapat berujung konflik.
Dalam kasus buku pelajaran kemarin, para penyusun sudah sewajarnya untuk bertanya kepada otoritas agama, terlebih terkait ajaran yang memang tidak dikuasai. Hal ini demi mengurangi potensi konflik dan dapat dipertanggungjawabkan keabsahan informasi yang dicerap oleh para peserta didik.
“Tanyakan sesuatu pada ahlinya” begitu Islam mengajarkan pada umatnya.
Fatahallahu alaina futuh al-arifin



