
‘Mama, I don’t wanna die, but sometimes I wish I’d never been born at all’ pekik Freddie Mercury sang vokalis Queen dalam ‘Bohemian Rhapsody’ (1975).
Lagu legendaris ini agaknya dapat dianggap sebagai representasi suatu gagasan atau sikap moral yang memudian disebut sebagai ‘anti-natalisme’ – pandangan bahwa kelahiran dan berketurunan merupakan hal buruk. Meski terma ‘anti-natalis’ baru ditemukan tahun 2006 namun ide/prinsip serupa telah dianut manusia sejak ribuan tahun.
Pada awalnya, anti-natalisme muncul sebagai prinsip religius yang menganggap kehidupan dunia dan nafsu yang berkaitan dengan naluri bertahan hidup sebagai pangkal penderitaan dan kejahatan.
Pada masa modern ia lebih berkaitan dengan suatu kesadaran biopolitik/etis akan pengendalian populasi, juga pembalikan nilai-nilai kekeluargaan sebagai dampak sekularisasi dan individualisasi.
Akar-akar religius
Meski dalan praktik asketisme agama-agama besar selalu ada kecenderungan untuk berselibat alias tidak melakukan aktivitas seksual samasekali, namun pada sejumlah tradisi prokreasi sungguh dianggap jahat.
Salah satu aliran yang paling terkenal adalah Katarisme (Catharism), sempalan Kristen Abad Pertengahan yg berkembang pesat di Prancis selatan dan Italia sekitar abad ke-12 hingga abad-13, dan telah menjadi target pembasmian brutal oleh pasukan salib.
Menurut kepercayaan Katar – yang bersifat gnostik-dualis – Tuhan sejati tidak menciptakan dunia fana; Dalam kodrat spiritualnya, manusia adalah percikan ilahi, namun terpenjara dalam tubuh fana yang tercipta dari kuasa kegelapan, dan karenanya ia harus menjalani penyucian diri secara ketat dengan tidak menikah, berketurunan, ataupun makan daging.
Beberapa pengikut Katar konon menjalani ritual berpuasa hingga mati (‘endura’) hingga banyak kalangan Kristen memandang sekte ini berbahaya bagi masyarakat Eropa saat itu.
Dalam beberapa segi, antinatalisme berkaitan erat dengan ide atau ajaran reinkarnasi – di mana ‘penderitaan’ manusia identik dengan siklus kelahiran kembali tanpa akhir.
Selain aliran Katar, sumber religius paling penting bagi pemikiran anti-natalis adalah agama-agama oriental khususnya Buddhisme yamg memiliki pengaruh terbesar di Asia Timur. Namun berbeda dengan (proto) antinatalis yang berkembang di Eropa pra-modern, ajaran Buddha lebih menekankan pada penolakan kelahiran kembali (di masa depan) daripada negasi terhadap kehidupan (masa sekarang) itu sendiri.
Dalam hal ini ia tidak sepenuhnya dapat dikatakan antinatalis mengingat kaum Buddhis meyakini bahwa nirvana dapat dicapai di dunia – melalui jalan asketisme dan praktik religius tertentu – serta ketika manusia melepas semua kemelekatan dan kehendak.
Anti-natalisme modern
Kemunculan anti-natalisme modern berkaitan dengan setidaknya dua sumber;
Pertama, sains dan wacana biopolitik seperti kontrol populasi dan perkawinan selektif (eugenika).
Kedua, pemikiran filosofis umumnya berkaitan dengan nihilisme, yang sedikit banyak juga dipengaruhi agama dan filsafat kuno.
Tulisan ini tidak akan membahas poin pertama yang sudah didiskusikan di beberapa tulisan saya sebelumnya, melainkan lebih pada akar-akar filosofisnya.
Salah satu tokoh yang paling sering dijadikan rujukan dalam membahas gagasan anti-natalis adalah filsuf Jerman Arthur Schopenhauer (1788-1860) yg mendapat pengaruh kuat dari filosofi ketimuran khususnya India (Hindu-Buddha).
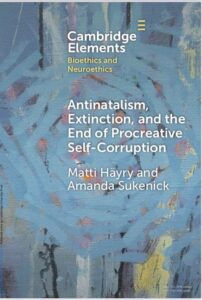
Inti gagasan filsafat Schopenhauer sebagian besar tertuang dalam karya besarnya ‘The World as Will and Representation’ (1818, direvisi 1844).
Menurutnya, kehidupan adalah manifestasi kehendak (will) yang melahirkan gambaran ideal (representasi) dunia, dan implikasi dari kehendak adalah penderitaan.
Kebahagiaan karena terpenuhinya kehendak adalah fana atau sementara saja, karena bahkan ketika semua keinginan manusia terpenuhi, kehidupan menjadi serba pasti dan teratur, maka yang muncul kemudian adalah situasi kejenuhan (boredom) belaka; Meski demikian, ada satu kemungkinan untuk keluar dari situasi ketidakbermaknaan dan penderitaan karena keinginan, yaitu kenikmatan murni yang didapatkan dari keindahan karya-karuya seni.
Hanya dalam kontemplasi estetis manusia menemukan semacam katarsis, pengalaman yg membuatnya berjarak dari keinginan atau hasrat individualnya. Ia merupakan jembatan penghubung menuju ‘pengosongan’ diri dari kehendak dan ‘samsara’ sebagaimana digambarkan dalam Buddhisme.
Filsafat pesimistis dan nihilis ala Schopenhauer membawa pengaruh kuat terutama pada Nietzsche – pencetus konsep ‘kehendak akan kuasa’ (will to power) dan aliran eksistensialisme, sebagai reaksi terhadap alur pemikiran ini.
Penulis eksistensialis Albert Camus dalam ‘The Myth of Sisyphus’ (1942), memaparkan legenda Sisyphus sebagai metafor tentang kehidupan absurd yang harus dijalani manusia.
Dikisahkan bagaimana Sisyphus, tokoh dalam mitologi Yunani dikutuk untuk selalu mengulangi tugas yang sama, mendorong batu karang ke puncak gunung meski ia tahu batu itu akan bergulir jatuh kembali.
Meski demikian Sisyphus rela menjalaninya karena ‘perjuangan’ itu telah memberi makna pada lakon kehidupan yang ia jalani – maka kita harus membayangkan Sisyphus menemukan kebahagiaan pada akhirnya.
Bagi Camus, situasi absurditas tidak dengan sendirinya membenarkan opsi menolak hidup ataupun bunuh diri, melainkan dengan melakukan ‘pemberontakan’ sebagai penegasan eksistensial manusia (‘aku berontak maka aku ada’).
Pada akhirnya, wacana anti-natalisme modern menemukan bentuknya dari karya David Benatar, ‘Better Never to Have Been: The Harm of Coming into Existence’ (2006). Benatar menyatakan bahwa melahirkan manusia ke dunia memiliki sejumlah cacat moral karena beberapa alasan.
Pertama, ada lebih besar kemungkinan logis untuk menderita karena terlahir ke dunia daripada tidak, yang diambil dari ‘argumen (etika) asimetris’ penderitaan dan kesenangan. Dalam skema asimetris tersebut, ketiadaan penderitaan niscaya adalah baik sementara ketiadaan kesenangan bukan sesuatu yang buruk (netral).
Dengan melakukan prokreasi, seorang juga bisa dianggap bertanggungjawab atas ketidakberuntungan generasi-generasi yang akan datang – seperti ketika overpopulasi dan kelangkaan sumber daya menciptakan kemiskinan. Apalagi kenyataan bahwa melahirkan adalah perbuatan yang dilakukan tanpa ‘consent’ (persetujuan) dari yang dilahirkan.
Kedua adalah alasan etika lingkungan bahwa kelahiran/kehadiran manusia berarti penghancuran terhadap spesies lain, dan akhirnya ekosistem secara keseluruhan.
Dengan pertimbangan bahwa manusia adalah makhluk paling destruktif di planet bumi, maka pada tahun 1991 beberapa orang Amerika bahkan membentuk organisasi Gerakan Pemunahan Manusia secara Sukarela (Voluntary Human Extinction Movement) untuk mencegah kerusakan bumi lebih jauh lagi.
Satu hal yang menarik adalah bahwa kelompok ini lebih mendukung penghentian reproduksi secara sukarela untuk mencapai pertumbuhan penduduk di angka nol daripada kontrol populasi yang dipaksakan oleh negara.
Dekonstruksi (ke)keluarga(an)
Sebagai ide antinatalisme tampak sebagai pesimisme ekstrim, dan di Indonesia agaknya tidak terlalu penting; Meski demikian, premis bahwa setiap orang dilahirkan ke dunia tanpa persetujuan dan pilihan bebas – dan karenanya secara probabilitas lebih banyak menciptakan penderitaan – telah mengubah secara fundamental nilai tentang kepengasuhan (parenting) dan peran menjadi orangtua’ (parenthood).
Peran sakral orangtua sebagai agen yang menciptakan kehidupan dan manifestasi kuasa ilahiah hanya mungkin oleh pengakuan akan kehidupan sebagai prinsip positif, anugerah, dan kenikmatan.
Dengan demikian setiap anak yang terlahir mengemban hutang, kewajiban mengabdi pada yg memberi mereka kehidupan. Namun jika kehidupan merupakan sebentuk penderitaan dan ketidakpastian, maka orangtua-lah yang sesungguhnya memiliki hutang moral itu.
Artinya, merekalah yang mesti ‘mengabdi’ untuk kebahagiaan anak-anaknya.
Mungkin segi paling positif adalah kenyataan bahwa antinatalisme mengubah relasi orangtua-anak yang semakin bersifat egalitarian di masa depan.
Orangtua modern umumnya hanya bertanggung jawab atau memegang kontrol penuh atas anak-anaknya pada usia dini, dan setelah itu mereka lebih berperan sebagai partner begitu anak-anak itu menginjak masa remaja (yang di dunia barat sudah dianggap mampu bertanggungjawab).
Semakin berkurang anggapan bahwa seorang anak itu ‘durhaka’ ketika menentang atau tidak sejalan dengan keinginan orangtuanya, sejauh anak-anak ini menyadari implikasi dari pilihan-pilihan mereka.
Sebaliknya, pandangan bahwa orangtua mesti mengalah demi kesenangan anak bisa saja menciptakan generasi yang rentan, kurang memiliki disiplin diri dan rasa bertanggungjawab.
Sementara bagi orang-orang yang berpengetahuan namun merasa kekurangan secara material – dengan standar kelas menengah tentunya – menyebabkan keengganan yg semakin kuat untuk berkeluarga dan berketurunan, tanpa harus menganggap bahwa kelahiran itu buruk adanya.
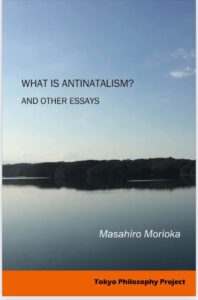
Referensi:
Masahiro Morioka, ‘What is Antinatalism? And other essays’, Tokyo Philosophy Project, 2021
Mati Hayry & Amanda Sukenick, ‘Antinatalism, Extinction and the End of Procreative Self-Corruption’, Cambridge University Press, 2024
Robert C. Solomon & Kathleen M. Higgins, ‘Sejarah Filsafat’, MataBangsa, 2024



