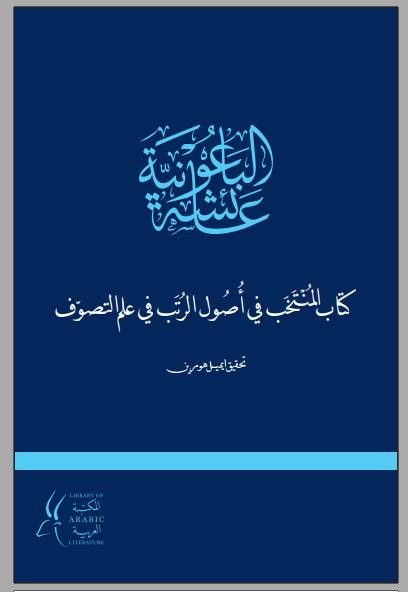
Membincang sufi perempuan tidak mungkin bisa lepas dari bayang-bayang sufi besar Rabi’ah al-Adawiyah (w. 713 M). Nama sufi asal kota Basrah dan konsep cinta (al-hubb)-nya ini telah dan terus menjadi perbincangan dalam diskursus kesufian.
Salah seorang sufi ternama yang masih sangat sedikit, setidaknya dalam tulisan berbahasa Indonesia, adalah Aisyah Al-Ba’uniyyah. Padahal ia bukan hanya cukup terkenal dan mendapatkan apresiasi tinggi oleh para ulama, melainkan juga banyak meninggalkan karya.
Muhammad ‘Ali as-Shoriki dalam bukunya berjudul ‘Aisyah Al-Ba’uniyyah Fadhilat az-Zaman mengatakan bahwa ia adalah perempuan paling ‘alim(ah) pada abad kesepuluh hijriyah. Bahkan, mungkin, salah satu perempuan terhebat dalam sepanjang sejarah Islam setelah sahabat perempuan, generasi tabiin, dan setelahnya tabiin dalam kategori perempuan yang memiliki pengetahuan luas, keutamaan, sekaligus penulis produktif.
Sekilas tentang Aisyah Ba’uniyyah
Aisyah binti Al-Qadhi Yusuf bin Ahmad bin Nashir al-Ba’uni, demikian Ibn ‘Imad dalam Syazarat adz-dzahab melansir nama lengkap sufi asal Damaskus ini. Marga Ba’uniyyah merupakan penisbatan terhadap sebuah nama desa (ba’un) di Yordania Timur yang dikaitkan dengan leluhurnya yang memang berasal dari sana.
Para sejarawan memperkirakan bahwa Aisyah Ba’uniyyah lahir di Damaskus pada pertengahan abad ke-9 H/ 15-M. Perkiraan tahun kelahirannya ini menunjukkan bahwa belum ada data historis yang dapat memastikan tahun kelahirannya.
Ia berasal dari keturunan ulama-ulama besar. Kakeknya, Ahmad ibn Nasir (751-816 H/ 1350-1413) merupakan seorang imam dan khatib di Masjid Al-Aqsha, Masjid Umayyah di Damaskus. Sedangkan ayahandanya, Yusuf ibn Ahmad (805-880 H/1402-1475 M) merupakan seorang kadi di Aleppo dan Damaskus.
Mula-mula ia belajar kepada ayahanda dan anggota keluarganya yang lain. Ia belajar al-Quran, hadis, fikih, hingga sastra. Konon, ia sudah hafal Al-Quran saat usianya baru mencapai umur delapan tahun.
Selain ayahandanya, ada beberapa sosok dari keluarganya yang turut membentuk keilmuan ‘Aisyah. Bahauddin Muhammad bin Yusuf al-Ba’uni (857-916 H) saudara kandungnya, dan kedua pamannya: Burhanuddin Ibrahim bin Ahmad bin Nashir (777-870 H) dan Syamsuddin Muhammad bin Ahmad al-Bauni (?).
Beberapa Karya-Karyanya
Sebagai ulama perempuan yang cukup produktif, Aisyah al-Ba’uniyyah telah menghasilkan sejumlah karya dalam berbagai bidang. Mahdi ‘Arar dalam pengantar suntingan atas karya Aisyah Bauniyyah yang berjudul Takhmis al-Burdah merilis beberapa judul kitab karya Aisyah, di antaranya sebagai berikut:
Al-Isyarat al-Khafiyyah fil Manazil al-‘Aliyyah, sebuah karya di bidang tasawuf yang mana kitab ini merupakan ringkasan (ikhtishar) karya Al-Harawi berjudul Manazil as-Sairin.
Shilat as-Salam fi Fadl as-Shalat was-Salam, sebuah karya ringkasan atas kitab al-Qawl al-Badi’ fish-Shalat ‘ala al-Habib asy-Syafi’ karya As-Sakhawi
Al-Qawl as-Shahih fi Takhmis Burdah al-Madih, sebuah puisi Parsi yang terdiri dari lima baris yang diadopsi dari Burdah karya Imam Al-Bushiri.
Al-Malamih asy-Syarifah fil Atsar al-Munifah, tentang tasawuf
Al-Muntakhab fi Ushul ar-Rutab fi ‘Ilm at-Tashawwuf, sebuah karya tentang tasawuf.
Diwan al-Bauinyyah, kumpulan puisi.
Dan sejumlah karya lainnya.
Tarekat Qadiriyyah dan Konsep Cinta ala Aisyah
Sufisme merupakan disiplin yang bukan hanya digemari oleh ‘Aisyah Al-Bauniyyah, melainkan menjadi praktik dan laku spiritualnya. Sebagian besar keluarganya yang merupakan para pelaku dan guru-guru sufi rupanya turut membentuk Aisyah dalam spesialisasi di bidang ilmu ini.
Emil Homerin dalam sebuah tulisannya berjudul Living Love: The Mystical Writings of ‘Aishah al-Bauniyyah, menulis:
Aishah also specialized in the study and practice of Islamic msyticism, which was important to the entire family. Her great uncle Ismail had been a Sufi ascetic; her uncle Muhammad composed a devotional poem of over the thousand verses on the prophet Muhammad, while her uncle Ibrahim had been the first director of the al-Basitiyah khanqah in Damascus.
Menurut Homerin, Aisyah sangat menggandrungi tarekat Qadiriyyah, sebuah tarekat yang dinisbatkan kepada Syaikh Abdul Qadir al-Jailani. Hal ini, menurutnya, tercermin dari karya-karya tasawuf yang ditulisnya. Pun ia juga sangat dipengaruhi oleh Abdullah al-Anshari dalam karyanya berjudul Manazil as-Sairin.
Al-Muntakhab fi Ushul ar-Rutab fi ‘Ilm at-Tashawwuf adalah salah satu karya Aisyah Al-Bauniyyah. Emiel Homerin menyunting karya yang manuskripnya tersimpan di Dar Kutub al-Mishriyyah di mana dalam manuskrip ini tercatat tahun 1071 H/ 1661 M sebagai tahun penulisannya.
Dalam kitab ini Aisyah menjelaskan mengenai “maqamat” bagi para penempuh (salik). Menurutnya, maqamat bagi para salik tidak terbatas jumlahnya. Namun, secara prinsip semuanya bermuara pada empat maqam utama: taubat, ikhlas, dzikir, dan mahabbah. Oleh karenanya, dalam kitab yang setelah disunting berjumlah 76 halaman ini hanya menjelaskan empat hal ini.
Setiap bab dalam kitabnya ini berisi penjelasan dan uraian yang cukup panjang mengenai prinsip maqamat ini. Dimulai dengan rujukan primer: Al-Quran dan Hadis, Aisyah juga memperkaya penjelasannya dengan kutipan-kutipan para sufi besar seperti Dzu Nun al-Mishri, Fudhail bin ‘Iyadh, hingga Abu Yazid al-Bishthami. Kekayaan kutipan ini tentu bisa dikatakan sebagai salah satu bukti banyaknya literatur yang dibacanya.
Salah satu intisari dari kitab ini adalah penjelasan yang cukup komprehensif tentang konsep cinta (al-Mahabbah). Mengenai Mahabbah, ia menulis:
cinta adalah rahasia Allah yang paling agung. Intisari dan kejerniha. Buah dari pengkhususan. Wasilah mendekatkan diri. Mikraj untuk wushul. Hakikat kemuliaan. Rahasianya rahasia. Lautan tanpa tepi. Mutiara yang tak ternilai harganya. Cahaya tanpa kegelapan yang menyertainya. Rahasia yang tidak bisa direngkuh wujudnya. Makna yang tak bisa disifati oleh akal. Cinta yang demikian ini sejalan dengan firman-Nya: Demikianlah karunia Allah, diberikan-Nya kepada siapa yang dikehendaki-Nya; dan Allah mempunyai karunia yang besar (al-Jumuah: 4).
Aisyah al-Bauniyah merupakan salah satu sosok perempuan ‘alim yang menguasai banyak disiplin keilmuan, fikih, sastra, hingga tasawuf. Tak heran bila pujian dari banyak ulama terkemuka lintas zaman terhadapnya mengalir deras. Syaikh ‘Abdul Ghani An-Nabulsi (w. 1731 M), salah satu pembesar Sufi asal Damaskus, memujinya dengan perkataan “Aisyah merupakan ulama terkemuka di masanya dan pemimpin sastrawan kesohor”.
Konsep mahabbah-nya membuat Aisyah merasakah keintiman dengan Tuhan. Ia memilih untuk terasing dari dunia, mengagumi Tuhan dan merasakan kepuasan atas segala kehendak-Nya. Ia sangat mencintai orang lain yang mencintai Tuhan, dan meninggalkan hal-hal duniawiyah yang sebelumnya ia cintai (Homerin: 231).



