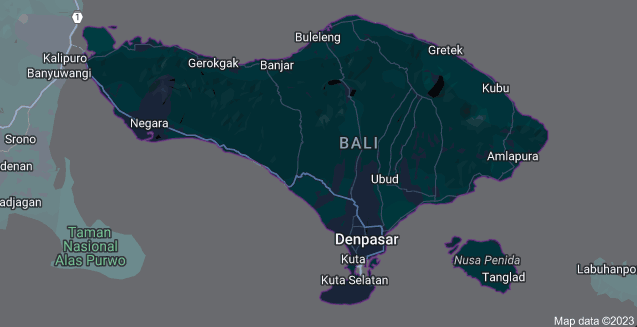
Apa bayangan yang muncul saat mendengar kata Bali? Selain pulau yang memiliki garis pantai nan indah, hal yang acap kali diasosiasikan dengan Bali adalah kata Dewata yang bermakna tempat tinggal para dewa.
Memang, 86 persen dari total penduduk Bali memeluk agama Hindu yang menjadikan kebudayaan penduduk di sana sangat lekat dengan ajarannya. Hal ini pula yang jadi alasan mengapa di hampir tiap jengkal wilayah Bali akan dengan mudah ditemukan Pura, istana para dewa, yang notabene merupakan tempat peribadatan mereka.
Tapi siapa sangka, Bali yang sering dikaitkan dengan ajaran Hinduisme ternyata memiliki jejak para wali yang membawa ajaran agama Islam di sana. Bahkan, saat ini telah diistilahkan dengan Wali Pitu atau tujuh wali dalam arti harafiah.
Dikatakan bahwa kiprah Wali Pitu hampir sama dengan Walisongo yang ada di pulau Jawa dalam misinya menyiarkan agama Islam di pulau Bali. Berangkat dari asumsi tersebut, banyak orang berdatangan ke makam Wali Pitu yang letaknya menyebar ke seluruh penjuru pulau Bali, untuk berziarah.
Daftar nama dan lokasi Wali Pitu tersebut adalah sebagai berikut: 1) Pangeran Mas Sepuh / Raden Amangkurat (Badung), 2) Habib Umar bin Maulana Yusuf al Maghribi (Tabanan), 3) Habib Ali bin Abu Bakar bin Umar bin Abu Bakar Al-Hamid (Klungkung), 4) Habib Ali Zainul Abidin Al-Idrus (Klungkungan), 5) Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdi Al-Maghribi (Karangasem), 6) Syekh Abdul Qodir Muhammad / Kwan Lie (Buleleng), 7) Habib Ali bin Umar Bafaqih (Jembrana).
Referensi Wali Pitu di Bali berasal dari sebuah buku berjudul ‘Sejarah Wujudnya Makam Sab’atul Auliya Wali Pitu di Bali’, yang ditulis oleh Chabib Toyyib Zaen Arifin Assegaf dan diterbitkan pada tahun 1998.
Chabib Toyyib Zaen Arifin Assegaf merupakan pengasuh Jam’iyah Manaqib al-Jamali (Jawa Madura Bali). Ia menulis buku tersebut atas dasar pengalaman spiritual yang dialami pada bulan Muharram 1412 H atau tahun 1992 M. Ia mengaku telah mendapatkan petunjuk dari Tuhan sehingga menemukan makam-makam Wali Pitu tersebut.
Wali di Bali?
Bagi umat Islam lokal yang tinggal di perkampungan muslim di Bali, mereka mengaku mulanya tidak mengenal istilah Wali Pitu di sana. Menurut mereka, justru istilah tersebut datang dari para pelaku wisata religi yang datang dari luar wilayah Bali.
Kiai Fathur Rahim, salah satu tokoh agama Islam di kampung muslim, sekaligus pengasuh pondok pesantren Nurul Ikhlas di Jembrana, Bali, sepakat dengan opini tersebut.
Ia menyangsikan keabsahan Wali Pitu. Katanya, saat mengunjungi makam-makam tersebut ditemukan ketidakcocokan cerita antara juru kunci makam dengan warga sekitar, tentang ketokohan wali yang diziarahi. Salah satunya adalah makam wali Syekh Maulana Yusuf Al-Baghdi Al-Maghribi di Karangasem.
Dalam pemaparan warga setempat, Maulana Yusuf Al-Baghdi Al-Maghribi adalah orang keturunan Arab yang masuk dalam kategori Sohibul Ghanam (orang kaya raya), yang profesi utamanya adalah tukang jagal kambing, dan semasa hidupnya tidak (terlalu) dianggap masyarakat sebagai sosok istimewa.
Menurut Kiai Fathur Rahim, harus ditemukan kesesuaian narasi antara cerita ketokohan sosok yang dianggap wali dengan masyarakat yang hidup di wilayah pemakamannya. Apalagi ketika makam itu ada di tengah kampung muslim. Baginya, musykil masyarakat setempat tidak mengetahui cerita sejarah tokoh istimewa (baca: wali) yang ada di wilayahnya sendiri.
Agaknya, keberadaan situs Wali Pitu di Bali memang perlu dipertanyakan akurasinya. Menilik bagaimana Habib Toyyib Zaen Arifin Assegaf menuliskan sejarah Wali Pitu berdasarkan referensi pengalaman spiritual, tentu membutuhkan verifikasi sejarah lanjutan.
Dalam opini Kiai Fathur Rahim, ia tidak menyetujui pendapat yang menyamakan kebesaran Wali Pitu di Bali dengan Walisongo di Jawa.
Walisongo merupakan dewan ulama (sekaligus wali) yang dibentuk oleh Raden Rahmat (Sunan Ampel) pada 1404 M atas misi penyebaran Islam di seluruh tanah Jawa. Sementara, Wali Pitu di Bali merupakan istilah dari makna leksikal ‘tujuh wali’, yang dalam hematnya, tidak memiliki kadar signifikansi yang sama dalam penyebaran Islam di Bali jika dibandingkan dengan Walisongo di Jawa.
Dialektika Kewalian
Pertanyaan yang (mungkin) muncul setelah rentetan penjelasan tersebut: bagaimana kemudian umat Islam bisa ada di Bali dan sampai membuat komunitas (baca: kampung) muslim di sana?
Meski Kiai Fathur Rahim meragukan keaslian Wali Pitu, namun ia tidak menampik adanya wali-wali yang berperan dalam penyebaran Islam di Bali, yang dalam hitungan jumlahnya lebih dari tujuh.
Banyak ulama, para wali, yang telah berjasa menyiarkan agama Islam di tanah Dewata di luar dari tujuh wali yang disebutkan dalam daftar Wali Pitu. Misalnya, Gusti Ayu Made Rai atau Siti Khatijah, seorang putri raja Puri Pamecutan yang menjadi mualaf karena pernikahannya dengan Raden Cakraningrat IV dari Keraton Madura.
Konversi agama Siti Khatijah yang mulanya Hindu jadi Islam, kemudian mengenalkan umat Hindu di Bali tentang ajaran agama Islam. Dan, banyak lagi contoh ketokohan ulama (wali) yang kisah dan makamnya dapat ditemukan di kampung-kampung muslim yang tersebar di pulau Bali.
Di luar kontroversi keakuratan Wali Pitu, keberadaan makam-makam ‘keramat’ yang ramai diziarahi tersebut mampu membantu perekonomian masyarakat di daerah Bali. Terhitung dari kisaran jumlah pengunjung ziarah yang mencapai 50ribu orang tiap tahun. Merujuk pada tulisan penulis sebelumnya bahwa wisata religi merupakan ‘ladang basah’ yang mampu menumbuhkan perekonomian daerah setempat.
Oleh karena itu, dibutuhkan pemahaman dialektis terkait keberadaan wali di bumi Dewata yang tidak bisa disamakan dengan keberadaan wali di tanah Jawa. Tanpa sikap kritis untuk bertabayyun dengan menanyakan dan memverifikasi sumber keakuratan situs makam wali, malah menjerumuskan diri dalam kebodohan untuk mengeramatkan makam yang tidak sepatutnya disakralkan (wallahu alam).



