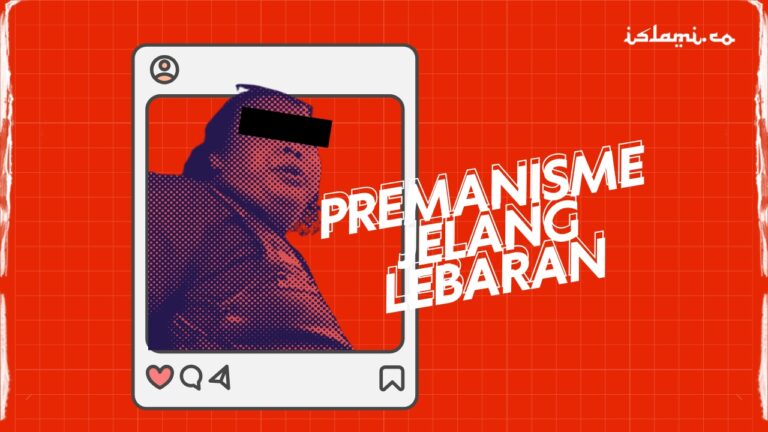
Fenomena organisasi kemasyarakatan (ormas) atau kelompok yang mengatasnamakan LSM, meminta THR (Tunjangan Hari Raya) menjelang lebaran akhir-akhir ini, menimbulkan keresahan di kalangan dunia usaha. Di Bekasi, seorang laki-laki yang dikenal dengan jagoan Cikiwul berurusan dengan polisi karena minta THR disertai pengancaman.
Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) Jakarta, Khrisnadi, mengungkapkan, permintaan semacam ini bukanlah hal baru dan kerap terjadi setiap tahun. Ia menyoroti banyak ormas menganggap pengusaha sebagai sumber dana yang selalu dapat dimintai bantuan finansial, terutama menjelang hari raya.
Di Tangerang Selatan, Wali Kota Benyamin Davnie mengimbau agar ormas tidak memaksa dalam meminta THR kepada pengusaha. Ia menekankan, meskipun pengajuan bantuan diperbolehkan, tindakan pemaksaan dapat berujung tindak pidana. Pemerintah kota berkomitmen mengawasi aktivitas ormas guna memastikan tidak ada pelanggaran hukum dalam praktik tersebut.
Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) juga menyuarakan keprihatinannya terhadap praktik ini. Ketua Bidang Ketenagakerjaan Apindo, Bob Azam, menegaskan, permintaan THR oleh ormas seharusnya tidak dilakukan dengan memaksa atau premanisme, karena dapat berdampak negatif pada iklim usaha dan investasi. Ia mengingatkan, perusahaan memiliki dana Corporate Social Responsibility (CSR) yang dapat digunakan untuk pembinaan komunitas, namun penyalurannya harus dilakukan secara bijak dan tanpa tekanan.
Pihak kepolisian pun memberikan peringatan tegas terhadap ormas yang memaksa meminta THR. Kabid Humas Polda Metro Jaya, Kombes Ade Ary Syam Indradi, menyatakan, tindakan tersebut merupakan perbuatan melawan hukum dan akan ditindak sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Masyarakat dan pengusaha yang mengalami intimidasi diimbau segera melapor ke pihak berwajib.
Fenomena ini juga sekaligus menunjukkan bahwa praktik pemaksaan oleh ormas dalam meminta THR masih terjadi dan menimbulkan keresahan di masyarakat. Penegakan hukum yang tegas dan kesadaran kolektif dari semua pihak diperlukan untuk menghapus praktik premanisme yang berkedok tradisi ini. Tindakan ini juga merusak ketertiban sosial sekaligus menciptakan ketakutan di kalangan warga dan dunia usaha.
Sayangnya, yang mengejutkan, fenomena ini malah dianggap “tradisi” oleh Wakil Menteri Agama, Romo M. Syafi’i. Menurutnya, aksi premanisme menjelang Lebaran bagian dari “budaya Lebaran di Indonesia sejak dahulu kala” dan karena itu tidak perlu dipermasalahkan. Pernyataan Wamen pada 24 Maret 2025 ini menunjukkan betapa lemahnya pemahaman sejarah dalam melihat dinamika sosial di Indonesia.
Premanisme Warisan Orde Baru
Jika kita telusuri sejarah, klaim bahwa aksi premanisme semacam ini sebagai “budaya asli Indonesia” adalah kesalahan besar. Aksi meminta-minta dengan cara memaksa bukan bagian dari tradisi masyarakat. Justru, fenomena ini merupakan produk politik dan sosial era Orde Baru yang berkembang sejak 1970-an hingga 1990-an.
Pada masa Soeharto, negara membiarkan atau bahkan secara tidak langsung mendorong tumbuhnya berbagai organisasi kemasyarakatan (ormas) dan kelompok pemuda berseragam menyerupai militer. Kelompok-kelompok ini sering bertindak sewenang-wenang dengan dalih menjaga keamanan dan ketertiban, namun pada kenyataannya mereka sering berperan sebagai alat kekuasaan mengontrol masyarakat bawah dan menekan lawan-lawan politik. Dalam praktiknya, mereka sering meminta “sumbangan wajib” dari pengusaha dan pedagang, terutama menjelang hari-hari besar seperti Hari Kemerdekaan, Natal, Tahun Baru, dan tentu saja Lebaran.
Sosiolog Ariel Heryanto dalam bukunya State Terrorism and Political Identity in Indonesia: Fatally Belonging (2006) menjelaskan, sejumlah kelompok pemuda dan ormas yang tumbuh di era Orde Baru memiliki relasi kuat dengan aparat negara. Mereka diberi ruang beroperasi secara semi-legal sebagai “perpanjangan tangan” pemerintah, tetapi dalam praktiknya sering bertindak seperti preman dengan dalih menjaga stabilitas dan ketertiban.
Fenomena ini juga diperkuat analisis Edward Aspinall dalam Opposing Suharto: Compromise, Resistance, and Regime Change in Indonesia (2005). Ia menjelaskan bagaimana berbagai organisasi semi-militer digunakan menekan kelompok-kelompok oposisi, dan di saat bersamaan mencari keuntungan ekonomi melalui praktik pemerasan terselubung.
Premanisme Pasca Reformasi
Setelah reformasi 1998, banyak kelompok yang dulu jadi alat rezim Orde Baru mulai mencari cara baru untuk bertahan hidup. Beberapa berubah menjadi ormas dengan klaim berbasis agama atau nasionalisme, sementara lainnya menjelma jadi kelompok kepemudaan yang mengklaim membela kepentingan rakyat. Namun, pola-pola pemaksaan dan kekerasan masih berlanjut, bahkan berkembang lebih luas dengan dalih menjaga ketertiban atau mendukung kepentingan masyarakat.
Riset Ian Wilson dalam bukunya The Politics of Protection Rackets in Post-New Order Indonesia (2015) menunjukkan, banyak kelompok preman dan ormas yang berkembang di era reformasi memiliki jaringan dengan elit politik dan aparat keamanan. Mereka sering beroperasi dengan sistem perlindungan (protection racket), di mana pengusaha atau masyarakat “dipaksa” bayar uang keamanan demi menghindari gangguan.
Dalam konteks Lebaran, fenomena ini jadi lebih dirasakan karena adanya tekanan sosial dan ekonomi. Dengan dalih solidaritas dan tradisi berbagi, sejumlah kelompok ini meminta jatah Lebaran atau THR dari para pengusaha, tetapi bukan dengan cara sukarela, melainkan dengan paksaan dan ancaman.
Indonesia memiliki tradisi berbagi dan gotong royong, terutama dalam perayaan hari besar keagamaan. Konsep zakat, sedekah, dan infak adalah bentuk kepedulian sosial yang dianjurkan agama. Namun, gotong royong dan sedekah selalu bersifat sukarela, bukan dipaksa dengan ancaman apalagi kekerasan.
Sosiolog Koentjaraningrat dalam Kebudayaan, Mentalitas, dan Pembangunan (1974) menekankan, nilai gotong royong dalam masyarakat Indonesia adalah kerja sama yang dilakukan atas dasar kesadaran kolektif, kerelaan bukan paksaan. Gotong royong bukan hanya dipahami sebagai perilaku melainkan juga sebagai nilai-nilai moral. Jika ada unsur pemaksaan, maka tidak bisa lagi dimaknai gotong royong.
Pernyataan blunder Wamen yang menyebut aksi premanisme sebagai “budaya Lebaran” adalah bentuk distorsi sejarah dan kegagalan memahami dinamika sosial kebangsaan. Jika dibiarkan, ini akan semakin memperkuat anggapan bahwa tindakan intimidatif adalah sesuatu yang lumrah dan dapat ditoleransi dalam masyarakat.
Lawan Premanisme
Aksi premanisme berkedok tradisi yang muncul menjelang Lebaran bukan sekadar keresahan tahunan, melainkan ancaman bagi tatanan sosial. Ketika kelompok tertentu menggunakan dalih solidaritas dengan menekan dan memeras pengusaha, esensi ketulusan berbagi berubah jadi praktik intimidasi yang mencederai nilai-nilai kebersamaan. Fenomena ini tidak dapat dibiarkan, apalagi ditoleransi dengan alasan kebiasaan. Butuh langkah tegas dan sistematis menghapus warisan buruk ini.
Penegakan hukum harus menjadi ujung tombak menangani aksi pemaksaan berkedok sumbangan. Aparat keamanan tidak boleh ragu menindak kelompok-kelompok yang menggunakan ancaman sebagai alat mengeruk keuntungan. Selama ini, kelemahan dalam penegakan hukum justru memberikan ruang bagi praktik ini terus berkembang, menciptakan siklus ketakutan di kalangan pengusaha dan masyarakat. Ketegasan hukum bukan hanya menghentikan aksi premanisme di lapangan, tetapi juga mengirim pesan bahwa tidak ada tempat bagi pemerasan dalam kehidupan bermasyarakat.
Selain langkah hukum, upaya meningkatkan kesadaran publik juga menjadi penting. Tradisi berbagi dalam Islam telah memiliki mekanisme yang jelas melalui zakat, infak, dan sedekah, semuanya berakar pada keikhlasan, bukan tekanan. Oleh karena itu, masyarakat perlu mendapatkan pemahaman agar mengerti antara donasi sukarela dan pemaksaan berkedok solidaritas. Kampanye publik tentang pentingnya berbagi yang benar dapat membantu mengurangi legitimasi sosial terhadap praktik premanisme ini.
Lebih dari itu, revitalisasi nilai gotong royong harus dikedepankan sebagai alternatif. Pemerintah dan masyarakat sipil harus memperkuat skema bantuan sosial berbasis komunitas, yang tidak hanya memastikan yang berhak mendapatkan bantuan, tetapi juga menutup celah kelompok-kelompok yang ingin memanfaatkan kebaikan orang lain demi kepentingan pribadi. Gotong-royong yang sehat tumbuh dari empati dan kepedulian, bukan karena tekanan dan ketakutan.
Premanisme tidak akan pernah bisa diberantas jika masih ada dukungan politik di belakangnya. Selama ini, hubungan antara elite politik dan kelompok-kelompok preman menjadi simbiosis saling menguntungkan: premanisme mendapatkan perlindungan, sementara politisi memperoleh alat mobilisasi. Untuk mengakhiri ini, partai politik dan pejabat publik harus mengambil sikap tegas dengan tidak lagi memberikan ruang bagi kelompok yang menggunakan cara-cara kekerasan. Selama masih ada perlindungan politik, premanisme akan terus tumbuh dan berkembang dengan wajah baru yang lebih sulit diberantas.
Menganggap pemerasan menjelang Lebaran sebagai bagian dari budaya menunjukkan ketidakpahaman terhadap sejarah dan tumpulnya memahami realitas sosial. Budaya berbagi dalam masyarakat tidak pernah lahir dari paksaan, melainkan keikhlasan. Oleh karena itu, yang dibutuhkan bukanlah pembenaran terhadap praktik ini, melainkan keberanian melawannya.
Solidaritas sejati tidak pernah lahir dari ancaman, tetapi ketulusan. Jika ingin menjaga nilai-nilai luhur gotong royong, maka sudah saatnya memberantas premanisme dengan ketegasan dan menggantinya dengan semangat berbagi sesuai ajaran Baginda Nabi.
(AN)



