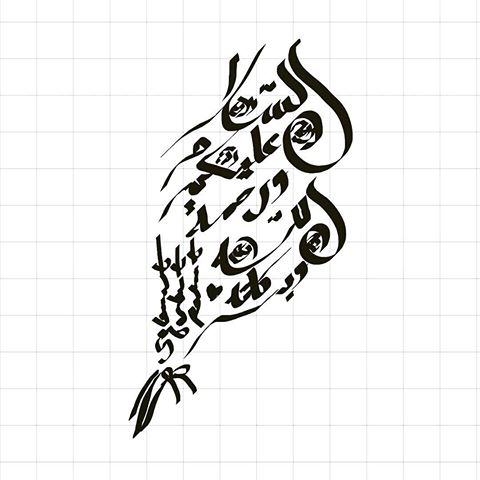
Untuk pertama kalinya, rasanya saya perlu menyapa para pembaca islami.co dengan salam. Sebuah kalimat pembuka yang sudah menjadi sedemikian klise di antara sekian banyak kebiasaan yang terjadi di tengah komunikasi dan interaksi sosial kita sehari-hari.
Tidak masalah. Saya masih menyimpan segugus keyakinan di kedalaman dan kesunyian batin bahwa di balik tiap ritual yang telah kadung “bermetamorfosis” menjadi hambaran ke hambaran masih terdapat ruang sakral untuk menyematkan sepotong ketulusan pada sesama.
Memang sangat terasa kemerosotan nilai dan filosofi salam secara ontologis di tengah persuan dan persinggungan di antara sesama muslim. Makna luhur dan mulia yang terkandung di dalamnya semakin hari semakin kikis untuk kemudian kabur ditelan oleh kehampaan dan angkara murka.
Saksikanlah dengan seksama. Orang-orang mengucapkan salam dengan lantang dan fasih ketika memulai orasi di mimbar-mimbar demonstrasi untuk kemudian mencaci-maki dan meludahi kehormatan siapa saja yang tidak sejalan dengan pandangan dan keyakinan mereka.
Orang-orang memulai ceramah dengan mengucapkan salam yang keseriusannya tidak mungkin terbantahkan oleh siapa pun. Setelah itu mereka menempelkan gelar “bajingan” dan “kurang ajar” kepada siapa saja yang pemikiran dan interpretasi keagamaannya tidak sejalan dan tidak seirama dengan keyakinan mereka.
Orang-orang memulai khotbah di masjid-masjid pada hari Jumat dengan salam yang sangat kental dengan nuansa Arab. Setelah itu mereka memuntahkan dengus kebencian demi dengus kebencian kepada siapa saja yang diyakini sebagai “dedengkot-dedengkot” agama yang dekil dan tidak bermoral.
Orang-orang mengucapkan salam dengan keyakinan yang bersahaja ketika membuka rapat di perusahaan-perusahaan. Setelah itu mereka bersungguh-sungguh setengah mati untuk menguasai forum dan “memaksa” para peserta rapat yang lain untuk sepenuhnya mengikuti jalan pikiran mereka yang telah disetting sebelumnya.
Orang-orang yang terpelajar dari kalangan mahasiswa mengucapkan salam dengan lagak yang paling elegan ketika membuka acara LPJ di organisasi-organisasi yang mereka selami. Setelah itu suasana menjadi panas dan beringas, saling tuding dan penuh dengan kemarahan, baik yang agak disembunyikan maupun yang meledak-meledak.
Sumpek dengan suasana-suasana kelam seperti itu? Bisa ya. Bisa juga tidak. Tapi saya jelas memilih condong kepada yang tidak. Sebab, di seberang segala suasana yang kelam, –uluk salam bercampur ketidaksenonohan– itu ada cakrawala cahaya dan keindahan yang menghablur langsung dari Tuhan semesta alam.
Kalau di pagi hari kita tidak bisa menikmati kicauan burung-burung, kalau menjelang malam kita tidak bisa menikmati kemolekan senja, kalau di musim hujan kita tidak bisa menikmati rumput-rumput yang tumbuh dan bunga-bunga yang tumpah-ruah, kalau di tengah malam kita tidak bisa menikmati kedepan bintang-bintang, kalau menjelang subuh kita tidak bisa menikmati kokok-kokok ayam jantan, dan lain sebagainya, maka sesungguhnya masih disediakan untuk kita aneka macam jalan spiritual yang menuju kepada asal-usul semua keindahan tersebut. Itulah dimensi jamaliyyah dari hadiratNya.
Dengan dimensi yang tidak akan pernah lekang oleh panas dan tidak akan pernah lapuk oleh hujan itulah saya berikhtiar untuk tetap nekad mengucap salam, baik secara terang-terangan maupun dengan cara yang paling senyap, kepada siapa saja yang saya “jumpai” dalam hidup ini. Baik kepada mereka yang saleh maupun kepada mereka yang durja.
Bukan apa-apa. Bukankah dalam hidup yang sekejap ini kita mesti senantiasa menebarkan damai dan pengharapan kepada sesama? Setelah itu, dengan melodi keindahan hadiratNya, semoga kita selalu melangkah dengan penuh senyuman menuju hamparan bunga keabadian yang menggigil di seberang semesta yang fana ini. Wallahu a’lamu bish-shawab. (Kuswaidi Syafiie adalah penyair, juga pengasuh PP Maulana Rumi Sewon Bantul Yogyakarta)



