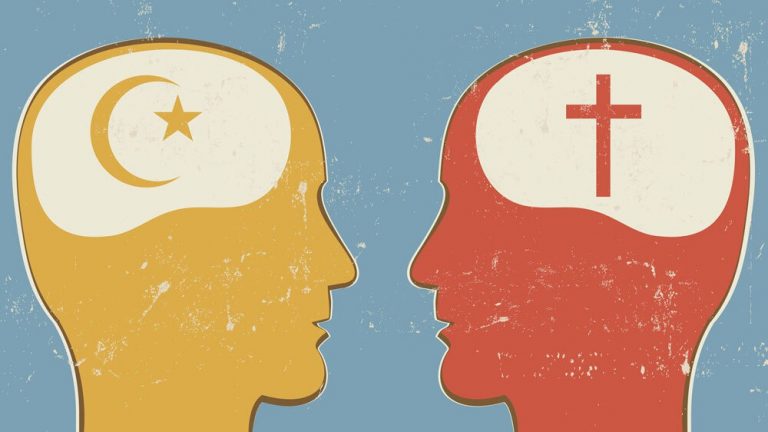
Beberapa waktu lalu, linimasa media sosial sempat dihebohkan oleh surat edaran yang dikeluarkan oleh salah satu rektor di Yogyakarta. Media sosial mendadak ramai, dan televisi turut latah memberitakannya. Sebagian sarjana menyebut fenomena ini sebagai “Desakralisasi Gelar.” Artinya, gelar tersebut “dicoba” untuk tidak lagi memiliki nilai prestise seperti sebelumnya.
Denis Lombard pernah mengatakan bahwa gelar akademis telah berubah menjadi gelar kebangsawanan baru. Dunia akademik yang diimpor dari Barat, menurut Lombard, tidak pernah benar-benar “modern” atau rasional berbasis meritokrasi. Bagus Laksana, seorang akademisi, mengutip Lombard bahwa lembaga akademik yang diimpor dari Barat ini dimanfaatkan oleh kaum elit priyayi untuk melestarikan prestise dan pengaruh mereka.
Jika mengacu pada kumpulan surat Kartini yang diterjemahkan dengan judul Habis Gelap, Terbitlah Terang, kita bisa bertanya: “Apakah usaha desakralisasi gelar akademik yang mulai digalakkan (walaupun masih sedikit) dapat menghapuskan kesenjangan yang selama ini terjadi akibat sakralisasi gelar akademik?”
Euforia kita atas desakralisasi gelar seharusnya tidak membuat kita lupa akan konsep “hegemoni” yang diperkenalkan oleh Gramsci. Jika ditelaah lebih dalam, gelar akademik bisa menjadi alat hegemonik kelompok dominan terhadap kelas subordinat.
Pemilik gelar tersebut dapat menggunakan gelar mereka untuk menciptakan konsensus politik atau ideologis yang menyusup ke dalam kelompok dominan maupun yang didominasi. Mereka menggunakan berbagai cara untuk membangun lingkaran-lingkaran semu yang tak kasat mata, yang pada akhirnya mempengaruhi kelompok-kelompok lain.
Pengetahuan sering kali menjadi alat akademisi untuk mengeksklusi atau mengeluarkan orang-orang yang tidak sesuai dengan standar mereka. Persoalan ini sulit dilawan jika kita hanya berhenti pada desakralisasi gelar. Penindasan atau hegemoni terhadap kelompok tertentu sering kali “diresmikan” dengan berbagai ungkapan atau dalil-dalil yang tampak sah.
Desakralisasi gelar bisa menjadi awal yang baik, tetapi jika kita berhenti di sini, penindasan terhadap kelompok lain tetap akan berlangsung. Apalagi, alasan rasionalisasi pengetahuan dan normalisasi ketimpangan pendidikan sangat mudah ditemukan di ruang publik kita saat ini.
Di titik ini, perempuan sering kali menjadi kelompok subordinat. Perempuan yang memiliki gelar serupa dengan laki-laki mungkin saja mendapatkan perlakuan negatif atau disubordinasi, seperti disingkirkan atau diabaikan. Kita sering mendengar ungkapan-ungkapan negatif yang ditujukan kepada perempuan yang berpendidikan tinggi.
Dalam banyak struktur sosial dan imaji masyarakat kita, perempuan masih belum benar-benar bebas dari relasi patriarkal yang menindas. Seorang perempuan bisa mengalami penindasan atau subordinasi sejak bangun tidur hingga tidur kembali.
Seperti dijelaskan sebelumnya, desakralisasi gelar mungkin menjadi langkah awal yang baik. Namun, bagi perempuan, desakralisasi hanya akan berdampak jika diikuti dengan pembongkaran relasi patriarki di lingkungan akademik. Posisi akademisi perempuan sering kali dinomorduakan atau rentan menghadapi subordinasi dari kelompok dominan.
Penyeragaman hingga penerapan standar khusus bagi perempuan sudah biasa kita temui. Ini harus dibongkar dan dilawan, karena nilai-nilai yang selama ini berlaku sering kali tidak ramah terhadap perempuan.
Berkaca pada pengalaman Kartini, perjuangan perempuan untuk mendapatkan relasi yang setara masih menghadapi stigma dan mitos tentang peran, posisi, serta keadaan mereka. Desakralisasi gelar hanya akan menjadi ilusi jika hanya menguntungkan segelintir pihak, misalnya laki-laki. Hegemoni atas perempuan sering kali berlapis-lapis dan berkarat, hingga sulit dikenali apakah itu penindasan. Kita telah menerimanya sebagai nilai yang hidup di masyarakat.
Desakralisasi relasi patriarki di kalangan akademisi harus menjadi agenda kita berikutnya. Kita perlu membongkar penindasan dan subordinasi yang selama ini dilanggengkan di dunia akademik, karena nilai-nilai yang digunakan sering kali memperkuat relasi tersebut.
Jika desakralisasi gelar hanya berhenti pada perayaan sesaat, kita sebenarnya belum benar-benar berubah. Desakralisasi gelar tidak akan benar-benar berhasil menjalankan tugasnya, yaitu menghapuskan penggunaan gelar untuk melestarikan relasi priyayi atau elit di kalangan akademisi.
Cita-cita egalitarianisme dan kesetaraan yang diharapkan dapat mendorong akademisi berkontribusi langsung ke masyarakat bisa saja gagal jika posisi perempuan diabaikan. Oleh karena itu, bagian dari usaha desakralisasi seharusnya menciptakan ruang yang aman, nyaman, dan setara bagi akademisi perempuan.
Dimuat juga di sini
Fatahallahu alaina futuh al-arifin



