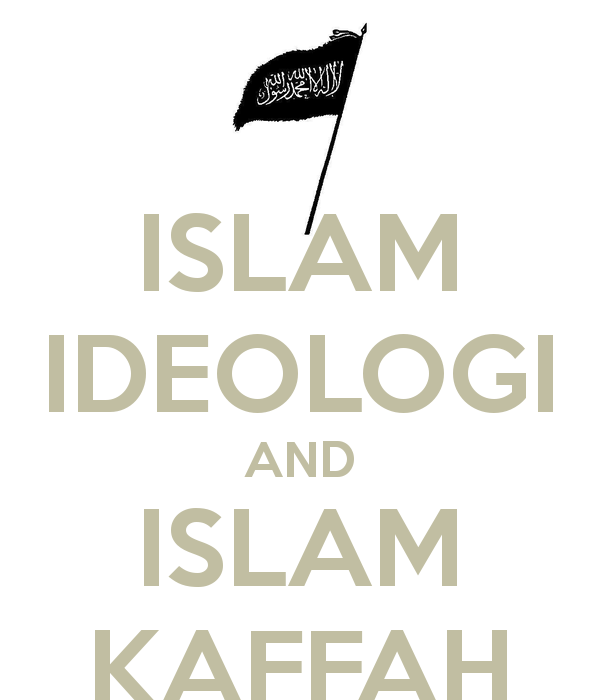
Ada beberapa pertanyaan: bagaimana tafsiran kata kaffah itu sendiri? Bagaimana kriteria kaffah? Dan kaffah menurut siapa? Apakah setiap individu memiliki otoritas mengklaim dirinya kaffah hanya dengan beranggapan telah menjalankan syariat Islam? Adakah tingkatan ke-kaffah-an, karena bukankah kaffah pun sesuatu yang sangat relatif? Atau jangan-jangan orang yang mengaku kaffah hanya sebatas seonggok egoisitas yang sok benar dan berlaga paling Islam, paling sempurna daripada yang lain.
Dan pertanyaan terakhir, perlukah kita beragama secara kaffah? Beberapa pertanyaan ini harus dijawab dengan pikiran jernih dan sadar terhadap realitas. Kaffah yang bahasa Arab itu kalau ditransliterasikan ke dalam bahasa Indonesia mengandung makna: semuanya tanpa kecuali. Dalam al-Qur’an kita dapat menjumpai kata kâffah dalam empat ayat. Pada surah al-Baqarah ayat 208, al-taubah ayat 36 dan 122, terakhir dalam surah Saba’ ayat 28.
Kalau diperhatikan, Allah menggunakan kata kâffah paling banyak—meskipun hanya dua kali—pada surat al-taubah, yang mana dalam kebanyakan ayatnya mengisahkan peperangan atas pemutusan hubungan damai anara kaum mukminin dan musyrikin. Dalam ayat 36 misalnya, dipaparkan bahwa orang mukmin diperintahkan oleh Allah untuk memerangi orang musyrik secara kâffah.
Dalam surat Saba’ kata kâffah berbicara dalam konteks risalah Muhammad yang universal, menyeluruh untuk segenap umat manusia. Namun, yang menarik untuk kita bincangkan adalah kata kâffah yang terdapat dalam surah al-Baqarah ayat 208.
Adapun teks lengkap dari ayat tersebut adalah sebagai berikut: Yâ ayyuhalladzîna âmanû unkhulû fi al-silmi kâffah walâ tattabi’u khutuwât al-syaithân, innahu lakum ‘aduwwum mubîn.
Maka tak lacur kalau kita memahami ayat ini secara integral antara satu kata dengan kata yang lain. Dan ada baiknya pula membandingkan satu jenis aliran qiraat (bacaan) dengan qiraat yang lain pula.
Sebelum kata “kâffah“, kita temui kata “silmi“. Kebanyakan kita menafsirkan kata silmi dengan Islam. Padahal kalau kita membaca tafsir yang ditulis oleh Muthafa Al-Maraghi, ia mencatat, bahwa asal kata silmi yaitu tunduk dan patuh, yang bisa digunakan dalam perdamaian dan agama Islam. Jadi tidak sebatas pada makna agama Islam saja. Bahkan ada sebuah qiraat, kata itu tidak dibaca “silmi” tapi “salami” yang tentu saja memiliki arti berbeda dari pengertian konvensional yang ada selama ini. Memang tidak ada salahnya kita memaknai “silmi” dengan pemaknaan “Islam”, namun yang pasti pada ayat ini tidak hanya terdapat pemahaman tunggal.
Memang ke-kaffah-an dalam agama Islam selalu identik dengan penduplikatan segala tingkah pola kepada masa Muhammad. Zaman awal Islam menjadi rujukan ke-kaffah-an. Tidak semudah itu, apalagi kehidupan sekarang yang tengah dihadapkan pada modernitas yang telah menyusup ke segala sudut kehidupan. Tidak bisa dibayangkan kalau sekarang masih ngotot mengandalkan ke-kaffah-an di tengah arena kehidupan yang tidak sebanding lagi dengan masa awal Islam.
Ada pula yang bukan hanya historis masa lalu yang dijadikan referensi tingkah laku yang kaffah, tapi berpanutan pada kitab suci secara tekstual, harfiah. Mereka yang hanya biasa memahami al-Qur’an hanya secara literal, bukan pada inti yang maksud yang terkandung dalam al-Qur’an itu sendiri.
Banyak kejadian yang dapat kita jadikan contoh dalam kasus ini. Pemaknaan yang sempit terhadap ajaran al-Qur’an akan berakibat fatal. Karena kalau diperhatikan hampir seluruh ketentuan hukum (pidana) Islam yang terdapat dalam al-Qur’an mencerminkan kondisi 14 abad silam yang menjadi ciri khas suku-suku Arab ketika itu. Kalau kita menmandangnya sebagai sesuatu yang mengikat untuk dewasa ini dalam kebanyakan kasus merupakan anakronisme yang patut disesalkan.
Kiranya tidak berlebihan kalau kitab suci dianggap sebagai wacana sejarah yang tidak akan pernah selesai untuk ditafsirkan. Dan kalau al-Qur’an ingin selalu sesuai dengan keadaan zaman, maka ia harus diberi interpretasi yang tidak boleh mau menang sendiri. Karena begitu banyak persoalan yang terkadang tidak dapat dijawab dengan hanya merujuk pada al-Qur’an an sich.
Dan perlu disadari bahwa manusia sekadar pemberi interpretasi terhadap simbol agama dan ketuhanan. Dalam proses penafsiran, terkandung relativitas yang tinggi. Kita boleh dan berhak memberi tafsiran atas teks, dan memberi tafsiran terhadap tafsir, dan seterusnya. []



