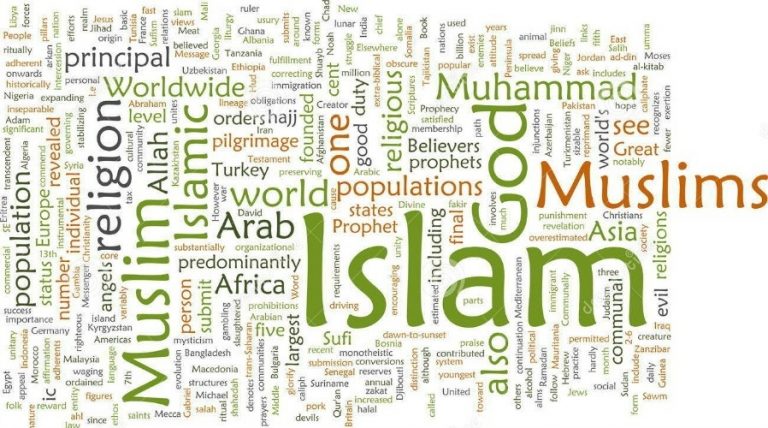
Saat saya menjelaskan proses panjang sejarah kodifikasi al-Qur’an, sejumlah pihak banyak yang kaget. Mereka tahunya hanya produk akhir berupa mushaf al-Qur’an yang sekarang kita pegang. Mereka tidak menyangka bahwa tanda baca, pembagian 30 juz, bahkan ilustrasi di pinggiran mushaf itu tidak ada di jaman Nabi Muhammad SAW.
Begitu juga ketika saya menjelaskan perbedaan tanda berhenti di sebuah potongan ayat akan melahirkan perbedaan pandangan ulama, sebagian menuduh saya mengada-ngada bahkan ada yang menyebut saya professor tolol atau kiai sesat. Saya terpaksa mencantumkan teks asli dari berbagai kitab tafsir klasik kepada mereka untuk membuktikan bahwa perdebatan itu sudah berlangsung sejak ribuan tahun yang lalu. Sejarah perdebatan dan perkembangan pemikiran keislaman dari mulai di jaman Nabi, sahabat, khilafah, sampai sekarang amat menarik untuk ditelusuri.
Di lain kesempatan saya mengulas mengenai sejarah agama di dunia, bahwa sebelum Islam datang, agama Nasrani memiliki sejarah yang amat panjang termasuk konflik saat pemilhan Paus. Agama apapun, apakah itu Islam, Budha atau Nasrani memiliki sejarah yang begitu asyik untuk dipelajari sehingga kita akan paham dinamika internal mereka. Bahkan ekspresi keberagamaan yang diwujudkan dalam bentuk seni baik berupa lukisan, tarian atau bahkan masakan yang berbeda semuanya merupakan elemen penting untuk memahami peradaban dunia. Islam adalah bagian dari peradaban dunia, maka mempelajari dunia adalah hal penting untuk memahami Islam.
Selain pentingnya memahami agama dari sudut sejarah, kita juga akan terpesona melihat agama dari perpektif sosial. Misalnya tutup kepala baik untuk lelaki atau perempuan di masing-masing agama itu berbeda-beda. Lihat saja dari mulai sorban di arab, sampai bentuk kopiah yang berbeda di Turki, Mesir dan Indonesia. Atau bagaimana lebaran di tanah air identik dengan ketupat, mudik dan saling maaf-memaafkan yang berbeda dengan di jazirah Arab.
Lihatlah bagaimana sebagian kalangan marah-marah ketika saya tunjukkan fenomena sosial sebagian permaisuri dan tokoh perempuan Arab yang tidak berhijab syar’i atau foto sebagian syekh yang bersalaman dengan perempuan. Mereka menganggap saya menyebarkan pemahaman yang sesat, padahal saya sedang menunjukkan bagaimana Islam dipraktekkan secara berbeda-beda dalam tataran sosial kemasyarakatan. Saya tidak sedang membahas teks keagamaan, tapi kenyataan sosial. Ini bukan masalah benar atau salah, tapi bagaimana di Arab sekalipun ada fenomena sosial yang sangat dinamis dan menarik untuk kita pelajari.
Memahami agama dalam perspektif politik juga amat menarik. Bagaimana kita harus membaca dengan kritis hadis-hadis yang diriwayatkan setelah masa konflik di era Khalifah Utsman, Ali dan Muawiyah. Karena sejak dulu sampai sekarang bagi para politisi tidak ada cara kampanye yang paling efektif selain mencari justifikasi ayat dan hadis, bukan?! Sebagai contoh dari dulu sampai sekarang akan ada pihak yang berdebat mengenai kesahihan maupun kepalsuan riwayat: “jikalau engkau melihat Muawiyah berdiri di mimbarku, bunuhlah ia!” Sekali lagi, politisasi agama terjadi sejak dulu. Inilah yang harus kita pahami untuk menelaah konflik sunni-syi’ah dalam perspektif politik.
Begitulah, beragam perspektif yang amat dinamis dalam memahami teks keagamaan baik di pesantren, madrasah maupun perguruan tinggi Islam. Cara kita mengkaji Islam menjadi warna-warni. Ini berbeda dengan pola pengajaran di halaqah dan majelis ta’lim yang mengajarkan Islam lewat doktrin semata. Islam dipahami hanya dalam dua bentuk saja: surga atau neraka; sunnah atau bid’ah; benar atau salah; pahala atau dosa; Muslim atau kafir; sah atau batal; dan halal atau haram.
Di luar itu bagi mereka tidak ada pembahasan dari sudut sejarah, budaya, sosial ataupun politik. Maka terkaget-kagetlah sebagian saudara kita itu melihat berbagai perspektif berbeda yang ditawarkan para kiai, cendekiawan maupun budayawan. Mereka kena penyakit kagetan, terus marah-marah dan akhirnya mencaci maki. Sudah tak ada ilmu, tak pula mereka menjaga adab.
Islam yang dipahami sebagai doktrin semata akan terasa kering dari berbagai disiplin ilmu. Islam yang melulu diajarkan dalam bentuk doktrin akan terasa tajam menghakimi yang lain. Sebagai contoh, perdebatan apakah bumi ini bulat atau datar, Islam doktrin akan buru-buru merujuk pada terjemahan ayat Qur’an untuk mengatakan bumi itu datar. Islam dalam perpsektif kajian ilmu akan berkonsultasi dengan para saintis terlebuh dahulu, dan bekal info dari para saintis itulah yang akan membawa perspektif baru dalam memahami ayat Qur’an seputar ini.
Begitu juga soal air yang suci dan menyucikan. Islam doktrin akan mengatakan selama air itu dua kullah maka dianggap suci untuk berwudhu. Secara doktrin fiqh ini memang sah, namun apakah air dua kullah itu secara medis/klinis tidak mengandung bakteri atau kuman? Di sinilah kita perlu perspektif baru mengenai air yang bersih dan layak untuk dikonsumsi. Sah secara fiqh dan bersih secara medis/klinis.
Semoga kita bisa terus belajar dan tidak hanya berhenti di doktrin, tapi terus melengkapi kajian Islam dengan berbagai perspektif ilmu yang sangat kaya dan dinamis. Generasi santri modern adalah mereka yang bisa mengkaji ayat quraniyah dan ayat kauniyah sekaligus. Kita menunggu terus bermunculan para pakar yang menguasai berbagai bidang ilmu keislaman dan ilmu umum agar wawasan kita menjadi luas. Insya Allah!
Tabik,
Nadirsyah Hosen
Rais Syuriah PCI Nahdlatul Ulama Australia-New Zealand dan Dosen Senior Monash Law School



