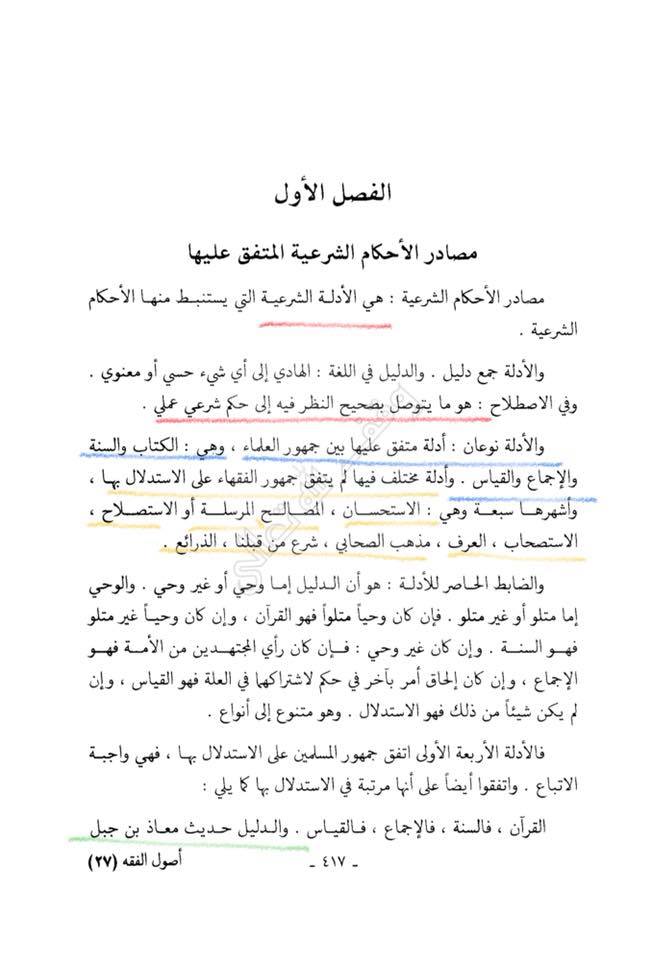
Sering ada yang bertanya: ini mana dalilnya? Di balik pertanyaan ini kerap kali terjadi kesalahpahaman tentang dalil. Dengan merujuk pada kitab Ushul al-Fiqh al-Islamiy karya Syekh Wahbah az-Zuhaili (jilid 1, halaman 417-419) seperti yang saya skrinsut di sini, mari kita kaji ulang dimana letak salah pahamnya.
Para ulama biasanya membahas masalah dalil ini dalam topik mashadir al-ahkam (sumber-sumber hukum) atau al-adillah asy-syar’iyyah (dalil-dalil syara’). Secara umum yang disebut sebagai dalil itu tidak hanya terbatas pada al-Qur’an dan Hadits saja. Dengan demikian, Inilah kesalahan pertama dibalik pertanyaan mana dalilnya, yaitu menganggap seolah dalil itu hanya ayat al-Qur’an dan Hadits.
Syekh Wahbah mengutip Hadits riwayat Sayidina Muaz bin Jabbal. Ketika Muaz Radhiyallah ‘Anhu akan berangkat ke Yaman sebagai utusan Nabi, Nabi bertanya kepada Muaz: “Hai Muaz, jika umat bertanya padamu tentang sesuatu masalah, dalil apa yang engkau gunakan?”
Maka Muaz menjawab: “dengan al-Qur’an”
Nabi bertanya:”Jika tidak terdapat dalam al-Qur’an, bagaimana?”
Maka Muaz menjawab:”dengan sunnahmu”
Nabi bertanya:”Jika tak ada dalam sunnahku dan al-Qur’an?”
Maka Muaz menjawab: “dengan ijithadku”
Nabi menyetujui dan memuji jawaban ini.
Syekh Wahbah juga menjelaskan bagaimana Sayidina Abu Bakar mencari petunjuk di dalam al-Qur’an dan Hadits, tapi begitu tidak diperolehnya maka beliau mengumpulkan para sahabat Nabi lainnya untuk bermusyawarah. Kemudian beliau kumpulkan pendapat para sahabat dan lantas memutuskan perkara berdasarkan hal tersebut. Metode ini juga dilakukan oleh Sayidina Umar dan para sahabat lainnya.
Nah, kesalahpahaman yang kedua adalah cepat-cepat menolak suatu perkara hanya karena tidak terdapat di dalam al-Qur’an dan Hadits. Padahal para sahabat utama seperti Sayidina Abu Bakar dan Sayidina Umar akan mengajak berdiskusi dulu dan bertukar pikiran. Di sinilah peranan ijtihad.
Kesalahan ketiga adalah menolak menghukumi sesuatu perkara berdasarkan akal. Seolah akal itu sesuatu yang tercela. Padahal sekian banyak ayat al-Qur’an meminta kita untuk menggunakan akal pikiran. Syekh Wahbah az-Zuhaili menjelaskan ada pembagian dalil naqli dan dalil aqli. Contoh dalil aqli yang sah digunakan untuk memutus perkara itu qiyas (analogi), pertimbangan kemaslahatan, dan lainnya. Dalil naqli seperti al-Qur’an dan Hadits tidak bisa dipahami kecuali melalui pertimbangan akal, perenungan dan pandangan yang sahih.
Jadi, keliru besar kalau serta-merta menolak penggunaan akal dalam urusan dalil. Ambil contoh, penggunaan qiyas (analogi) jelas bertumpu pada logika. Meski demikian qiyas juga harus bersandar pada petunjuk dalam al-Qur’an atau Hadits karena kita tidak bisa melalukan analogi tanpa ada pokok (ashal) perkaranya terlebih dahulu.
Artinya, dalam kajian metodologi hukum Islam, peranan akal bukannya dilarang digunakan, tapi justru diatur dan dibahas dengan jelas aturan mainnya. Bukan sekadar akal-akalan, bukan pula untuk mengakali, tapi justru digunakan sesuai kaidah yang telah digariskan para ulama.
Al-Qur’an, Hadits, Ijma’ dan Qiyas adalah empat dalil yang disepakati penggunaannya. Sedangkan dalil lainnya seperti mashalih mursalah, istihsan, istishan, qaulus shahabi, ‘urf (adat), dan lainnya itu diperdebatkan penggunaannya oleh para ulama.
Saya hendak tambahkan bahwa selain dalil, ada juga namanya analisa terhadap dalil. Dalam bahasa ushul al-fiqh, ini disebut sebagai istidlal. Contohnya: ayat al-Qur’an memerintahkan kita untuk mengusap kepala saat berwudhu (wamsahu bi ru’usikum). Timbul pertanyaan, berapa banyak yang harus kita basuh. Apa semuanya? Atau sebagian saja?
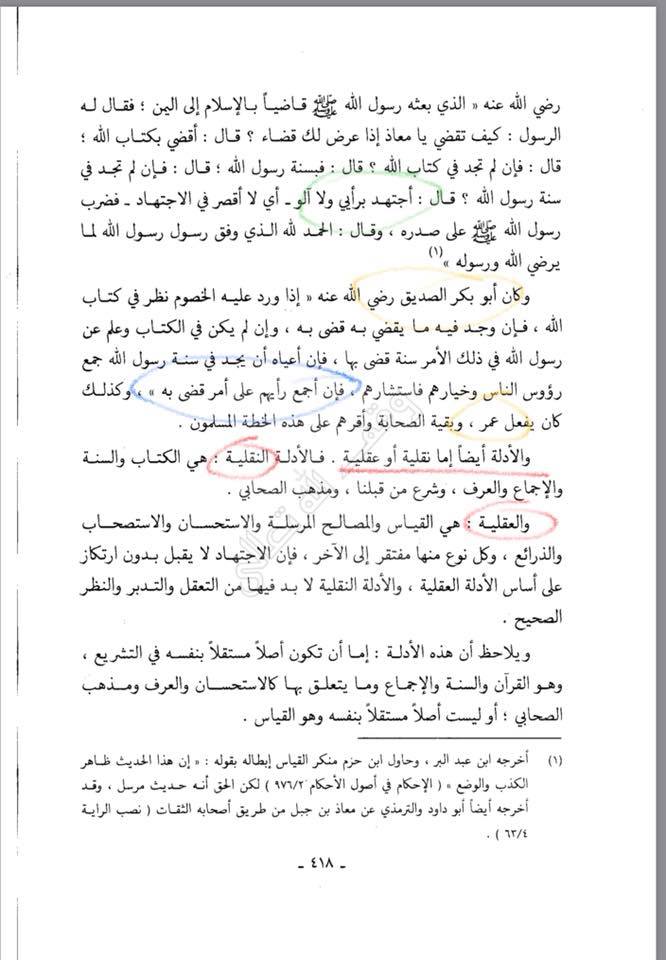
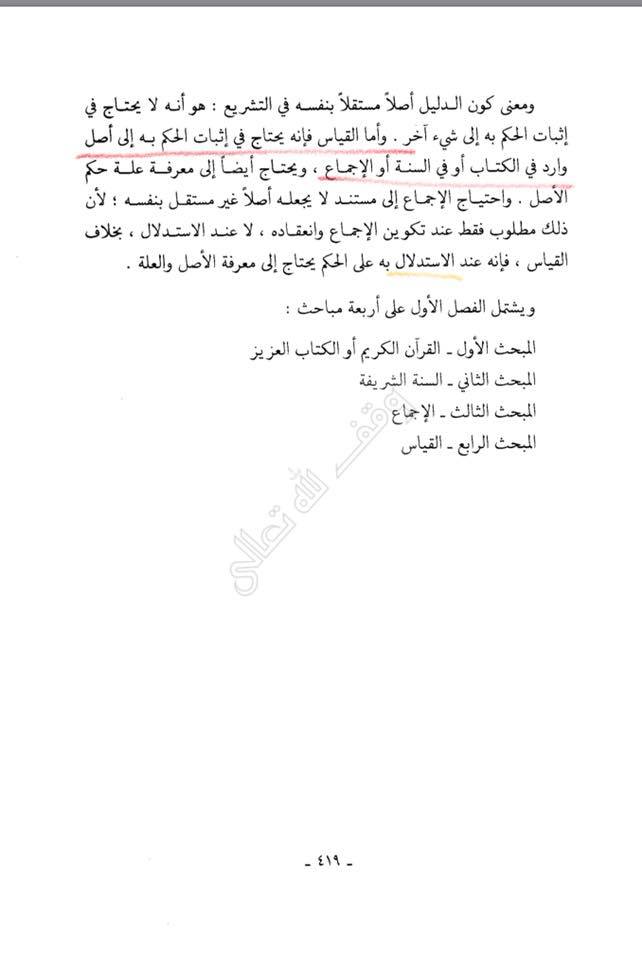
Ayat al-Qur’an tidak menjelaskan dengan pasti batasanya, maka para ulama menganalisa dalil ini. Ditemukanlah huruf “bi” pada ayat tersebut. Ada ulama yang menganalisa bahwa fungsi “bi” pada ayat di atas bermakna sebagian (li tab’id). Ulama lain memberikan analisanya bahwa huruf “bi” bergungsi lil iltishaq (keseluruhan).
Akibat perbedaan analisa terhadap wajh istidlal maka kesimpulannya bisa berbeda-beda meski dalilnya sama. Mazhab Syafi’i dan Hanafi mengatakan cukup sebagian saja kepala yang dibasuh. Sedangkan Maliki dan Hanbali mengatakan harus seluruhnya.
Nah, kesalahan terakhir adalah seringkali dianggap kalau sudah ada dalilnya maka kemudian tidak akan lagi ada perbedaan pendapat. Faktanya, para ulama justru berbeda pendapat akibat menganalisa dalil tersebut. Perbedaan pendapat bukan disebabkan ketiadaan dalil. Dalil ada, analisa berbeda, kesimpulan pun bisa jadi berbeda-beda.
Ringkasnya, salah kaprah soal dalil itu karena gagal memahami bahwa:
1. Dalil itu tidak hanya al-Qur’an dan Hadits.
2. Kalau tidak terdapat petunjuk di dalam al-Qur’an dan Hadits, maka gunakan ijtihad
3. Akal itu juga diakui sebagai dalil. Namanya dalil aqli. Contohnya mayoritas ulama sepakat memakai Qiyas (analogi)
4. Para ulama berbeda pendapat bukan karena tidak ada dalil tapi karena berbeda menganalisa dalil, sehingga kesimpulannya pun bisa berbeda-beda.
Jadi, sebelum kita bertanya, “mana dalilnya?”, pahami terlebih dahulu, paling tidak, keempat point di atas. Biar gak salah kaprah.
Wa Allahu a’lam bis shawab.
Tabik,
Nadirsyah Hosen



