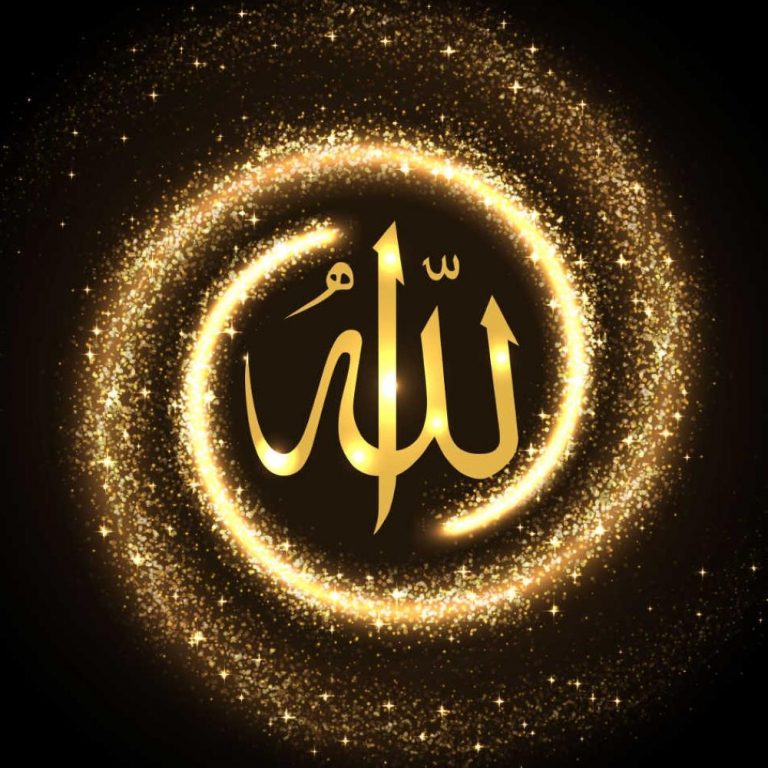
Secara umum, ketika kita mengenal “sesuatu,” maka secara implisit kita telah “menguasai” dan “membatasi” sesuatu dalam kekuasaan pengetahuan kita. Kita juga tahu bahwa tindak “mengetahui” atau “mengenal” mensyaratkan adanya “sesuatu” yang dikenal. Tetapi karena Allah adalah “sesuatu” yang tidak diserupai oleh “sesuatu” yang lain, laysa kamitslihi syai’un (QS. 42:11) maka semua cara untuk mengenal Allah telah tertutup, karena kita tak bisa mengasosiasikannya dengan sesuatu yang kita kenal di dalam dunia fenomena.
Tetapi, jika hanya Allah yang mengenal Dzat Allah, karena tiada sesuatupun yang menyerupai-Nya (walam yakullahu kufuan ahad), bagaimana batasan “nalar-rasio” kita dalam mencoba memahami-Nya?
Manusia, yang eksistensinya tidak mendahului eksistensi Allah—sebab Dia adalah Mahaawal—tak mungkin memiliki gagasan apa pun tentang Dzat Allah. Maka gagasan atau pengetahuan seseorang tentang-Nya “berada” dalam ketidaktahuan tentang Allah; Atau, pengetahuan tentang Allah berada dalam pemusnahan pengetahuan tentang Allah.
Jika pengetahuan tentang “sesuatu” berada dalam “pemusnahan” pengetahuan itu, maka “penemuan” pengetahuan tersebut menjadi bukan penemuan; karena itu para Sufi mengatakan bahwa pengetahuan (manusia) tentang Allah adalah ketidaktahuan dan keheranan.
Nabi bersabda, “Kami mengetahui Engkau hanya sebatas pada apa yang diperintahkan oleh pengetahuan-Mu (tentang Dirimu)” dan “ Ya Rabbi. Tambahkan kepadaku kebingungan (hayran) atas-Mu, yakni bingung atas tiada henti-hentinya tajalli-Mu, dan dari banyaknya perpindahan Zat-Mu dalam segala tindakan dan sifat-Mu.”
Inilah salah satu tafsir dari martabat Ahadiyyah, atau derajat Keesaan Mutlak, di mana semua hal terserap ke dalam Keesaan Mutlak yang tak kenal kegandaan atau kejamakan.
Maka, pada martabat ini, Sifat dan Dzat adalah satu, dan karenanya tidak ada petunjuk apa pun untuk mengenal-Nya; kita tak bisa menggunakan adjektif “ini” atau “itu” kepada-Nya. Subhanahu wa ta’ala amma yashifun (QS. 6: 100), yakni Dia tanpa sifat terbatas yang kita kenakan (nisbahkan) kepada-Nya.
Sesuatu dikenal karena ada sifat-sifat yang menjelaskan eksistensi (keberadaan) sesuatu, tetapi jika sifat terserap dan lenyap dalam eksistensi, maka kita tak bisa mengenal sesuatu itu. Jika kita memaksakan diri untuk menyelidiki keadaan semacam ini terus-menerus, kita bisa menjadi gila.
Maka, berusaha memikirkan Dzat-Nya dilarang keras, seperti sabda Nabi saw: “Janganlah memikirkan Dzat-Nya” (laa tafakkaru fi Dzatihi). Mencoba mendedah melebihi batas ini akan menimbulkan perbedaan, perpecahan dan kekacauan, sebagaimana terjadi dalam 1000 tahun debat panjang dalam teologi Islam.
Marilah kita belajar dari sejarah, agar tak mengulangi kekeliruan yang sama – seperti dikatakan Santayana, “orang yang tak mengambil hikmah dari sejarah, akan terperangkap dlm kekeliruan yg sama.”



