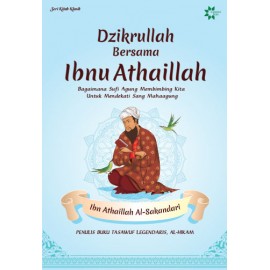
Syaikh Ibnu Athaillah sudah menjadi salah satu nama utama dalam dunia tasawuf. Tapi, jauh sebelum menapaki jalan sebagai seorang sufi, beliau dikenal sebagai seorang faqih (ahli fikih). Beliau menggabungkan antara syariat dan tasawuf. Hal ini sesuai dengan pernyataan salah satu sahabat Nabi saw., Malik bin Anas: “Barang siapa bertasawuf namun tidak bersyariat, sungguh ia telah zindiq (kafir); barang siapa bersyariat namun tidak bertasawuf, sungguh ia telah fasiq; barang siapa menggabungkan keduanya, sungguh ia berlaku benar.”
Syaikh Ibnu Athaillah menjalani syariat dan tasawuf dengan sangat apik. Karena itulah dia dijuluki sebagai sufi agung. Kitab-kitabnya dinilai sebagai klasik. Magnum opusnya, Al-Hikam, senantiasa dikaji, diteliti, dibaca, dan diresapi banyak orang; terutama mereka yang meniti langkah sebagai salik (pejalan). Ada nuansa dan suasana yang Syaikh Ibnu Athaillah hadirkan dalam setiap anggitannya, seakan kita merasakan kehadiran beliau ketika kita membaca setiap kalimat yang tersusun dalam bukunya.
Seperti juga dalam buku ini. Syaikh Ibnu Athaillah menjuduli buku ini dengan Miftah al-Falah wa Mishbah al-Arwah fi Dzikrillah al-Karimi al-Fattah (Kunci Kesuksesan dan Lentera Jiwa-jiwa dengan Berzikir kepada Allah Yang Mahamulia lagi Maha Pembuka). Karena itulah redaksi Lentera Hati memberi judul buku ini dalam bahasa Indonesia dengan Dzikrullah Bersama Ibnu Athaillah.[1] Dalam buku ini Syaikh Ibnu Athaillah seperti membimbing kita bagaimana kita mendekati Allah Sang Maha Agung.
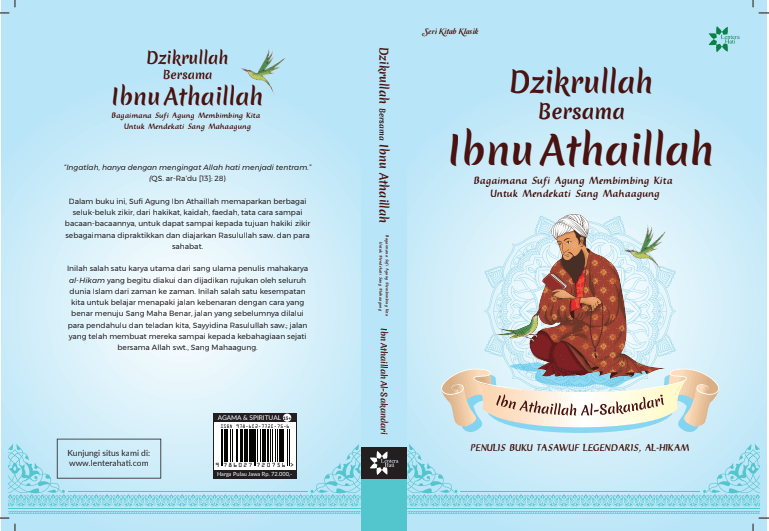
Bimbingan yang beliau berikan kepada kita amat sangat teliti dan telaten. Jika diibaratkan, dalam buku ini Syaikh Ibnu Athaillah seperti sedang memberikan kunci kepada kita untuk memasuki gerbang-gerbang kearifan. Tak sekadar memberikan kunci, beliau juga menuntun kita untuk memasuki kamar-kamar dan menggapai tangga-tangga untuk kita bisa sampai ke tujuan kita. Tujuan kita yang paling ujung adalah mendapatkan gerujukan rahmat dari Allah swt.
Sebagaimana kita ketahui bersama, tangga yang paling dasar haruslah yang paling kuat. Karena itu, dalam buku ini Syaikh memulainya dengan membahas zikir dari sisi definisi sampai membahas soal hati alias jiwa.
Kondisi jiwa ini menjadi pembahasan penting. Zikir merupakan lentera yang akan menerangi hati. Agar hati senantiasa terang, tak berubah menjadi gelap. Dalam bahasa Arab, hati yang gelap disebut sebagai zhulm. Tak aneh bila kemudian orang yang berlaku kejam dan mengabaikan nurani disebut sebagai zalim. Karena hatinya gelap.
Dalam sejarah Islam kehadiran Nabi Muhammad yang membawa Islam disebut sebagai masa peralihan dari kegelapan menuju cahaya (min al-zhulumâti ila al-nûr). Ungkapan ini merupakan kiasan untuk menyebut cahaya Islam yang menerangi hati orang-orang Islam saat itu. Dan, mereka yang kerap berzikir mengingat Allah insya Allah hatinya senantiasa terang lagi tenang. Inilah di antara kandungan QS. al-Ra’du [13]: 28.
Jika memang mengingat Allah menjadi tenang, kenapa di QS. al-Anfâl [8]: 2 disebutkan: “Orang-orang mukmin hanyalah mereka yang apabila disebut (nama) Allah, gemetarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya, ia menambah iman mereka dan kepada Tuhan Pemelihara mereka, mereka berserah diri.”
Gemetar dan tenang merupakan dua sifat berbeda. Kalau hati gemetar, tentu tidak akan tenang. Lalu, apa maksudnya? Dalam hal ini, mufasir klasik Imam Fakhruddin al-Razi atau dikenal sebagai Imam al-Razi (544-604 H) dalam Mafâtîh al-Ghaib menyatakan bahwa hati gemetar ketika mengingat maksiat, dan hati menjadi tenang ketika hati hibuk dengan ketaatan. Karena itu, ayat 29 surat al-Ra’du menjadi dalam pembahasan ini: “Orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal saleh, bagi mereka (kehidupan yang penuh) kebahagiaan (di dunia dan akhirat) dan (bagi mereka pula) tempat kembali yang baik (surga).”
Sibuk dengan ketaatan bermakna positif. Hal yang positif niscaya melahirkan kegiatan positif pula. Ayat ini jelas mengisyaratkan bahwa seorang yang beriman mewujudkan zikir kepada Allah dalam kesehariannya melalui mengerjakan amal saleh, kebaikan, kebaikan, dan kebaikan. Tiada lain. Jika kita senantiasa berzikir kepada Allah Yang Mahaagung tapi masih melakukan keburukan, sebaiknya kita perlu bertanya secara mendasar: betulkah Allah Yang Mahaagung yang kita ingat?
Tentu, pengantar ini bukan hendak meringkas atau memangkas pembahasan yang sangat baik dari sang sufi agung dalam buku ini. Karena itu, kami mencukupkan sampai di sini. Harapan kami, semoga Allah meridai ikhtiar ini dan memberikan keberkahan dalam kehidupan kita.
Amin ya rabbal ‘alamin, ya mujib al-sailin.
[1] Redaksi menggunakan diksi “dzikr” dengan ditulis miring untuk memudahkan pemahaman; “dzikrullah” bermakna zikir kepada Allah/mengingat Allah. Kami menggunakannya untuk judul saja. Sementara Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) menulis “zikir” untuk maksud yang sama, dan kami menggunakan diksi ini di sepanjang buku.
Tulisan ini adalah pengantar buku ini dan untuk lebih lengkapnya terkait buku ini atau buku Profesor Quraish Shihab, bisa didapatkan di Penerbit Lentera Hati



